Cerpen Hary B Kori’un
SEBENARNYA SAYA tidak pernah yakin tentang cerita Yusrizal, teman dekat yang tahu bagaimana budaya Minangkabau dilahirkan, dan selalu mengatakan bahwa di tanah itu wanita begitu mendapat kehormatan dan dikultuskan. Katanya, negeri Minangkabau di zaman dahulu kala, diperintah oleh seorang ratu yang bernama Bundo Kanduang di Istana Pagaruyung (saat ini di Batusangkar). Sang Ratu, menurut ceritanya lagi, tidak pernah menikah, tetapi bisa melahirkan anak hanya karena meminum air kelapa yang –tanpa sepengetahuannya—telah disabda oleh dewa.
Cerita Yusrizal pun lebih panjang lagi. Siti Nurbaya, katanya, adalah salah satu contoh betapa wanita Minang ditakdirkan untuk menjadi terkenal. “Kamu tahu, meskipun hanya sebuah fiksi Marah Rusli, tetapi Siti Nurbaya dianggap hidup, dibuatkan makamnya berdekatan dengan kekasihnya, Samsul Bahri, dan macam-macam lagi yang menggambarkan kehidupannya yang sangat terkenal itu. Kamu tahu ‘kan, dermaga Teluk Bayur tempat Siti Nurbaya melepas Syamsul ke Batavia dalam suasana yang amat romantik dan dramatis? Kamu besok kuajak ke sana…”
Benar. Saya diajak ke Teluk Bayur. Tetapi saya tidak melihat bentuk kapal yang dalam cerita digambarkan sangat megah. Yang saya lihat di sana hanya kapal-kapal barang, perahu-perahu nelayan dan satu kapal Kambuna yang sedang berlabuh. “Masih banyak orang Padang yang pergi ke Jakarta naik kapal, Yus?” tanya saya.
Yusrizal diam. Kemudian katanya, “Itulah yang aneh. Sangat jarang sekarang. Bahkan jadwal keberangkatan pun hanya sekali sepekan. Itu pun tidak pasti. Mereka tidak menghormati sejarah.”
Sejarah? Saya tertawa dalam hati. Benarkah Siti Nurbaya memang pernah benar-benar hidup sehingga saya harus melihat kuburannya di Gunung Padang? Kata teman-teman saya –dan juga dari buku-buku yang saya baca— Siti Nurbaya hanya tokoh fiktif, begitu juga dengan Bundo Kanduang atau dongeng Malin Kundang. Namun, ketika Yusrizal bercerita meyakinkan tentang kehebatan wanita Minangkabau, saya menjadi ragu. “Bayangkan. Tidak ada di dunia ini sistem matrilinial dipakai oleh sebuah etnis manapun. Hanya di sini…”
Saya mendengarnya dengan tersenyum. Maklumlah, saya tidak tahu banyak tentang Minangkabau.
Tetapi ketika saya tanya mengapa di Minangkabau ada seorang ibu yang rela menjadikan anaknya sebagai batu seperti dalam dongeng Malin Kundang --Saya juga diajaknya ke Pantai Air Manis, tempat kapal Malin Kundang pecah karena menabrak karang dan kemudian menjadi batu--, Yusrizal bingung. “Kalau anaknya keterlaluan, wanita manapun akan rela menghilangkan kasih sayangnya, termasuk ibu Maling Kundang,” jawabnya.
“Lho, bukankah kasih sayang ibu sepanjang jalan dan tak berbatas?”
“Semua manusia punya batas kesabaran. Dan tidak ada manusia yang sempurna,” jawabannya diplomatis lagi. Saya diam, berusaha mengerti.
Dalam saat-saat seperti ini, mengingat cerita Yusrizal ketika saya punya kesempatan ke Padang –dia selalu mengatakan bahwa Padang hanya sebuah kota, bukan sebutan resmi untuk etnis Minangkabau karena orang luar Minang selalu mengatakan orang Minang adalah orang Padang—dan diajak keliling Sumbar, memang sangat menyenangkan. Terutama pada saat-saat saya begitu kangen kepada Vera Olivia Danea, gadis cerdas yang selalu mengingatkan saya kepada sebuah wilayah bernama Kayutanam, tidak jauh dari Lembah Anai di lereng Gunung Singgalang.
Saya juga sering berpikir, benarkah Olivia benar-benar hidup dan nyata seperti yang saya jumpai hampir satu pekan selama acara itu? Sebab, jika saya ingat-ingat cerita Yusrizal tentang wanita Minangkabau yang banyak fiksinya, saya menjadi ketakutan: jangan-jangan Olivia hanya sebuah fiksi. Atau, jangan-jangan perjalanan saya ke ranah Minang itu juga hanya sebuah fiksi atau mimpi. Keraguan itu menjadi menguat, sebab hingga hari ini setiap saya berkirim surat ke alamat yang dia berikan, tidak pernah datang balasannya. Saya juga ingin dengar suaranya, tetapi dulu ketika saya meminta nomor teleponnya, dia bilang tidak punya. Ingin kembali ke sana, saya menjadi serba ragu. Jangan-jangan… Ya, jangan-jangan Olivia memang hanya sebuah fiksi. Bahkan beberapa kali saya menghubungi Yusrizal dan menanyakan tentang Olivia, dia juga tidak pernah bertemu dan tidak tahu di mana rumahnya. Padahal jelas-jelas tertulis: Jl. Bagindo Azis Chan nomor 14, depan Lapangan Imam Bonjol, Padang.
Jangan-jangan. Ah, tidak. Saya pikir otak saya masih kompak. Tetapi…
SAYA TIDAK ingin Olivia hanya sebuah fiksi atau seperti dongeng-dongeng berbau mistis tentang wanita Minang yang memiliki kekuatan luar biasa seperti cerita Yusrizal itu. Sebab, ketika saya berada di Kayutanam Olivia adalah sosok hidup yang tidak akan pernah saya lupakan sampai kapan pun.
Waktu itu, saya begitu terkejut ketika tiba-tiba ia duduk di samping kanan saya ketika saya makan, dan ia mengatakan bahwa ia hanya ingin duduk, tidak hendak makan. Dia memang cantik dengan rambut sebahu dengan potongan tubuhnya yang ramping dan tinggi.
“Dari Jakarta?” ia bertanya.
Saya menghentikan makan sebentar dan menoleh kepadanya. “Tahu dari mana?”
“Tampangmu mirip orang Jakarta…” Saya membatin, orang Jakarta memang seperti apa?
Saya tersenyum, kemudian benar-benar menghentikan makan malam pertama di acara teresebut. Saya tertarik untuk bercakap-cakap panjang dengannya. Maklumlah, acara seperti ini sepi dengan perempuan cantik. Banyak perempuan yang datang, tetapi rata-rata mereka sudah berumur. Saya tidak suka gadis yang sudah berumur.
“Dari Padang?”
Dia mengangguk, kemudian memperlihatkan tanda pengenalnya. “Sejak pagi tadi ingin sekali saya duduk di sini,” katanya datar.
“Maksudmu, meja ini kesukaanmu?”
“Iya.”
“Oh, maaf. Saya tidak sengaja.”
“Tidak apa-apa. Saya memang sedang butuh teman.”
Ia kemudian mengajak saya berjalan-jalan keliling lokasi. Kami nonton teater anak-anak Unand yang dilatih Wisran Hadi sebentar, kemudian duduk di tempat orang-orang membaca puisi. Dia ikut membaca puisi dan saya memotretnya –hasilnya terpampang di pojok kamar saya dalam ukuran besar yang saya bingkai dengan rapi. Hampir tengah malam, ia mengajak naik ke bukit di belakang gedung INS. Di puncak bukit itu terdapat tugu kecil yang tingginya kira-kira tiga meter. Katanya, tugu itu dibuat untuk menandai hancurnya tempat pendidikan terkenal itu ketika dibumihanguskan tentara republik agar tidak dimanfaatkan oleh Belanda yang kembali ingin berkuasa.
“Tempat ini sangat bersejarah,” katanya antusias. “Banyak orang Minangkabau yang kemudian menjadi orang besar, bersekolah di sini. Logika dan ketrampilan serta ketaatan diajarkan. Saya beruntung pernah sekolah di sini.” Dia seperti berpromosi dan saya sering hanya mengangguk. Dari bukit itu, terlihat INS seperti pasar malam, karena hingga menjelang fajar, banyak orang-orang yang tidak mau tidur.
***
PAGI-PAGI SEKALI ia sudah berada di depan penginapan saya ketika saya akan mandi. Saya tersenyum dan kemudian mengatakan padanya bahwa saya lebih baik mandi dulu. Ia tersenyum sambil mengangguk.
Ia mengajak ke Bukittinggi. Saya mau saja meski acara pembukaan sehari sebelumnya dilangsungkan di sana. “Bukittinggi adalah kota paling unik di dunia,” katanya sambil tertawa ketika kami sampai di sana. Dia berpromosi lagi.
“Berapa kamu dibayar untuk promosi ini?” saya berkelakar.
“Cukup untuk makan dan minum sebulan,” katanya masih sambil tertawa. “Kamu lucu.”
Saya memandangnya tapa kedip. Olivia sangat cantik. Wajahnya seperti perpaduan konservatifisme Jawa dan agresifitas Barat. Kulitnya bersih, seperti susu. Tatap matanya tajam dan bening. Hidungnya tidak terlalu mancung dan bibirnya memerah: terlihat garis-garis kecantikannya. Tatap matanya tajam dan bening, namun terlihat luruh kadang-kadang.
“Kamu sudah pernah menikah?” tiba-tiba saja pertanyaan itu muncul dari mulut saya dan saya terlambat menyesalinya.
Ia tidak terkejut. “Siapa yang berani menikah dalam kondisi seperti ini? Susu menjadi mahal dan seluruh biaya hidup sangat tinggi. Dengan apa anak-anak nanti bisa tumbuh sehat dan bergizi?”
Kami berada di bibir Ngarai Sianok waktu itu.
“Susu ibu dan segala kasih sayangnya lebih dari cukup jika dibandingkan dengan semua yang serba instant. Anak-anak akan terlindungi karena ibunya sangat memperhatikannya. Alat mainan modern hanya merangsang anak untuk tumbuh menjadi kerdil dan tidak kreatif. Apakah betul seperti itu? Saya tidak terlalu banyak tahu, hanya membaca beberapa buku saja. Hahaa…”
“Kuno kamu. Dari zaman dulu orang selalu mengatakan bahwa sentuhan wanita bisa mengalahkan segalanya, baik untuk anak-anaknya maupun suaminya. Padahal itu hanya kalimat lain bagi laki-laki untuk menghilangkan hak perempuan untuk hidup sejajar dengan wajar. Kamu tahu? Di sini wanita adalah simbol kekuatan. Wanita-wanita perkasa lahir di sini, bukan wanita cengeng seperti Kartini yang dijadikan simbol emansipasi wanita Indonesia. Saya tidak setuju itu.”
Ternyata dia selalu marah jika ada orang yang menempatkan wanita tidak seperti yang ada dalam keinginannya. Katanya lagi, sebenarnya orang hidup saling membutuhkan dan tidak ada kasta yang membatasinya. Tetapi, “Banyak laki-laki yang selalu memperlakukan wanita seenak perutnya.” Dia emosi.
Malam harinya ketika sampai lagi di Kayutanam, ia bercerita tentang ibunya. Ibunya lahir sebagai gadis Pariaman yang terkungkung dengan tetek-bengek adat. “Ibu harus menikah dengan ayah. Adat kami, laki-laki dijemput oleh wanita dengan uang, emas atau benda-benda berharga lainnya. Hal itu membuat laki-laki besar kepala meski sebenarnya yang memiliki kekuasaan di rumah adalah perempuan. Tetapi, apakah kehidupan sebuah perkawinan hanya untuk saling menguasai satu dan yang lainnya? Lelaki cenderung poligami. Ayah kemudian menikah lagi dengan dua wanita lain selain ibu. Tahu apa yang dirasakan oleh ibu? Hatinya pedih. Tercabik. Tetapi ia tidak bisa berontak karena tatanan adat memperbolehkan. Ibu kemudian membesarkan saya dan dua adik saya tanpa peduli ayah. Ayah sibuk dengan istri-istri mudanya dan setiap malam selalu keluar masuk rumah, seperti seorang gigolo yang mendapat banyak kontrak. Tetapi ibu tidak menangis atau mengeluh. Dia tetap berhasil meski tanpa laki-laki itu…”
Yang terjadi kemudian, di balik kecerdasannya yang luar biasa –kadang dengan referensi yang entah diambil dari buku apa—dia melihat laki-laki dari sisi negatif. Katanya, ibunya meninggal dalam usia muda, dan ayahnya menikah lagi dengan gadis belia seusianya. “Ayah sekarang masih hidup, dan hanya mencari kepuasaan dari istri-istrinya setiap malam. Pagi sampai sore ia berjudi di lapau. Ia seperti pengemis, meminta nafkah lahir dan batin dari istri-istrinya. Saya akan selalu melihat laki-laki bukan dari sisi yang benar. Karena laki-laki telah membuat ibu mati dengan hati patah meski itu tidak pernah diperlihatkannya…”
Saya diciumnya ketika malam terakhir dan kami akan berpisah. “Saya tidak tahu bagaimana menilai kamu. Mungkin kamu sebuah kekecualian,” bisiknya malam itu.
SURAT YUSRIZAL datang beberapa saat setelah saya shalat Zuhur. Katanya: Kabarmu tentu baik-baik saja, Bung, aku di Padang juga begitu. Kali ini mungkin mungkin pendek saja aku menulis surat padamu. Aku hanya ingin bercerita sedikit, barangkali kamu masih mau membacanya. Beberapa hari yang lalu aku pergi ke Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) di Padangpanjang –tidak jauh dari Kayutanam—untuk mencari referensi tentang artikel yang dulu kamu pesan. Secara tidak sengaja, aku menemukan kliping sebuah koran tentang kematian seorang gadis berusia 28 tahun, lima tahun lampau, di kelokan dekat air terjun Lemban Anai. Dia seorang dosen di Fakultas Sastra Unand yang kemudian memilih mengajar di INS Kayutanam. Katanya, ia bosan di kota dan ingin mengabdi di sekolah tua itu.
Dalam berita itu ditulis mobil mewah yang dikemudikannya ditabrak truk pengangkut batubara dan remuk. Bahkan tubuhnya pun tidak ditemukan utuh. Aku terkejut Bung, karena nama wanita itu persis dengan nama wanita yang kamu kenal di Kayutanam, yang hingga kini aku tak pernah tahu wajahnya serupa apa. Mungkin juga kebetulan, ketika alamatnya yang kamu ingin aku mencarinya itu kutemukan, pemilik rumah itu langsung terkejut dan mengatakan tidak tahu…
Saya mengambil rokok beberapa batang, membakarnya dan kemudian menghisapnya. Hati saya kalut, padahal saya ingin meyakinkan bahwa cerita Yusrizal tentang wanita Minangkabau yang sering berbau mistis dan fiktif, adalah sebuah kebohongan. Juga ceritanya dalam surat itu. Tidak mungkin saya meragukan pikiran normal saya. Tentang perkenalan dengan Vera Olivia Danea, kecerdasannya, semua ceritanya tentang laki-laki dan seluruh perjalanan kami yang hanya sepekan itu.
Saya tetap tidak percaya dengan segala mitologi wanita Minangkabau itu. Karena saya ingin Olivia bukan dongengan berbau mistis seperti yang sering diceritakan Yusrizal serta banyak literatur yang saya baca itu. Saya tetap ingin bertemu dengan Olivia Danea.***
Padang, Januari 1999-Pekanbaru Februari 2005
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






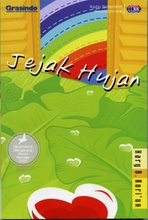

No comments:
Post a Comment