Cerpen Hary B Kori’un
AKU masih menunggunya di sini; orang-orang berjalan kaki lalu-lalang, gedung-gedung tinggi, pohon-pohon yang teduh di sebuah kota yang dibangun dengan pikiran maju. Menunggunya, barangkali bukanlah sebuah pekerjaan yang berat bagiku. Burung-burung tetap beterbangan dan hinggap di dekatku: di depan sebuah plaza di pusat kota. Di sekitarku, banyak orang duduk-duduk sambil bercanda dengan teman-temannya, atau pasangan kekasih yang saling berpelukan, juga seorang ibu yang berkejaran dengan anaknya dan ayahnya memandang dengan senyuman, duduk di bangku tidak jauh dari situ.
Memang, menunggunya bukanlah pekerjaan yang sulit bagiku. Aku sudah sering menunggu kedatangannya di manapun kami berjanji untuk berjumpa; di sebuah kafe di pinggir kotaku, di sebuah hotel di pusat kota di kotanya, sebuah cottage di pinggir sebuah danau di Sumatera Barat, di coffeeshop di pinggir jalan di sebuah senja yang basah saat gerimis di Jogja, atau seperti saat ini, di depan sebuah plaza di negri asing yang membuat aku memang merasa asing. Tetapi dengan harapan bisa bertemu dengannya, aku menjadi sabar dan percaya bahwa ketika bertemu dengannya nanti, semuanya akan lebih baik dan semua kepenatan menunggunya akan hilang berganti dengan beribu rasa yang indah. Dia memang membuat semuanya menjadi indah dalam kehidupanku.
Seorang gadis kecil berkulit kuning bersih dengan mata sipit dan rambut lurus, memandangku sambil tersenyum seakan dia ingin bertanya, untuk apa aku berada di sini menunggunya. Dia tetap tersenyum sambil berdiri di hadapanku dan aku membalas senyumnya. Aku tahu, dia mungkin tidak tahu apa yang kukatakan, namun perasaan barangkali tidak memerlukan bahasa ucap yang verbal. Ingin kukatakan padanya bahwa aku sedang menunggu seseorang yang selama ini membuat aku memiliki semangat hidup yang berlebih, kekuatan yang dahsyat yang membuat aku ingin hidup lebih lama lagi. Sejak mengenalnya, aku merasa dunia ini terang, semua menjadi lebih baik dan penuh warna.
Seorang wanita cantik, mungkin umurnya sebaya denganku, datang dan mengatakan sesuatu dengan bahasa Inggris beraksen Melayu, dia minta maaf kalau anaknya mengganggu kesendirianku. Kukatakan bahwa aku tidak merasa terganggu. Perempuan berkulit kuning itu memandangku dan kemudian tersenyum sambil mengangguk. Setelah itu, keduanya berlalu. Aku melihat lalu-lalang orang berjalan kaki di trotoar begitu ramai. Dan aku tetap menunggunya, menunggu untuk sebuah pertemuan yang dia janjikan dulu.
“Tunggulah aku di Orchard Road. Di depan Plaza Singapura, tidak jauh dari Istana Park dan Takashimaya, ada tempat duduk di antara pohon-pohon teduh. Banyak orang duduk di sana, engkau akan melihat burung-burung dengan bebas beterbangan. Bayangkan, di sebuah kota yang besar dan modern itu, burung-burung bebas beterbangan dari satu pohon ke pohon lainnya, dan kadang datang kepadamu. Di negri kita, engkau masih bisa melihat burung gagak bebas terbang? Burung gagak yang selalu mengantarkan aroma kematian itu, bebas hidup di sana, juga burung jalak dari segala jenis. Tunggulah aku di sana...” katanya dalam e-mail.
“Kita bukan orang-orang bebas seperti burung-burung itu, kan? Mestinya kita tidak berjanji di tempat yang sangat jauh seperti itu,” jawabku.
Beberapa saat setelah itu, aku membaca jawabannya. “Dari awal kita sudah tahu, kita memang bukan orang bebas karena kita punya komitmen dengan orang lain dalam sebuah ikatan. Tetapi aku mencintaimu...”
“Mestinya kita tidak melakukan ini, kita menyakiti orang-orang yang pernah kita cintai...” kali ini aku mengirimkannya lewat sms.
“Sejak kita bertemu, aku merasa menjadi remaja lagi dengan segala vitalitasnya....”
“Tetapi semestinya kita tidak melakukannya.”
“Tetapi aku mencintaimu...”
“Bodohnya, aku juga mencintaimu, meski aku selalu risau...”
Aku memang selalu menunggunya di tempat-tempat di mana kami berjanji bertemu. Seperti angin, dia selalu datang seperti yang direncanakan dan tepat waktu. Dia mengatakan, sangat bahagia bisa bertemu denganku. Katanya, dia suka melihat ceruk di antara dua tulang di leher bawahku. “Setiap aku rindu padamu, aku selalu mengingat tahi lalatmu ini,” katanya sambil meraba ceruk itu. Aku memang memiliki tahi lalat yang terlihat menonjol di sana. “Bisa bertemu denganmu saja sudah sebuah anugerah yang besar bagiku, meski harus melewati laut dan pulau-pulau, dan jauh seperti ini...”
Suatu waktu, dia mengatakan bahwa di saat pikirannya suntuk, dengan mengingatku semuanya akan menjadi lebih baik. “Aku muak dengan banyak hal. Orang-orang munafik, bicara masalah keadilan di sembarang tempat, sementara dia menginjak kaki orang-orang yang semestinya mendapatkan kepastian apa yang mereka ucapkan itu. Mereka menghisap darah, dan menjadikannya kekuatan untuk melakukan penghisapan yang lain...” katanya yang membuatku kadang bingung. Dia selalu bicara tentang kebebasan berpikir, kemakmuran bersama, ide-ide pembebasan yang kadang membuatku ngeri.
“Aku bukan orang yang paham dengan semua itu...”
“Tetapi kamu telah membuat aku yakin bahwa kebaikan yang sedang kami perjuangkan akan tercapai.”
“Kamu sedang berjuang untuk apa?”
“Untuk kebaikan semua orang.”
“Jangan-jangan kamu anggota jaringan teroris yang dicari itu...” kataku sambil bercanda.
Dia hanya tersenyum seulas. “Teroris berjuang untuk sesuatu yang tak pasti, aku berjuang untuk kebaikan. Seandainya aku teroris, kamu masih mau bertemu denganku?”
Entah mengapa, tiba-tiba aku memeluknya dari belakang dan mengatakan bahwa aku ingin tetap mencintainya, meskipun dia seorang pembunuh bayaran dan aku adalah targetnya saat ini. “Aku akan tetap mencintaimu, meski di belakang punggungmu kau simpan belati atau pistol...”
“Itu mirip kata-kata Khalil Gibran...”
“Aku suka Gibran...”
“Dia bukan contoh yang baik seseorang untuk memperbaiki keadaan. Dia hanya bisa bersyair dan menangisi nasib. Laki-laki harus melakukan sesuatu lebih dari sekedar menangis dan bersyair...”
“Tetapi syair-syairnya menjelaskan bahwa dia seorang lelaki romantis, tabah, baik hati...”
“Kebaikan tidak bisa dilihat dari syair. Banyak penyair yang suka membunuh...”
“O ya, siapa?”
Dia hanya tersenyum sebelum mengatakan bahwa dia sangat mencintaiku dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Aku sudah lupa entah berapa kali dia mengatakan itu di setiap pertemuan kami, karena setelah itu aku baru sadar ketika terbangun di pagi hari saat sinar matahari mulai menyusup lewat sela-sela gorden dan sering aku sudah mendapatinya sedang berada di depan note book yang memang selalu dibawanya ke mana dia pergi.
“Sedang membuat syair cinta untukku?” kataku sambil mendekatinya.
“Aku tidak bisa membuat syair...”
“Sedang menulis apa?”
“Artikel untuk mencerahkan manusia...”
“Untuk dikirim ke koran mana?”
“Di manapun yang mau memuatnya, di manapun orang mau membacanya...”
Kemudian aku membaca sejenak. Aku tak kenal nama-nama yang dikutipnya seperti Ayatullah Khomeini, Ali Syariati, Mohammed Arkoun dan sederetan nama lainnya yang tak pernah kutemui di buku-buku atau diktat manajemen yang kudapatkan ketika masih kuliah dulu. Ketika kutanya siapa mereka itu, dia mengatakan bahwa orang-orang itu adalah pemikir pembebasan muslim yang pikirannya sangat berpengaruh. Setelah itu aku tidak bertanya lagi dan masuk ke kamar mandi. Siraman air pada tubuhku membuat semuanya segar dan indah. Aku benar-benar mencintainya yang terbebas dari apapun.
Suatu waktu, dalam pertemuan lain, kata-katanya terasa perih dan pesimis. “Esok atau kapan, jika engkau melihat fotoku di koran sedang dikerubungi lalat di tong sampah atau parit, katakan kepada penulis beritanya, atau fotografernya, bahwa aku memang pantas mati seperti itu...”
“Kamu sedang bicara tentang apa?”
“Tentang cinta dan kematian...”
“Cinta untuk siapa dan kematian bagi siapa?”
“Cinta untukmu dan kematian bagiku...”
“Jangan bicara seperti itu, aku tak ingin kamu mati...” Aku menangis.
“Kadang-kadang, aku ingin hanya berpikir bagaimana merasakan mati...”
Aku memang sering tidak mengerti pikiran-pikirannya, juga keinginan-keinginannya. Dia bicara tentang keadilan yang carut-marut, kebodohan dan kemiskinan yang tetap menjadi hal yang dominan dan jadi bahan proposal, juga anak-anak yang mati karena kolera dan malaria, padahal pemerintah memiliki uang untuk membangun rumah sakit dan membayar dokter, juga membuat sekolah-sekolah dan menggaji guru dengan layak. “Tetapi semua tidak dilakukan. Orang-orang banyak yang hanya berpikir tentang dirinya tanpa berpikir bahwa banyak orang di luar lingkupnya memerlukan kehidupan yang lebih layak dari hanya sekedar bisa makan...”
Di setiap pertemuan kami, dia memang selalu bercerita tentang semua itu, kadang sambil memandang kosong ke depan, dengan menangis sesenggukan dan kemudian memelukku dengan sangat erat, kadang juga dengan kemarahan yang sangat yang membuat giginya gemerutuk dan tatapan matanya setajam harimau.
Hingga senja, aku masih duduk di bangku di depan Plaza Singapura itu. Orang-orang berjalan bergegas; banyak yang berpasangan dengan bergandeng tangan atau berjalan sambil berpelukan mesra, juga ada yang sendirian tetapi menikmati dengan riang. Mereka bisa bebas seperti itu, sementara di setiap pertemuan kami, kami harus melihat kiri-kanan apakah ada orang yang kami kenal. Di kota-kota di setiap kami berjumpa, tidak pernah kami bisa bebas berjalan bergandengan tangan atau berpelukan atau bahkan berciuman seperti banyak pasangan muda-mudi di sini. Aku baru sadar, kami sudah bukan remaja lagi. Tetapi di sini, meski banyak yang bukan remaja lagi, tetapi mereka juga bisa bebas melakukan seperti yang dilakukan anak-anak muda, juga seperti burung-burung yang hinggap dari satu pohon ke pohon lain di sebuah negeri kota yang sangat maju ini. Aku iri kepada mereka, juga pada burung-burung itu. Tetapi, burung gagak itu, selalu lalu-lalang dengan suara koaknya, terbang dari satu pohon ke pohon lain, tidak jauh dari tempat dudukku.
Hari sudah malam dan suasana di depan plaza itu tetap ramai, namun aku mulai merasa kesepian, meski aku yakin dia akan datang. Ketika menyeberang dari Batam pagi tadi, ada rasa sumringah dalam dadaku karena akan bertemu kembali dengannya setelah sekian waktu kami tak saling jumpa. Aku selalu rindu padanya, meskipun aku sadar, kami bukan lagi orang-orang bebas. Adakah ini benar-benar cinta?
Hampir tengah malam ketika toko-toko dan pusat shopping mulai menutup diri, aku berjalan gontai, ke hotel yang disebutkannya dan ketika sampai di sini pagi tadi, aku langsung ke sana dan memesan kamar. Aku hampir patah arang, tetapi aku tetap yakin dia akan datang karena sebelumnya dia tidak pernah mengingkari janji untuk bertemu, barang sekalipun. Tapi, suara gagak berkoak itu tetap terdengar di telingaku, entah di pohon mana dia hinggap.
Aku jadi serba resah. Aku ingat kata-kata terakhirnya ketika dia menyebut tentang kematian itu; tentang rasa pesimisnya memandang hidup dan semua paradoks yang ada di kepalanya. Keresahan itu semakin membuatku gamang ketika kuhidupkan televisi dan sebuah berita menjelaskan tentang meledaknya sebuah bom mobil di depan sebuah kedutaan asing di Jakarta yang membuat puluhan gedung di sekitarnya ikut rusak. Ada puluhan korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka dan aku membayangkan dia berada di antara orang-orang yang mati atau terluka tersebut. Aku meyakinkan diri bahwa dia akan tetap datang ke negeri kota ini menemuiku, mengatakan rindu padaku.
Namun, dia memang tidak pernah datang tanpa kabar dan aku benar-benar tidak bisa menghubunginya. Sampai pagi aku menunggunya di depan jendela, namun hingga kemudian aku berkemas, dia belum datang juga. Ketika aku mengatakan kepada resepsionis bahwa aku akan cek out, aku masih berharap dia datang. Dan sampai aku akan masuk ke dalam feri penyeberangan yang akan membawaku kembali ke Batam, dia juga tidak pernah datang dan tanpa kabar apapun. Namun, jantungku terasa berhenti ketika aku membeli sebuah koran berbahasa Inggris yang memberitakan tentang peledakan di Jakarta tersebut. Aku mengamati sketsa wajah itu, dan aku terduduk dengan debar jantung tak karuan. Koran itu mengatakan, lelaki yang sketsa wajahnya dibuat oleh polisi dan disebarkan ke publik itu, diduga adalah pelaku bom bunuh diri yang meledakkan sebuah gedung kedutaan di Jakarta. Aku mengenal goresan sketsa itu, sangat mengenalnya.
Aku ingat kata-katanya ketika terakhir kali kami berjumpa. “Esok atau kapan, jika engkau melihat fotoku di koran sedang dikerubungi lalat di tong sampah atau parit, katakan kepada penulis beritanya, atau fotografernya, bahwa aku memang pantas mati seperti itu...”
Aku benar-benar mengenal sketsa itu, tetapi aku tetap berharap itu tidak benar. Aku tetap ingin dia datang padaku dan kami bertemu seperti masa-masa sebelumnya. Meski sebenarnya, itu tidak boleh terjadi. Tapi, adakah pertemuan-pertemuan itu kembali di masa datang? Air mataku terus mengalir, benarkah dia lelaki yang kukenal selama ini, yang selalu berjanji bertemu di tempat yang jauh?***
Singapura, September 2004-Pekanbaru, Maret 2006
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






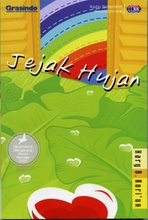

No comments:
Post a Comment