Cerpen Hary B Kori’un
“JIKA kamu nanti ke Jogja mampirlah ke Solo, temui Laksmi, bawa dia ke Jakarta…”
Begitu pesan ibu ketika aku mengatakan akan ke Jogja untuk sebuah urusan percetakan buku dari kantorku. Sejak harga kertas melambung tinggi, penerbitan buku tempatku bekerja memilih mencetak buku di Jogja yang masih agak murah harganya. Terus terang, aku tidak suka dibebani tugas seperti ini, menjemput seorang perempuan yang tak kukenal, akan berada satu kereta api hampir sehari atau semalam dengannya sementara aku memang ingin melakukan perjalananku sendirian.
“Kalau terlalu lama perjalananmu naik kereta, naik pesawat saja pulangnya,” kata ibu lagi seolah-olah tahu jalan pikiranku.
“Apakah aku memang harus membawanya ke Jakarta, Ibu?” kataku mencoba menawar.
“Iya. Katakan padanya kalau tempatnya bukan di Solo. Tinggi-tinggi sekolah, hanya menjadi guru di desa. Ndak memper ! Dia bisa menjadi apa saja di Jakarta asal dia mau. Nanti biar Ibu yang memasukkan dia kerja di perusahaan kolega ayahmu. Pokoknya katakan padanya kalau Ibu yang nyuruh dia ke Jakarta…”
“Kenapa Ibu tidak langsung telpon dia saja, biar nanti saya langsung menjemput dia kalau urusan saya sudah selesai di Jogja…”
“Walah Cah Bagus… Dia itu ngajarnya di Bekonang, dan desanya sangat terpencil. Ndak ada telpon di sana…”
Aku tak punya kata-kata lagi yang akan kujadikan alasan kepada ibu. Ketika aku akan pergi ke Gambir, ibu kembali berpesan. “Jangan lupa ya. Dia tidak akan menolak keinginan Ibu. Dia anak yang patuh…”
***
DIA anak yang patuh, kata ibu. Ketika aku sampai di desa tempat dia mengajar, aku dibawa oleh salah seorang tukang ojek ke sebuah sekolah dasar yang bangunannya terlihat ringkih. Atap gentengnya sudah banyak yang pecah, dindingnya yang terbuat dari semen sudah kelihatan mulai melapuk. Air masih menggenang terlihat di halaman sekolah itu. Ada enam kelas di bangunan itu, dan hampir semua kursi dan mejanya terlihat lusuh dan banyak yang patah. Lantainya memang terbuat dari semen, tetapi terlihat sudah rusak di sana-sini.
Dia muncul dengan senyumnya ketika aku sudah duduk di ruangan guru yang sempit, satu ruangan dengan kepala sekolah yang tadi menerimaku. “Anda mencari saya?”
Kukatakan bahwa aku disuruh oleh ibuku untuk mampir ke sini. Dia kemudian paham bahwa aku anak budenya. Kami memang tidak pernah saling kenal. Aku hanya numpang lahir di Solo dan kemudian ketika keluargaku pindah ke Jakarta, aku jarang pulang. Sementara dia, sejak lahir hingga SMA di Solo dan melanjutkan kuliahnya di Jogja sebelum kembali ke Solo untuk menjadi guru. Cerita terlalu jauh tentang dirinya, aku tidak tahu. Yang sedikit itupun aku tahu dari ibu. Hanya, aku tahu bahwa dari kecil hingga menamatkan kuliahnya, ibu yang membiayai karena ibu sangat sayang kepadanya dan kebetulan keluarganya –bapaknya adik kandung ibuku— memang secara ekonomi kurang menguntungkan.
“Bude menyuruh saya ke Jakarta?” katanya dengan suara yang halus.
“Begitu katanya. Dan sore nanti kita bisa berangkat ke Jakarta. Saya sudah membeli dua tiket kereta…”
Dia terlihat terperangah. “Secepat itu? Saya di sini kan bekerja, dan tidak secepat ini saya mendapatkan izin untuk pergi…”
“Ibu bilang, kamu tinggal di Jakarta saja. Toh kamu mengajar di sini kan tidak permanen…”
“Tetapi saya harus menghormati orang-orang di sekolah ini; guru-guru, murid bahkan orang tua mereka. Mereka harus tahu saya pergi. Mosok saya harus pergi seperti maling, tidak pamitan…”
“Serumit itu?” kataku.
“Tidak rumit. Ini desa, seperti itulah adat yang harus kita ikuti…”
“Saya bisa menunggu sampai jam 4. Kamu bisa pamitan dan kita langsung berangkat. Kalau tidak, kita bisa ketinggalan kereta…”
“Tetap tidak bisa. Minimal baru besok saya bisa, dan itupun sangat mepet.”
Dalam hati, saya heran. Pembawaannya santun dan halus, tetapi dari apa yang dikatakannya, ada karakter keras dalam dirinya. Kukatakan bahwa aku tak bisa menunggu sampai besok karena besok saya sudah harus masuk kantor. “Saya tak mungkin menunggu…”
“Kalau begitu, saya akan berangkat ke Jakarta sendiri.”
“Lalu, apa yang harus saya katakan pada ibu?”
“Sampaikan salam saya, katakan bahwa saya bisa ke Jakarta sendirian…”
Keras kepala! Aku menggerutu dalam hati.
***
HARI itu saya berangkat ke Jakarta sendirian dengan hati jengkel. Jauh-jauh saya ke Bekonang, ke desa pedalaman lagi, tapi dia tidak mau berangkat. Kukatakan pada ibu bahwa perempuan bernama Laksmi itu sangat keras kepala. “Saya jadi jengkel dibuatnya, Bu…”
“Dia itu adikmu, Wahyu. Kamu tidak boleh bicara begitu. Dia tadi nelpon, katanya dia akan berangkat dari Solo dengan kereta malam nanti. Besok pagi-pagi betul kamu harus ke stasiun untuk menjemputnya.”
“Menjemputnya?!”
“Ya. Siapa lagi? Mosok ayahmu yang harus ke stasiun…”
“Suruh saja dia naik taksi, Bu. Kan tinggal ngasih alamat saja sama sopir taksi, dan dia sampai di sini. Kenapa saya harus repot-repot menjemput?”
Ibu mendekatiku. Kemudian dengan wajah serius bicara padaku. Tidak biasanya ibu bicara seserius begitu. “Wahyu, hargailah dia. Meskipun dia orang desa, tetapi dia saudaramu. Jangan menjadi sombong seperti itu…”
“Bukan sombong, Bu. Tapi besok saya kan harus masuk kantor pagi-pagi…”
“Jangan mencari alasan. Kamu bisa menjemputnya setelah Subuh dan kamu tak akan telat sampai ke kantormu…”
Itu titah. Dan saya tidak bisa menjawab apa-apa lagi.
Dan pagi-pagi benar saya sudah di stasiun sebelum kereta datang. Ketika kereta datang dan dia melihatku terkantuk-kantuk di ruang tunggu, dia mengatakan minta maaf karena merepotkan. “Saya sebenarnya bisa naik taksi dan tidak usah dijemput…”
Aku diam dan membukakan bagasi untuk barang-barangnya. Tidak banyak, hanya dua tas berisi pakaian dan dia sendiri membawa tas sandang. Sepanjang perjalanan dari Gambir sampai ke Kembangan, kami tak banyak bicara. Hingga akhirnya saya berangkat lagi ke kantor, aku tak menegurnya dan aku tahu ibu memperhatikan sikapku itu.
Nampaknya ibu benar-benar ingin saya direpotkan oleh Laksmi. Ketika beberapa kali tes dan interview untuk pekerjaan-pekerjaan di mana dia dipanggil sebagai pelamar, harus aku yang mengantarkannya. “Dia kan baru di Jakarta. Dia tidak tahu utara-selatan, dia bisa tersesat,” begitu kata ibu. Padahal pekerjaanku di kantor menumpuk dan aku harus menjadi sopir baginya.
Sebenarnya dia tidak memerlukan waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan karena teman-teman ayah bersedia menerimanya. Tetapi dia tidak mau membuka jilbabnya sebagai syarat pekerjaan itu dan aku menjadi jengkel dibuatnya. “Apa susahnya sih membuka jilbab?”
Dia mengatakan, biarlah dia tidak mendapatkan pekerjaan itu kalau syaratnya itu.
“Ini Jakarta, Laksmi. Di sini orang yang mencari pekerjaan ribuan orang untuk satu lowongan. Sementara kamu, menolaknya hanya gara-gara tidak mau membuka jilbab. Toh kamu tetap bisa beribadah dan tetap tidak akan murtad kalau harus membuka jilbab?”
Dia tetap menggeleng. Dan akhirnya aku benar-benar tidak mau mengantarkannya mengikuti tes lagi. Hingga suatu hari aku membiarkan dia harus naik-turun oplet dan bus untuk mengikuti tes di beberapa tempat. “Kamu tega, Wahyu. Kalau dia tersesat bagaimana?”
“Dia kan punya otak, Bu. Biar dia rasakan sendiri capeknya…”
Setelah itu beberapa hari saya tak bertemu dia. Pekerjaan saya benar-benar menumpuk. Banyak buku yang harus kuedit karena ada seorang editor yang cuti dan buku yang ditanganinya harus cepat dikirim ke percetakan. Aku sering pulang tengah malam dan pagi-pagi harus ke kantor. Hingga beberapa hari kemudian aku tahu dari ibu kalau dia mendapat pekerjaan di sebuah yayasan anak-anak cacat sebagai tenaga guru. “Hormatilah pilihannya. Di sana semua guru harus pakai jilbab dan yayasan itu sangat bersimpati padanya…”
Aku termenung. Dia lebih memilih menjadi guru di yayasan anak-anak cacat dengan gaji kecil ketimbang bekerja di kantor perusahaan asing milik relasi ayahku dengan gaji yang berlipat-lipat? Benar-benar gadis aneh…
***
KAMI sampai di sini beberapa hari yang lalu, tetapi aku belum juga menemukan dia. Sudah dua hari ini aku mencarinya, berharap menemukan berita tentang dirinya dari siapapun. Aku tak ingin menemukannya menjadi mayat seperti yang dalam dua hari ini kulakukan, mengevakuasi mayat-mayat yang betebaran di sana-sini.
Aku menyesali segala apa yang terjadi. Sudah lama aku tahu ibu ingin menjodohkan aku dengan Laksmi. Ketika aku disuruh mampir ke Solo saat ke Jogja, itu sebenarnya salah satu cara ibu agar aku bisa bertemu langsung dengannya. Waktu itu aku tidak tahu, dan ibu baru memberi tahu ketika hampir setahun dia tinggal di rumah saat dia bekerja di yayasan anak cacat itu. Aku marah besar ketika itu, seolah-olah aku tidak bisa mencari pendamping hidup sampai harus dijodohkan seperti itu.
Mungkin pertengkaranku dengan ibu didengarnya malam itu, meski paginya ketika aku mengantarkannya ke yayasan itu, sikapnya terhadapku masih seperti dulu, penuh sopan-santun dan bersahaja. Sampai akhirnya aku mendengar dari ibu bahwa dia ikut program relawan guru yang akan dikirim ke Aceh. Mulanya aku merasa tidak peduli, tetapi akhirnya aku menanyakan juga kepadanya kenapa dia memilih ke sana.
“Tidak ada apa-apa, Mas. Saya cuma ingin tahu Aceh itu seperti apa,” katanya ringan ketika itu.
“Di sana perang masih terus terjadi, Laksmi.”
“Saya tahu. Tetapi saya yakin Tuhan akan melindungi kita kalau niat kita tulus. Saya tahu, di beberapa daerah konflik tidak ada guru yang mau dikirim ke sana, dan yayasan kami mendapat jaminan keamanan dari pemerintah terhadap guru-guru yang dikirim ke sana. Kasihan anak-anak di sana tidak ada yang sekolah karena tidak ada yang mengajar mereka…”
Ketika itu, aku baru menyadari kebaikan hati wanita itu. Tetapi aku tetap tidak bisa mencegah kepergiannya. Aku yang mengantarkannya ke bandara ketika itu dan dia mengatakan terima kasih karena selama di Jakarta aku banyak membantunya. Aku tersenyum kecut merasa disindir meski aku tahu kata-katanya tulus. “Hati-hati, jaga dirimu di sana ya…” kataku sambil menyalaminya.
Dia hanya tersenyum dan kemudian membalikkan badan tanpa menoleh lagi. Itulah setahun lalu untuk terakhir kalinya aku bisa melihat Laksmi karena setelah itu dia hanya berkabar kepada ibu lewat surat maupun telepon bahwa dia baik-baik saja ketika berada di Pidie, Aceh Jaya, Kota Cane maupun saat terakhir dia ditarik ke Banda Aceh. Dan baru sebulan dia di kota itu, kabar dahsyat itu datang pada kami: kota itu, bersama beberapa kota dan daerah lainnya, disapu gelombang tsunami dengan korban puluhan ribu orang.
Aku panik. Ibu, ayah dan orang-orang di rumah semuanya panik. Dia tak bisa dihubungi. Nomor telepon rumah di mana dia tinggal yang dikirimkannya, tidak bisa dihubungi. Hari Senin aku memutuskan untuk terbang ke Medan dan kemudian berebutan pesawat menuju Banda Aceh. Aku masuk tim relawan, tetapi aku membiayai semua perjalananku sendiri. Aku akan mencarinya, dan aku akan mendapatkannya.
Aku baru menyadari betapa mulianya hati Laksmi. Gadis sederhana yang tidak banyak bicara, tetapi begitu perasa dan mempedulikan orang lain sampai dia tak mempedulikan dirinya sendiri. Tetapi sesampai di Banda Aceh, aku hanya bisa menangis melihat rumah-rumah, toko-toko, mobil-mobil dan semua infrastruktur lainnya hancur. Mayat-mayat bergelimpangan di sana-sini, ada yang mengambang di air, terjepit di reruntuhan, mencantol di atas pohon. Tuhanku, cobaan apa yang Engkau berikan ini?
Aku mencari rumah yang alamatnya dituliskan Laksmi dalam suratnya kepada ibuku. Jangankan rumahnya, seluruh kompleks di mana rumah itu berada, sudah rata dengan tanah dan lumpur. Seorang teman bertanya apakah aku punya kawan di sana, kujawab gelengan, tetapi air merembes dari mataku. Aku tetap mencarinya dan selalu berdoa kepada Tuhan bahwa Dia akan menyelamatkan orang-orang yang memiliki ketulusan dan niat baik.
Aku jadi ingat kata-katanya dulu. “Saya tahu. Tetapi saya yakin Tuhan akan melindungi kita kalau niat kita tulus. Saya tahu, di beberapa daerah konflik tidak ada guru yang mau dikirim ke sana, dan yayasan kami mendapat jaminan keamanan dari pemerintah terhadap guru-guru yang dikirim ke sana. Kasihan anak-anak di sana tidak ada yang sekolah karena tidak ada yang mengajar mereka…”
Aku benar-benar menangis ketika berhari-hari mengevakuasi mayat-mayat dan saat tidur di masjid di Pendopo Gubernuran. Aku selalu berdoa semoga Tuhan benar-benar menyelamatkannya di manapun dia kini berada. Aku berharap semoga saat air itu menghancurkan rumah yang ditinggalinya, dia sedang berada di Seulawah, Blang Bintang atau sedang bertamasya di bukit-bukit. Aku ingin Tuhan benar-benar menyelamatkannya, karena aku menyadari bahwa aku sangat mencintainya…***
Banda Aceh-Pekanbaru, Januari 2005-Januari 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






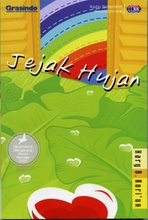

No comments:
Post a Comment