Hary B Kori'un
MAYAT itu ditutup kain batik dengan dominasi warna hitam. Tidak terlihat jelas wajahnya, karena ditutup, juga seluruh tubuhnya. Hanya kedua telapak kaki dan jari-jarinya dengan kuku menghitam yang terlihat. Entah kenapa, tidak ada orang yang berani bertanya, dan mungkin tidak ada gunanya bertanya, kenapa kedua kakinya tidak ditutup seperti bagian tubuh yang lain. Padahal di dekat mayat itu, ada seorang laki-laki tua, sangat tua, dengan gigi yang nyaris habis, kedua pipi cekung, memakai topi lusuh warna hitam. Ada tongkat terbuat dari kayu, yang juga sudah kelihatan lusuh. Seluruh pakaian yang dikenakannya juga berwana hitam, bahkan tas kain kecil, yang juga lusuh, juga berwarna hitam.
Laki-laki itu duduk bersila di sudut gerbong, sambil sekali-kali memegang kepala mayat yang ditutup kain batik hitam itu. Anehnya, tidak tercium bau busuk dari mayat itu, juga dari laki-laki itu. Padahal, sudah menjadi hal yang lumrah, bau keringat dan bau busuk lainnya cukup menyengat ketika orang-orang mulai berjubelan masuk, ada yang duduk, tetapi lebih banyak yang berdiri. Bahkan banyak juga yang tidak mendapat tempat, hanya sekedar berpegangan. Namun tetap ada tempat untuk laki-laki dan mayat di dekatnya itu. Paling tidak, hampir semua orang yang menggunakan jasa kereta api dari kota itu untuk bekerja di Jakarta, setiap hari pasti melihat lelaki tua dan mayat itu tetap di situ. Tentu mereka yang mendapat tempat di gerbong itu. Hanya posisinya saja yang kadang berubah. Kalau tidak di sudut kanan, pasti di sudut kiri.
Lelaki itu hanya diam, memandang ke orang-orang yang selalu berebutan tempat ketika pagi menuju Jakarta, dan sore ketika pulang. Barangkali juga ketika siang hari penumpang kereta agak lengang. Dia tidak pernah melakukan aktifitas apa-apa selain sekali-kali memegang kepala mayat di dekatnya, atau meletakkan kepala mayat itu ke pahanya, seperti memberi bantal. Dia tidak meminta-minta seperti banyak pengemis yang turun-naik di setiap stasiun, atau banyaknya orang yang meminta sumbangan macam-macam, baik untuk pesantren, membangun masjid atau untuk anak yatim. Biasanya mereka menggunakan peralatan elektronik yang dirakit secara manual. Bahkan ketika kakinya nyaris terinjak oleh sekelompok anak muda yang dengan bangganya mengamen dengan peralatan musik lengkap sebagaimana kelompok musik terkenal, dengan asesoris yang rumit --ada rantai yang ditalikan di saku yang dihubungkan dengan tempat ikat pinggang, gelang di tangan yang jumlahnya banyak dan warna-warni, telinga ditindik bahkan lebih dari satu, cincin dan asesoris lainnya--- lelaki tua itu tetap diam. Memang, kadang-kadang anak-anak muda yang mengamen itu bertindak kasar dan mengganggu penumpang, bukannya menghibur. Pernah seorang pedagang ayam marah-marah di suatu pagi, karena tumpukan keranjang berisi ayamnya ditabrak oleh sebuah kelompok musik di kereta api itu, hanya karena menghalangi jalan mereka. Namun, lelaki tua itu tetap tidak bergeming, tetap tenang tanpa melakukan apapun. Selain memegang kepala mayat di dekatnya, dia juga kadang minum air putih dari dalam botol air yang sudah nampak menguning.
Mula-mula, memang para penumpang lebih memperhatikan lelaki tua dan mayat itu ketimbang pengamen, penjual koran, peminta bantuan atau pengemis yang lalu-lalang. Karena, pasti aneh ada mayat ditunggu seorang laki-laki tua, berhari-hari tidak membusuk dan selalu menebarkan bau wangi. Logikanya, semakin lama daging mati dibiarkan, pasti akan membusuk dan menebarkan bau yang tak sedap. Namun ini tidak, bahkan orang-orang yang biasanya menutup hidung karena bau keringat bercampur bau lainnya, kini mereka justru menghirup dalam-dalam.
***
AWALNYA seorang gadis cantik yang juga berpakaian serba hitam --yang ini seragam di sebuah kantor swasta— yang bertanya kepada lelaki itu, di suatu pagi.
“Mayat ini saudara Bapak?”
Laki-laki itu menggeleng.
“Mengapa tidak dikuburkan saja?”
Lelaki tua itu hanya memandang gadis cantik itu. Tanpa jawaban.
“Saya ingin menolong, apa yang bisa saya bantu?”
Tetap tidak ada jawaban.
“Saya hanya punya uang ini, barangkali bisa membantu membeli kain kafan…” Gadis cantik itu memasukkan beberapa lembar uang lima puluh ribuan ke saku baju yang lusuh itu. Tidak ada rasa canggung dalam gerakannya sehingga justru mengundang perhatian hampir semua penumpang. “Tidak baik membiarkan mayat begitu lama tidak dikubur, Bapak. Kita semua akan menanggung dosanya. Nanti bawalah pulang, barangkali di luar kota masih ada tempat pemakaman yang murah…” Gadis cantik itu kemudian turun di Stasiun Gambir.
Sore harinya, seorang ustad dengan pakaian serba putih yang mendekati laki-laki tua itu. “Pak Tua, tidak baik kita membiarkan orang yang sudah meninggal. Rohnya akan tersiksa, kita harus lekas-lekas membumikannya, karena asalnya dari bumi. Bukan hanya Bapak yang menanggung dosa kepada Allah, kita semua. Tolonglah Pak, biarkan kami menguburnya di kampung kami kalau memang Pak Tua tidak bisa menguburkannya.”
Namun lelaki tua itu tetap diam.
Pagi berganti siang. Siang menjadi senja dan terbitlah malam. Pagi-pagi, kembali para penumpang kereta api mendapati lelaki tua itu tetap di gerbong pertama, menunggu mayat yang hanya nampak telapak kaki dan kukunya yang kelihatan menghitam. Lama-lama, karena mayat dan lelaki tua itu malah menyebarkan bau yang wangi, para penumpang tidak merasa terganggu dengan kehadirannya. Yang mengganggu mereka tetap saja pengemis yang lalu-lalang, peminta sumbangan yang turun-naik atau kelompok pengamen yang merasa lebih hebat dari grup musik manapun. Namun, kadang-kadang, tetap saja ada yang membicarakannya.
“Kasihan Pak Tua itu. Apakah mayat itu bagian dari keluarganya?” Seseorang bertanya, entah kepada siapa.
“Tetapi mengapa gosong? Seperti habis terbakar?” Terdengar yang lainnya.
“Mungkin korban perkosaan.”
“Korban perkosaan tak mungkin gosong. Pasti dia dibunuh dan kemudian dibakar.”
“Tepatnya diperkosa dulu, kemudian dibunuh dan dimasukkan ke dalam api. Supaya tak berjejak.”
“Mungkin juga bukan korban perkosaan dan pembunuhan. Mungkin benar-benar terbakar karena kecelakaan.”
“Mungkin korban kerusuhan yang membakar Jakarta dulu.”
“Ah, itu sudah lama. Sudah berganti tahun. Tak mungkin-lah…”
“Siapa tahu?”
“Tapi kok baunya wangi, ya?”
“Hiii… bulu kudukku berdiri…”
***
HINGGA di suatu siang yang agak lengang, datanglah seorang lelaki muda, duduk di kursi dekat lelaki tua itu duduk di lantai gerbong. Wajahnya tampan, bersih, seperti habis bercukur karena di janggut dan di antara bibir dan hidungnya terlihat warna agak membiru. Rambutnya hitam tebal, terlihat basah dan disisir kelimis ke belakang. Dia memakai jas warna hitam yang melapisi baju putih bersih. Celana yang dipakainya juga sewarna dan sejenis dengan jasnya. Di tangannya ada sebuah biola dan penggeseknya. Semua penumpang –jumlahnya tidak lebih dari 20 orang di gerbong itu— melihatnya dengan seksama.
“Siapapun mayat yang Bapak tunggui, saya tidak peduli. Tetapi saya tahu, Bapak pasti lelah berhari-hari, bahkan mungkin telah berbulan-bulan, duduk, hanya minum air putih, tidak melakukan gerakan yang berarti dan tak menghiraukan apa dan siapapun di gerbong kereta api ini. Padahal manusia hidup butuh makan, minum, bergerak dan berhubungan dengan orang lain. Tetapi saya tahu, Bapak pasti terluka atas kematian orang ini. Dan saya yakin orang ini pasti pernah begitu berarti dalam kehidupan Bapak…”
Semua orang dengan seksama mendengarkan kata-kata lelaki muda tampan itu. Sementara lelaki tua itu tetap diam dengan tatapan lurus searah mukanya. Kosong.
“Bapak, kita orang-orang terluka, tetapi jangan lihat pakaian dan alat yang saya bawa. Percayalah, kita sama-sama terluka. Oleh nasib, dan barangkali oleh ketidakberuntungan. Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, karena memang tidak ada yang salah. Jika luka membuat Bapak tetap duduk di sini berhari-hari, berminggu bahkan hampir genap tiga bulan ini, luka juga yang membuat saya berkeliling memainkan biola ini, menghibur siapa saja yang mau mendengarkannya. Kita dipermainkan oleh nasib, dan saya mempermainkan biola ini, dan orang-orang mendengarkan. Bapak, saya ingin memainkan untuk Bapak…”
Kemudian terdengar sebuah komposisi yang aneh. Mula-mula gesekan itu datar, namun tiba-tiba menukik dan tak beraturan, naik-turun. Seterusnya, terdengar sebuah rintihan perih. Perih yang muncul dari sebuah luka. Luka yang datang karena sebuah cinta, dan cinta itu menyisakan ngilu. Terbayang sebuah pertemuan, kindahan, kegelisahan dan perpisahan. Di sebuah kota kecil bersalju. Entah di mana. Beberapa saat kemudian, semua orang di gerbong itu tak sadar kalau air mata mereka sudah mengalir. Ada yang terasa luka di dada mereka masing-masing, entah luka apa. Ada yang terbayang pada masa lalu, pada luka karena kemiskinan; luka dikhianati; luka ditinggalkan; luka perpisahan; luka kehilangan kasih sayang; luka yang kadang tak bermakna apa-apa, namun terasa menyayat: luka semua orang.
***
AKU kisahkan ini kepadamu, Ira, sebab aku merasa terasing di sini, di sebuah kota pelarianku sekian tahun ini, hanya karena ketakutan bertemu kembali denganmu. Sebab, bertemu kembali denganmu hanya akan menyisakan perih dan ngilu: sebuah luka yang selalu basah, tidak kering oleh betadin dan tidak sembuh oleh balutan perban sutra, sekalipun.
Mulanya, aku tidak percaya dengan cerita dari mulut ke mulut itu. Bahwa ada seorang lelaki tua yang setiap hari menunggui mayat menghitam berbau wangi, di sebuah gerbong kereta api, setiap hari. Ketika kemudian aku penasaran dan naik kereta api itu, ternyata aku tidak menemukan apapun, juga lelaki tampan yang memainkan komposisi aneh itu. Yang kutemui tetap sama: penumpang yang berdesakan, pengamen yang kadang egois, pengemis yang tidak pernah habis, pencari sumbangan yang tak kenal lelah, penjual teh botol yang sering kehausan atau penjual koran yang malas membaca. Selalu itu. Aku menjadi kecewa.
Dari mulut ke mulut pula, beberapa bulan kemudian, tersiar kabar, bahwa di sebuah kampung di pinggir kota, terdapat tiga gundukan tanah yang masih memerah. Penduduk kampung itu menjelaskan, mereka menemukan seorang lelaki tua memegang botol minuman, seorang lelaki muda memegang biola dan seorang wanita yang gosong dan telanjang, terlempar dari gerbong sebuah kereta yang sedang melaju kencang. Mereka semua sudah mati, dan kemudian dikuburkan di kampung itu. Aku tidak ke sana, karena aku yakin, seperti yang terjadi sebelumnya, bahwa aku tidak akan menemukan apa-apa. Karena kabar itu kudapatkan dari mulut ke mulut. Namun, kabar yang lain mengatakan, mayat yang ditunggui lelaki tua itu --juga sering didatangi pemuda tampan pemain biola itu— masih berada di salah satu gerbong sebuah kereta hingga sekarang.
Ira, jangan percaya dengan kabar yang datang dari mulut ke mulut. Dan jika pun engkau membaca cerita ini, jangan cepat percaya. Sebab, saat ini aku memang menjadi tukang kabar, profesi baru yang kujalani di kota ini. Karena aku tidak punya teman untuk bercerita lagi setelah sekian tahun aku pergi menjauhimu. Dan jika suatu saat kamu datang ke kota ini, berkesempatan naik sebuah kereta api jurusan luar kota, jangan terkejut kalau kamu ketemu lelaki tua yang sedang menunggui mayat itu. ***
Pekanbaru, Maret 2005-November 2006
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






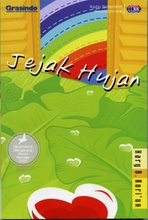

No comments:
Post a Comment