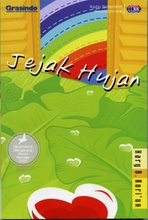Cerpen Hary B Kori'un
Sungai Duku
(Senja yang berkabut)
“AKU akan berlayar jauh mengarungi samudera dan mungkin bertahun-tahun tak kembali. Tunggulah aku di dermaga ini, aku akan kembali bersama kapal ini juga. Dari kecil aku ingin jadi pelayar dan menaklukkan lautan. Maukah engkau menungguku?”
Kapal akan segera berangkat dan lelaki itu sejenak merangkul kekasihnya yang dari tadi hanya diam. “Nyimas Rita Umi Kalsum, dengarkan aku. Aku akan kembali lagi ke dermaga ini dan aku ingin engkau selalu menungguku di sini. Katakanlah sesuatu...”
Kapal benar-benar akan berangkat dan lelaki itu semakin gelisah di dermaga. Panggilan terakhir terdengar, namun kekasihnya tidak juga berkata barang sepatahpun. “Umi, aku akan tetap kembali. Doakan aku...” Kemudian lelaki itu berlari menuju kapal dan masuk dalam kerumunan penumpang yang berjejal. Dia masih melihat kekasihnya memandang ke arah kapal, tanpa gerakan, seperti semula. Dia seperti patung yang bisu, beku dan hanya tatapan matanya yang menjelaskan dia masih benar-benar hidup.
Angin senja meniupkan hawa aneh yang menerpa tubuh perempuan itu. Rambutnya yang panjang sebahu tertiup angin dan tergerai-gerai. Kabut tipis yang datang sejak tadi semakin menyiratkan pedih di aura wanita itu. Perlahan, kapal meninggalkan dermaga dan wanita itu tetap mematung tanpa ekspresi yang pasti. Sedang lelaki yang sudah masuk ke kapal, hanya terlihat kepalanya dari jauh, yang tetap dikenali wanita itu. Lelaki itu melambai, tetapi wanita itu tetap diam. Semakin jauh, wajah lelaki itu sudah tak terlihat dan dalam hitungan menit, kapal penumpang itu sudah hilang di kelokan sungai. Wanita itu tetap diam di situ ketika para pengantar satu per satu sudah meninggalkan dermaga.
Seorang petugas dermaga menyapanya. “Anak, sebentar lagi malam. Tidakkah engkau ingin pulang?”
“Saya ingin menunggunya di sini, Pak.” Jawabnya. Inilah suara pertamanya sejak sampai di dermaga ini bersama kekasihnya tadi.
“Aduh, di sini tidak ada penginapan. Anak akan menginap di mana?”
“Saya tak akan menginap di mana-mana. Saya tidak perlu tidur. Saya akan duduk di dermaga ini, boleh Bapak?”
Lelaki itu kebingungan dan kemudian mengangguk sebelum pergi ke kantornya yang tak jauh dari situ. Dia menggeleng-geleng tak mengerti.
Beberapa hari kemudian, wanita itu tetap duduk di dermaga sambil memandang arah timur, arah dari mana biasanya kapal datang dari Bengkalis, Batam, Dabo Singkep, Tangjung Pinang atau daerah kepulauan lainnya. Matanya tampak sayu dan lelah, tetapi kecantikannya tak berubah meski ada warna hitam di bawah kelopak matanya. Warna yang terlalu dini untuk gadis muda seusianya.
“Siapa sih yang Anak tunggu?” tanya petugas dermaga itu yang hampir setiap hari berada di Pelabuhan Sungai Duku.
“Kekasih saya, Pak.”
Mulut lelaki itu berbentuk huruf ‘O’ mendengar jawaban wanita itu. “Lalu, dia pergi ke mana?”
“Tidak jelas. Katanya dia ingin berlayar mengarungi tujuh samudera dan menaklukkannya. Tetapi dia berjanji akan kembali kok, selama ini dia tak pernah mengingkari janjinya.”
“Sudah lama mengenalnya?” Lelaki itu semakin antusias bertanya.
“Kami bersama sejak kecil,” jawab wanita itu sambil tersenyum. Dia teringat masa kanak-kanak mereka di sebuah kampung di pinggir Sungai Siak, tak jauh dari dermaga itu. Ingat bagaimana mereka tumbuh bersama menjadi remaja dan kemudian cinta tumbuh dalam diri mereka. Cinta yang dibangun sejak masa kanak-kanak, sejak mereka sendiri tak tahu apa arti cinta itu.
“Dan dia tak pernah sekalipun mengingkari janjinya?”
Wanita itu menggeleng.
“Tujuh samudera...” gumam lelaki itu. “Apakah Anak yakin kalau dia akan selamat? Kapan dia berjanji akan kembali?”
“Saya selalu yakin dia akan selamat. Ketika kami kecil, dia pernah menyelamatkan saya dari arus Sungai Siak ini saat banjir bandang datang. Ketika kami remaja, dia pernah membunuh harimau di hutan yang selalu mengganggu penduduk meski dia terluka parah. Dan beberapa waktu lalu, ketika dia naik kapal dari Dabo, kapalnya pecah dihantam badai dan semua penumpang tewas. Tetapi dia masih hidup. Kalau dia mati, sudah dari dulu dia mati. Tetapi dia selalu mengatakan bahwa dia akan tetap hidup, untuk menemani, menjaga dan melindungi saya. Dia tidak pernah berjanji kapan pulang ketika dia pergi, tetapi selama ini dia selalu kembali...”
Lelaki itu bergumam tak jelas. “Cinta kalian luar biasa. Bapak serasa ingin menjadi remaja lagi...”
Anambas
(Dalam hempasan angin dan gelombang)
UMI, kapal kami sudah sampai di Kepulauan Natuna saat ini, dan sebentar lagi kami akan sampai di Laut Cina Selatan. Dari Sungai Duku, aku naik kapal ini di Tanjung Pinang, di sana semua awak yang akan berlayar di ekspedisi ini sudah menunggu. Kata kapten kapal, kami akan berlayar ke Hokaido, kemudian ke Hawai, singgah di Colorado, menembus Selat Panama, menyeberang Samudra Antlantik, singgah di beberapa negara Eropa, kemudian ke Andalusia di Semenanjung Cordoba (Spanyol), kemudian menuju Cape Town di Afrika Selatan, singgah ke Madagaskar, Sri Langka dan setelah itu akan kembali ke Selat Malaka. Aku senang sekali karena ini adalah pelayaran terbesar yang pernah dilakukan oleh kapal ini beserta para awaknya. Tidak rugi aku berjuang sekian tahun untuk menjadi salah satu awak kapal ini. Kalau kamu membaca buku sejarah ekspedisi terbesar yang pernah dilakukan Vasco Da Gama, Marcopollo, Amerigo Bertolucci, Christopher Columbus dan pelayar lainnya, ekspedisi kami ini tak kalah besarnya. Kamu harus bangga karena aku akan menjadi orang kampung kita pertama yang ikut menaklukkan dunia. Semua koran di seluruh dunia akan mencatat perjalanan kami ini, Umi.
Selama pelayaran dari Sungai Duku hingga ke Anambas ini, Umi, aku menjadi sedih. Banyak hal yang selama ini berada jauh dalam pemikiran dan hatiku. Orang bilang --dan memang kenyataannya begitu— kampung kita adalah salah satu kampung terkaya di negri ini. Memiliki minyak, baik di dalam tanah maupun di tumbuhan yang dibudidayakan; memiliki hutan yang sangat lebat dan membuat banyak orang tertarik untuk membabatnya; memiliki laut yang menghasilkan ikan dan pasir, tetapi malah banyak pulau yang tenggelam karena pasirnya dijual untuk membangun pulau kecil milik tetangga. Di kampung kita, juga banyak orang pintar Umi, tetapi banyak dari mereka yang malah menjual kepintaran dengan membesarkan perut sendiri, sementara banyak petani dan nelayan yang tetap miskin. Harga gabah dan ikan sangat rendah dan tak mampu membuat mereka bisa kembali melaut atau turun ke sawah lagi. Dan banyak lagi orang pintar yang menjadikan kemiskinan itu sebagai tambang uangnya. Mereka menjual proposal pemberdayaan kemiskinan ke donatur luar negeri. Mereka sebenarnya tidak suka orang miskin menjadi makmur, Umi, karena kalau petani, nelayan atau pekebun makmur, mereka tak punya lagi dagangan yang bisa dijual ke orang asing. Sepanjang Sungai Siak hingga kami sampai di Anambas ini, banyak kampung yang terisolir, tak berlistrik dan banyak pula sekolah bergedung kayu tetapi hampir rubuh.
Umi, surat ini kutulis dalam malam-malam yang sepi di antara jeripak air laut. Kutitipkan kepada salah seorang awak kapal penumpang yang akan menuju Sungai Duku. Kukatakan padanya ciri-cirimu dan kukatakan pula bahwa engkau selalu menunggu aku di Sungai Duku. Masihkah engkau di situ, Umi? Aku tahu, selama ini engkau adalah kekasihku yang sangat setia. Doakan aku dan tetaplah menunggu di dermaga tempat di mana aku pergi dulu.
Sungai Duku
(Musim kabut dan asap)
MARTIN, orang-orang yang lalu-lalang di Sungai Duku banyak yang heran mengapa aku tetap berada di dermaga ini. Tentu bagi mereka yang memang sering atau setiap hari ke sini. Bagi mereka yang sekali-kali saja, tentu tidak mau tahu dan menganggap aku seperti para calon penumpang lainnya atau sedang menunggu saudaranya dari kepulauan yang naik kapal menuju Pekanbaru. Aku masih tetap di sini, Martin, menunggu kabarmu, menunggu janjimu dan menunggu dirimu. Kapan engkau akan kembali?
Sekarang sedang musim kabut dan asap, Martin. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kabut dan asap sudah menjadi bagian dari kampung kita dan banyak orang mengatakan bahwa musim kabut dan asap sudah sama seperti musim hujan dan panas, dua musim yang memang ada di daerah tropis. Apakah kapalmu sudah sampai di Hokaido, Colorado atau justru sedang menyeberang ke Atlantik lewat Selat Panama? Pasti engkau nanti bisa merasakan empat musim yang ada di belahan bumi lain itu. Apakah sedang musim salju, semi, atau panas? Kadang-kadang, aku terpikir ingin juga pergi sepertimu. Tetapi aku sadar, aku hanya gadis kampung dan mungkin sudah kodratku untuk bertindak pasif. Banyak orang mengatakan bahwa perempuan sangat tidak sopan kalau terlalu agresif. Perempuan harus pasif, menunggu, menerima dan tak perlu banyak tanya. Namun, engkau yang sering mengajarkan padaku bahwa harus ada kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Aku senang, engkau sering membesarkan hatiku dalam banyak hal. Engkau jugalah yang meyakinkan orangtuaku agar aku bisa kuliah hingga menjadi sarjana, meski hanya sarjana guru.
Martin, ceritaku tentang kabut dan asap tadi belum selesai. Jarak pandang di kampung kita hanya beberapa meter dan sudah banyak anak-anak yang harus masuk rumah sakit karena radang pernapasan. Pagi tadi aku membeli koran di dekat dermaga. Kata koran itu, pemerintah sudah melakukan pengusutan para pengusaha yang melakukan pembakaran hutan. Banyak perusahaan yang dituding, tetapi belum ada satupun yang dijadikan tersangka, katanya belum ada fakta verbal, namun katanya pengusutan tetap dilakukan. Pengusutan yang membingungkan karena mirip benang kusut. Wartawan yang menulis berita itu tidak menuliskan bahwa sebenarnya pembakaran hutan yang dimulai dengan penebangan kayu, banyak terjadi kolusi antara pejabat pemerintah, pejabat keamanan dan pengusaha tersebut. Inilah yang menyulitkan. Dulu engkau sering bercerita padaku, Martin, bahwa warisan yang paling sulit dihilangkan dari pemerintah kolonial Belanda untuk negri kita adalah keterbelakangan berpikir dan mental korup yang mengakar dari pejabat tingkat RT hingga yang paling tinggi. Mereka mengatakannya inlander, tetapi makna yang muncul adalah keterbelakangan dan kebodohan. Bahkan, katamu, guru yang bertugas membuat orang pintar-pun, sekarang juga sudah pandai menyimpang. Sudah jarang ada guru seperti Umar Bakri seperti dalam lagu Iwan Fals itu. Sekarang, semuanya diatur dengan uang, dan untuk mendapatkan uang itu segala cara dilakukan. Aku senang, engkau selalu mengatakan padaku bahwa ukuran kebahagiaan bagimu bukanlah materi, tetapi ketenangan dan kesederhanaan. Namun aku menjadi bingung karena ukuran ketenangan bagimu justru keresahan bagiku. Ketenanganmu dalam perjalanan dan petualangan membuat aku resah setiap hari meski engkau harus selalu yakin bahwa aku akan tetap menunggumu sampai kapanpun. Namun, aku tetap bahagia, Martin. Pulanglah, dan engkau akan mendapati aku tetap berada di Sungai Duku menunggumu. Sampai kapanpun, meski nanti rambutku memutih dan mataku mulai rabun, aku akan tetap menunggumu.
Sungai Duku
(Ada cinta yang tak menuntut apa-apa...)
LELAKI petugas dermaga itu duduk di samping wanita itu sambil mengulurkan sepotong roti. Wanita itu menerimanya dan kemudian memakannya. Mereka sudah sangat akrab karena hampir setiap hari, kecuali hari Minggu atau sedang cuti, lelaki itu pasti bertemu dengan wanita yang sedang menunggu kekasihnya itu. Mereka sering bercerita apa saja, mulai dari musik, olahraga, filsafat atau sekedar ngobrol ringan pengisi waktu. Dia juga sering bercerita tentang keluarganya; anak-anaknya yang kini sudah tumbuh dewasa dan masuk perguruan tinggi, atau tentang istrinya yang sudah hampir 20 tahun ini selalu menemaninya, tanpa keluhan, meski gaji yang didapatkannya dari tugasnya sebagai petugas pabean tidak terlalu besar. Dia juga sering bercerita, banyak pengusaha ekspor-impor yang mengeluarkan dan memasukkan barang lewat dermaga ini, selalu berusaha memberinya banyak uang lelah, tetapi dia memilih berkata tidak meski dia sering dicibir teman-temannya. Bahkan, ada dari pengusaha-pengusaha tersebut yang menawarkan jasa untuk menyekolahkan salah seorang anaknya di perguruan tinggi, sampai tamat.
“Kenapa Bapak tidak mau menerima itu? Kan biaya yang Bapak keluarkan untuk pendidikan menjadi agak ringan,” kata wanita yang selalu menunggu kekasihnya itu.
Lelaki itu menghela nafas sebentar. “Dari kecil saya diajari orangtua untuk jujur, Nak. Uang haram yang kita gunakan untuk membesarkan anak-anak akan menjadi racun bagi mereka.”
“Seandainya di negri ini banyak pegawai yang seperti Bapak...” gumam wanita itu. “Tetapi bohong sedikit kan tak apa, Pak?”
“Mulanya sedikit, setelah itu lupa kalau itu bohong karena sudah menjadi kebiasaan...” lelaki itu bicara sambil tersenyum. Kemudian, “Eh, kapan kekasihmu itu kembali?”
“Saya tidak tahu, Pak. Kemarin dia kirim surat, katanya kapalnya berlabuh di Shouthampton dan mereka akan berada di Inggris lebih kurang seminggu. Kemudian baru melanjutkan perjalanan,” kata wanita itu agak murung.
“Kenapa kamu murung? Kamu mulai kesepian dan kehilangan?”
“Bapak, bagi saya, mencintai itu membebaskan. Saya bahagia dan tak merasa kesepian selama ini. Saya senang kalau apa yang dilakukannya itu membuatnya bahagia...”
“Seandainya, ini seandainya lho, kalau dia nanti misalnya kecantol gadis bule dan menikah di sana, bagaimana?!” kata lelaki itu dengan nada bercanda.
“Kalau dia jatuh cinta pada gadis lain, itu pasti sudah dilakukannya sejak dulu. Tetapi dia tidak melakukannya. Dan kalaupun misalnya kami tidak jadi menikah karena dia mengalihkan cintanya pada gadis lain, saya akan menerimanya dengan hati iklas. Saya tidak bisa memaksakan kehendak, Bapak, karena kalau cinta adalah sebuah paksaan, maka dia tak akan pernah berakhir bahagia. Tetapi kalau kita merelakannya dan menganggap kebahagiaannya adalah kebahagiaan kita, maka kita akan menemukan cinta yang indah. Bapak, ada cinta yang tidak menuntut apa-apa kecuali kebahagiaan orang yang kita cintai...”
Lelaki itu diam sejenak. “Seandainya semua orang seperti Anak... pasti tak ada cerita istri yang memotong kemaluan suaminya karena cemburu, atau suami yang memotong-motong tubuh kekasihnya karena motif yang sama...”
Senja hampir habis, dan lelaki itu pamit untuk pulang menemui istrinya yang setia dan anak-anaknya yang kini sudah tumbuh dewasa.
Cape Town
(Masihkah engkau di Sungai Duku, Umi?)
UMI, saat surat ini sampai kepadamu, mungkin kami sudah meninggalkan Cape Town di Afrika Selatan menuju Madagaskar. Seperti surat-surat sebelumnya, kabar kami baik-baik saja dan banyak hal yang baru yang selalu membuat kami terhibur di tengah-tengah lautan luas yang kadang tak terlihat batasnya. Namun Umi, dalam sekian waktu perjalanan ini, yang ada dalam pikiranku hanyalah engkau. Masihkah engkau berada di Sungai Duku menungguku? Ataukah engkau sudah pergi dan menikah dengan lelaki lain dan membangun rumah tangga dengan bahagia? Aku akan sedih jika itu memang terjadi padamu, Umi. Tetapi dari dulu aku memang ingin engkau bahagia, baik denganku atau tidak. Aku ingin engkau bahagia dan itu yang akan membuatku bahagia.
Namun, dengan kepergianku sekian lama, apakah engkau bahagia? Mestinya saat ini aku bersamamu, kita hidup bersama membangun cinta, tinggal di sebuah kampung dengan rumah kayu yang memiliki halaman yang luas. Di belakang rumah ada kolam ikan dan angsa-angsa putih berenang di atasnya. Di depan rumah ada lapangan sepakbola dan orang-orang kampung bermain bola setiap sore, sebuah pemandangan yang selama ini selalu aku inginkan. Aku ingin hidup seperti itu, Umi. Namun bukan berarti aku menyesali perjalananku. Aku senang karena bisa menaklukkan dunia, dan aku juga sangat senang karena sekembaliku dari perjalanan ini, aku akan melamarmu dan mewujudkan impian kita dulu. Tetapi, apakah engkau masih menungguku?
Sungai Duku
(Senja benar-benar tiba...)
MARTIN, aku masih tetap di dermaga ini. Orang-orang selalu datang dan pergi, banyak yang masih kukenal dan banyak yang tidak kukenal. Mungkin banyak orang yang sering ke sini heran melihat aku selalu berada di dermaga ini: siang, malam, pagi, siang, malam dan pagi lagi. Aku selalu menunggumu, menunggu ketidakpastianmu. Kamu tahu? Lelaki petugas pabean yang selalu menemani ngobrol, sudah meninggal hampir sepuluh tahun yang lalu, dan saat ini aku tak punya teman ngobrol lagi karena petugas yang menggantikannya dan lebih muda, tentu tak mau ngobrol dengan perempuan tua dan renta dengan rambut putih dan kulit keriput sepertiku. Aku sudah tua, Martin, aku lupa berapa umurku sekarang. Mungkin orang-orang yang lalu-lalang di sini menganggapku gembel atau pengemis, tetapi aku selalu mencuci pakaianku dan memakai minyak wangi yang harumnya dulu sangat engkau sukai.
Tertambat di manakah kapalmu saat ini, Martin? Di Madagaskar, Sri Langka, Selat Malaka ataukah hampir sampai di Sungai Duku? Aku sebenarnya capek menunggumu berpuluh-puluh tahun seperti ini, namun cinta membuatku selalu menunggumu dan melupakan semua rasa capek dan penat itu. Meski aku tak yakin engkau akan kembali ke Sungai Duku seperti janjimu dulu, tetapi aku selalu berharap dan ingin selalu memahami, bahwa cintaku tak pernah terukur dengan apapun, termasuk oleh waktu seperti sekarang ini.
Suatu saat, jika engkau memang benar-benar kembali ke Sungai Duku, aku berharap aku masih di sini, masih menunggumu seperti berpuluh-puluh tahun lalu. Bepuluh-puluh tahun yang lalu, Martin, bahkan aku sudah lupa entah sudah berapa puluh tahun. Aku tak ingin menjadi patung di sini, Martin, aku ingin tetap hidup dan memiliki harapan-harapan...
Pekanbaru, Januari 2002
ALIA, cerita tentang wanita yang selalu menunggu kekasihnya yang tak pernah kembali dari pengembaraannya itu sudah berkembang dari mulut ke mulut sejak jaman dulu, bahkan ketika aku sendiri belum lahir. Orang-orang kampung di pinggir Sungai Siak itu selalu bercerita bahwa wanita itu, hingga sekarang masih berada di Sungai Duku, sebuah pelabuhan kecil di pinggir Sungai Siak, sedikit di luar kota Pekanbaru, kota yang selama sekian tahun ini menjadi tempat pelarianku. Aku mulanya tak percaya, mana mungkin seorang wanita mau menunggu kekasihnya sejak zaman bahulea hingga sekarang. Barapa umurnya sekarang? Mereka tak ada yang memberi keterangan pasti. Katanya, wanita itu kini sudah tua sekali, berambut putih, kulit keriput, pakaian kebayanya masih tetap bersih dan tetap duduk di pinggir dermaga sambil mencelupkan kedua kakinya ke air.
Karena penasaran, aku pernah ke sana, ke Sungai Duku, untuk membuktikan cerita dari mulut ke mulut di kampung itu. Aku memang mendapati banyak wanita tua di sana, ada yang menjual makanan kecil, ada yang sedang menunggu kapal bersama keluarganya, ada yang sedang turun dari kapal dan masih banyak lagi. Yang mana wanita yang sedang menunggu kekasihnya itu? Apakah salah satu dari mereka adalah wanita yang dimaksud dari cerita penduduk kampung tersebut?
“Pokoknya wanita itu masih di sana, menunggu kekasihnya yang hingga kini tak pernah kembali,” kata salah seorang penduduk kampung tersebut.
“Ah, aku tak menemukannya. Beberapa hari terakhir ini aku ke sana,” kataku.
“Dia sudah tua, memakai pakaian kebaya, berambut putih dan duduk di pinggir dermaga,” katanya lagi.
“Banyak wanita tua yang pakai kebaya, tetapi tidak duduk di pinggir dermaga dengan mencelupkan kakinya ke air.”
“Kamu salah lihat mungkin...”
“Lalu, apakah kekasihnya yang pergi mengembara menaklukkan tujuh lautan itu pernah kembali ke Sungai Duku?” tanyaku kepada mereka.
“Entahlah. Ceritanya begalau. Ada yang mengatakan, kapal yang ditumpangi kekasihnya pecah di Selat Malaka dan seluruh awaknya meninggal, termasuk lelaki itu. Ada pula yang mengatakan, lelaki itu menikah dengan seorang wanita di Mallorca dan beranak-pinak di sana. Ada juga yang menjelaskan bahwa lelaki yang ditunggunya itu kembali ke Sungai Duku, tetapi sangat kecewa karena wanita itu sendiri menunggu bersama lelaki lain dan membangun keluarga di pinggir Sungai Duku. Entah mana yang benar...”
Alia, aku menjadi semakin penasaran dengan cerita-cerita itu. Apakah ada wanita yang begitu setia dengan menunggu kekasihnya hingga tua seperti itu? Aku tak yakin, karena itu hanya cerita dari mulut ke mulut. Tetapi, Alia, seandainya perjalananku ini memakan waktu lama, apakah engkau mau menungguku seperti wanita yang selalu menunggu kekasihnya di Sungai Duku itu?***
Pekanbaru, 26 September 2002.
Friday, November 16, 2007
Rendezvous
Cerpen Hary B Kori’un
BENAR-BENAR adakah cinta? Aku tanyakan itu kepada ibuku, dulu, ketika berbulan-bulan menemaninya di sebuah rumah sakit yang dingin dan bisu.
Dengan senyumnya yang menyejukkan, ibu selalu mengatakan bahwa salah satu karunia Tuhan yang tak bisa dihapuskan oleh siapapun adalah cinta. “Kamu bisa membayangkan, Cah Bagus, seandainya di dunia ini tak ada cinta. Seandainya orang-orang hidup tanpa cinta, semuanya akan menjadi besi, patung, gedung-gedung tua dan kemudian ambruk dimakan waktu. Tetapi cinta tidak. Dia adalah bangunan yang akan terus ada, meski kadang tak berwujud, tak kasat mata...”
Kini, perjalananku sudah setengah lebih. Subuh-subuh tadi aku berangkat dari Pekanbaru sendirian. Aku sengaja mengambil cuti hari ini. Aku ingin berada di sana, Tongar, kampung terakhir ibuku di Simpang Empat, Pasaman Barat. Ibu ulang tahun hari ini, dan aku ingin ada di dekatnya. Selalu, setiap ulang tahunnya, aku datang ke Tongar, sejak enam tahun lalu. Beberapa hari sebelumnya, aku sudah mengatakan kepada istriku dan aku berharap dia mau pergi. Tetapi pekerjaan di kantornya tak bisa ditinggalkan, dan Palagan, anakku, juga sedang ujian.
“Pergilah, katakan kepada ibu, kami tak bisa datang bersamamu. Tapi, bukankah kalian ingin rendesvouz berdua?” kata istriku sambil mencium tanganku, kemudian pipiku. Setelah itu aku mendekati Palagan yang masih tidur, mencium kedua pipinya.
Kukatakan pada istriku, bahwa ada perasaan aneh dan tak enak kali ini. Tidak seperti biasanya. Setiap aku akan pergi, yang muncul adalah perasaan sumringah. Selain akan datang di saat tahun ibu, aku juga akan pulang ke kampung tempat aku besar sebelum pergi meninggalkannya karena harus bekerja ke kota lain, berpindah-pindah. “Semoga tidak terjadi apa-apa. Hati-hati, kalau hujan dan jalan licin, jangan dipaksakan...” kata istriku lagi.
Hari memang hujan ketika aku keluar rumah, dan sepanjang jalan, ingatanku tertuju pada ibu yang memilih hidup sendirian sejak tiba di Tongar hingga akhir hayatnya. Setiap aku bertanya mengapa ibu tidak menikah lagi agar memiliki teman ketika aku pergi kuliah ke Padang dan kemungkinan akan meninggalkannya dalam waktu lama ketika berkerja di kota lain, ibu selalu mengatakan bahwa dia sudah punya janji kepada ayah. “Ayahmu menyuruh Ibu berangkat lebih dulu dengan kapal pertama, dan dia akan menyusul dalam kepulangan selanjutnya. Ibu akan tetap menunggunya di sini...” katanya berkali-kali setiap kutanya.
Dia kemudian bercerita. Pada 4 Januari 1954, rombongan pertama kepulangan orang-orang dari Suriname diberangkatkan dengan menggunakan kapal sewaan KM Langkuas, milik perusahaan pelayaran Belanda, NV Scheepvaart My Nederland.1) Sebelum naik ke atas kapal itulah untuk terakhir kalinya ibu bisa melihat ayah.
“Ibu sedang hamil 8 bulan ketika itu. Karena tidak semua keluarga bisa pulang bersama dan ayahmu tidak mendapatkan tiket, akhirnya Ibu disuruhnya pulang lebih dulu bersama kakek dan nenekmu. Dalam perjalanan setelah meninggalkan Semenanjung Pengharapan, kamu lahir di kapal. Ibu sedih karena ayahmu tidak ada ketika itu, tetapi Ibu yakin, ayahmu pasti akan berangkat dengan rombongan selanjutnya dan akan bertemu denganmu...”
Tetapi, setelah sekian tahun, ibu akhirnya tahu, bahwa ayah tidak pernah pulang, namun ibu tetap menunggunya. Ayah berkirim surat, bahwa memang tidak ada lagi kapal yang pulang ke Indonesia. Untuk pulang sendiri, ongkosnya sangat mahal. Gaji ayah sebagai tukang pos di Paramaribo tidak akan mencukupi untuk membeli tiket karena harus ke Belanda dulu. Ayah minta maaf dan selalu mengatakan bahwa dia sangat mencintai ibu dan meminta agar dikirimkan foto kami berdua kepadanya. Hingga bertahun-tahun kemudian ketika ayah memang benar-benar tak pernah kembali, ibu selalu menyimpan keyakinan bahwa ayah tetap akan kembali menyusul kami. Dan bahkan ketika akhirnya surat-surat ayah tak pernah datang lagi dan bertahun-tahun kemudian tak terdengar kabarnya, ibu juga tetap yakin bahwa ayah pasti akan menyusul kami di Tongar.
“Kita sebaiknya memang harus melupakan ayah,” kataku kemudian. Aku tak bisa membayangkan seperti apa ayahku, karena dalam surat-surat yang dikirimkan kepada ibu, tak pernah disertai foto dirinya, sementara satu-satunya foto yang disimpan di dompet ibu, sudah sangat lusuh dan gambarnya sudah buram.
“Ayahmu adalah kekuatan bagi hidup Ibu,” kata ibu sambil tersenyum dan membelai rambutku. Aku sudah tamat SMA ketika itu, dan akan melanjutkan kuliah di Padang.
“Ibu menderita karena selalu mengenang ayah...” ucapku kemudian.
Ibu menggeleng, dan di sudut matanya keluar butiran bening. “Ayahmu lelaki yang baik, berpendirian, jujur, bertanggung jawab dan selalu menepati janjinya. Ibu jatuh cinta kepadanya karena itu, bukan karena dia anak orang Jawa terpandang di Paramaribo. Kamu menuruni sifat-sifatnya Cah Bagus. Mengenangnya sepanjang hidup adalah karunia, dan dia terus ada dalam diri Ibu,” kata ibu lagi, dan butiran bening itu menetes mengenai lenganku.
“Lalu mengapa ayah membiarkan Ibu yang sedang hamil besar pulang sendiri dan tak berusaha untuk selalu bersama Ibu?” suaraku ikut serak.
“Semua orang ingin pulang dalam gelombang pertama ketika itu. Yayasan Tanah Air, yang mengurusi kepulangan kami, akhirnya mengambil keputusan, tidak semua anggota keluarga yang bisa pulang bersamaan. Ada yang bisa pulang bersamaan karena lebih dulu mendaftar, dan ada yang harus pulang terpisah. Ketika itu kami semua yakin, mereka yang ingin pulang pasti bisa pulang karena akan ada kapal lagi untuk gelombang kedua...”
“Dan kapal itu tidak pernah ada lagi, Bu?”
Ibu memandangku. “Iya....” katanya. “Dan ayahmu ternyata tidak bisa menyusul kita di sini...” suaranya terdengar lirih dan serak, menahan tangis. “Tapi Ibu selalu yakin, ayahmu pasti akan menyusul kita di sini...”
Hampir tengah hari, aku sudah melewati Bukittinggi dan sebentar lagi akan sampai di Danau Maninjau. Kabut tebal menutup Maninjau, terlihat dari pemandangan di Kelok Ampek-ampek.2) Air danau yang biasanya tenang, tak terlihat dari atas bukit. Terlihat di setiap kelokan ada rambu-rambu bertuliskan “Hati-hati” karena di kelokan ini sering terjadi kecelakaan. Setiap akan ke Tongar, aku memilih melewati jalan memotong ini karena setelah Maninjau, akan sampai ke simpang dekat Lubuk Basung dan setelah itu jalan akan lurus sepanjang lebih kurang 70 Km menuju Tongar.3)
Ketika aku tamat SMA dan kemudian melanjutkan kuliah di Padang, berat rasanya meninggalkan ibu sendirian. Namun kakek dan nenek serta saudara-saudara ibu meyakinkanku bahwa ibu akan baik-baik saja bersama mereka. Jarak Tongar dengan Padang tidak terlalu jauh, dengan bus sekitar lima jam, dan hampir setiap bulan aku pulang. Ibu sering bercerita bahwa ketika aku kecil dan sekian tahun tak ada tanda-tanda ayah akan menyusul kami, kakek dan nenek selalu mendesak agar ibu menikah lagi karena banyak lelaki yang menginginkan ibu. Aku tahu, ibu sangat cantik. Bahkan di masa tuanya, garis-garis kecantikannya mengingatkanku pada seorang bintang film idolaku yang main di film The House of The Spirits dan Out of Africa, yaitu Marryl Streep.
Kata ibu ketika itu, “Mereka tak tahu apa itu cinta dan nikmatnya menyimpan harapan sepanjang hidup. Kalau Ibu mau, Ibu bisa mendapatkan lelaki seperti apapun yang Ibu inginkan. Tetapi lelaki yang selalu Ibu inginkan hanyalah ayahmu. Cah Bagus, jika kamu memiliki cinta untuk seseorang, kejarlah cinta itu dan jangan lepaskan. Kamu akan bahagia bersama cinta itu, meski akhirnya suatu saat kalian akan terpisah...” Aku hanya mengangguk ketika itu dan masih sempat melihat ibu menoleh ke arah lain. Matanya basah.
Ketika aku tamat kuliah dan mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan pengeboran minyak di Pekanbaru, aku ingin membawa ibu ikut bersamaku. Ketika itu, persoalan tanah di Tongar sedang rumit. Ada perusahaan perkebunan sawit yang mengincar tanah orang-orang Tongar dan sekitarnya yang akan dijadikan perkebunan dan mereka telah mendapat izin dari pemerintah, hanya saja penduduk Tongar berkeras menolaknya. Aku tidak ingin ibu ikut dalam konflik itu.
Namun ibu menolaknya dan mengatakan dia akan tetap di Tongar, dia ingin ketika ayahku datang, dia ada di sana. Hatiku tersayat mendengar itu. Begitu besarnya cinta ibu untuk ayah. Adakah seseorang yang mencintai hingga seperti itu? Namun ketika ibu mulai sakit-sakitan, aku memaksa membawanya ke Pekanbaru meski ibu menolaknya. Aku tahu, aku telah mencabut semua impian dan harapannya ketika akhirnya aku merawatnya di sebuah rumah sakit di Pekanbaru. Aku hanya ingin dekat dengannya. Ibu selalu mengatakan, jika nanti dia meninggal, dia ingin dimakamkan di Tongar, dekat dengan makam kakek dan nenek.
Dan pada sebuah malam, setelah sekitar dua bulan dirawat, ibu mengatakan tiba-tiba sangat rindu kepada ayah. “Ibu tadi malam bertemu ayahmu. Dia mengajak ibu pulang ke Tongar. Ayahmu sudah berada di Tongar, Cah Bagus...” Namun kemudian dia mengusap rambutku, “Kamu harus ingat, cinta yang membuat orang hidup bahagia atau tidak. Bukan pekerjaan yang mapan, harta yang melimpah dan semua kesenangan. Cinta, Cah Bagus. Cinta...”
Esoknya, aku mengantarkan jenazah ibu ke Tongar. Ketika dia mengusap rambutku perlahan-lahan, aku tertidur, dan paginya ketika aku bangun, tangan ibu masih di kepalaku. Kulihat matanya terpejam dan bibirnya menyunggingkan senyum. Tetapi aku sadar, ibu telah benar-benar meninggalkanku.
Aku sudah sampai Simpang Empat, dan dalam hitungan menit, akan sampai ke Tongar. Sejak dari Simpang Lubuk Basung tadi, hujan terus turun meski tidak terlalu deras. Langit menghitam sepanjang perjalanan melewati hamparan kebun sawit yang kini mulai berbuah. Setiap tahun aku pulang melewati jalan ini, memang selalu ada perubahan pada pokok-pokok sawit itu.
Namun, ketika sampai di Simpang Air Gadang menuju Tongar, aku melihat keanehan. Keanehan itu semakin nyata ketika aku benar-benar memasuki Tongar. Terlihat hamparan luas tanah bekas geledoran buldozer dengan sawit-sawit muda dan baru tumbuh, nampaknya belum lama ditanam. Cepat-cepat aku menginjak gas mobil menuju tempat pemakaman umum di mana makam ibu dan keluarga besar kami ada di sana. Dan aku benar-benar tercekat ketika melihat pemandangan itu. Pemakaman umum itu telah rata dengan tanah, dan sawit-sawit muda telah tumbuh di atasnya.
Cepat-cepat aku memutar mobil dan berusaha mencari tahu di mana makam-makam itu dipindahkan. Dan ledakan tangisku tak bisa kucegah ketika Om Maksum, adik ibu, menjelaskan bahwa ketika masyarakat masih berusaha mempertahankan tanah mereka, malam hari beberapa bouldozer telah meratakan kuburan itu dan tak ada yang sempat memindahkan kuburan keluarganya. “Maafkan kami. Kami juga tak sempat memindahkan makam ibumu, juga kakek dan nenekmu...”
Hujan semakin deras, dan seperti orang gila, aku berlari ke sana-sini di bekas makam yang kini ditanami sawit itu. Kucabuti sawit-sawit itu dan kulemparkan ke segala arah. Aku menangis sejadi-jadinya dan kemudian terduduk di tanah basah yang telah menjadi lumpur. Haruskah aku menggali seluruh tanah bekas pemakaman ini untuk mencari kerangka ibu?
Senja sudah hampir habis, namun hujan tak juga berhenti. Ketika hari benar-benar gelap, Om Maksum dan beberapa orang kampung datang dan bermaksud mengajakku pulang. Namun, dengan suara nyaris tak terdengar, kukatakan pada mereka, “Biarkanlah aku di sini malam ini. Aku ingin menemani ibu. Ibu ulang tahun hari ini...”***
Pekanbaru, 18 Juni 2007
1)Di bawah pimpinan Ketua Yayasan Tanah Air, JW Kariodimedjo, rombongan berjumlah 1.014 orang itu berangkat dari pelabuhan di Paramaribo menuju Teluk Bayur di Padang. Setelah singgah di Amsterdam dan Tanjung Pengharapan (Afrika Selatan), pada 5 Februari 1954, kapal sampai di Teluk Bayur dan jumlah mereka menjadi 1.118 orang karena ada empat bayi yang lahir di kapal. Setelah menginap di Padang beberapa hari, kapal kemudian berlayar menuju pelabuhan kecil di Sasak dan sampai pada 12 Februari 1954 sebelum akhirnya berangkat menuju Desa Tongar di Kenagarian Air Gadang di Simpang Empat. Ini adalah kepulangan pertama dan terakhir orang Jawa dari Suriname. Setelah rombongan pertama ini berangkat, tidak ada rombongan kepulangan lagi, karena banyaknya pemberontakan sparatis di Indonesia seperti DI/TII, Republik Maluku Selatan, PRRI/Permesta hingga G 30 S/PKI, membuat mereka ketakutan. Koran-koran di Suriname memberitakan bahwa terjadi perang saudara di Indonesia. Lebih lengkap baca Salikin Mardi Harjo, Bunga Rampai dari Suriname (Balai Pustaka, 1989).
2)Kelok Empat-empat. Ada 44 kelokan (belokan) menuju Danau Maninjau dari arah Bukittinggi, Sumatera Barat. Ini adalah salah satu kawasan wisata yang sangat menarik di Kabupaten Agam.
3)Dari Bukittinggi, ada tiga jalan menuju Tongar. Selain lewat Maninjau, ada jalan lewat Simpang Lubuk Alung melewati Padangpanjang dan Sicincin yang nantinya akan sampai ke simpang Simpang Lubuk Basung. Jalan lainnya adalah dari Bukittinggi menuju Lubuk Sikaping, dan baru menuju Simpang Empat. Kedua jalan ini lebih jauh.
BENAR-BENAR adakah cinta? Aku tanyakan itu kepada ibuku, dulu, ketika berbulan-bulan menemaninya di sebuah rumah sakit yang dingin dan bisu.
Dengan senyumnya yang menyejukkan, ibu selalu mengatakan bahwa salah satu karunia Tuhan yang tak bisa dihapuskan oleh siapapun adalah cinta. “Kamu bisa membayangkan, Cah Bagus, seandainya di dunia ini tak ada cinta. Seandainya orang-orang hidup tanpa cinta, semuanya akan menjadi besi, patung, gedung-gedung tua dan kemudian ambruk dimakan waktu. Tetapi cinta tidak. Dia adalah bangunan yang akan terus ada, meski kadang tak berwujud, tak kasat mata...”
Kini, perjalananku sudah setengah lebih. Subuh-subuh tadi aku berangkat dari Pekanbaru sendirian. Aku sengaja mengambil cuti hari ini. Aku ingin berada di sana, Tongar, kampung terakhir ibuku di Simpang Empat, Pasaman Barat. Ibu ulang tahun hari ini, dan aku ingin ada di dekatnya. Selalu, setiap ulang tahunnya, aku datang ke Tongar, sejak enam tahun lalu. Beberapa hari sebelumnya, aku sudah mengatakan kepada istriku dan aku berharap dia mau pergi. Tetapi pekerjaan di kantornya tak bisa ditinggalkan, dan Palagan, anakku, juga sedang ujian.
“Pergilah, katakan kepada ibu, kami tak bisa datang bersamamu. Tapi, bukankah kalian ingin rendesvouz berdua?” kata istriku sambil mencium tanganku, kemudian pipiku. Setelah itu aku mendekati Palagan yang masih tidur, mencium kedua pipinya.
Kukatakan pada istriku, bahwa ada perasaan aneh dan tak enak kali ini. Tidak seperti biasanya. Setiap aku akan pergi, yang muncul adalah perasaan sumringah. Selain akan datang di saat tahun ibu, aku juga akan pulang ke kampung tempat aku besar sebelum pergi meninggalkannya karena harus bekerja ke kota lain, berpindah-pindah. “Semoga tidak terjadi apa-apa. Hati-hati, kalau hujan dan jalan licin, jangan dipaksakan...” kata istriku lagi.
Hari memang hujan ketika aku keluar rumah, dan sepanjang jalan, ingatanku tertuju pada ibu yang memilih hidup sendirian sejak tiba di Tongar hingga akhir hayatnya. Setiap aku bertanya mengapa ibu tidak menikah lagi agar memiliki teman ketika aku pergi kuliah ke Padang dan kemungkinan akan meninggalkannya dalam waktu lama ketika berkerja di kota lain, ibu selalu mengatakan bahwa dia sudah punya janji kepada ayah. “Ayahmu menyuruh Ibu berangkat lebih dulu dengan kapal pertama, dan dia akan menyusul dalam kepulangan selanjutnya. Ibu akan tetap menunggunya di sini...” katanya berkali-kali setiap kutanya.
Dia kemudian bercerita. Pada 4 Januari 1954, rombongan pertama kepulangan orang-orang dari Suriname diberangkatkan dengan menggunakan kapal sewaan KM Langkuas, milik perusahaan pelayaran Belanda, NV Scheepvaart My Nederland.1) Sebelum naik ke atas kapal itulah untuk terakhir kalinya ibu bisa melihat ayah.
“Ibu sedang hamil 8 bulan ketika itu. Karena tidak semua keluarga bisa pulang bersama dan ayahmu tidak mendapatkan tiket, akhirnya Ibu disuruhnya pulang lebih dulu bersama kakek dan nenekmu. Dalam perjalanan setelah meninggalkan Semenanjung Pengharapan, kamu lahir di kapal. Ibu sedih karena ayahmu tidak ada ketika itu, tetapi Ibu yakin, ayahmu pasti akan berangkat dengan rombongan selanjutnya dan akan bertemu denganmu...”
Tetapi, setelah sekian tahun, ibu akhirnya tahu, bahwa ayah tidak pernah pulang, namun ibu tetap menunggunya. Ayah berkirim surat, bahwa memang tidak ada lagi kapal yang pulang ke Indonesia. Untuk pulang sendiri, ongkosnya sangat mahal. Gaji ayah sebagai tukang pos di Paramaribo tidak akan mencukupi untuk membeli tiket karena harus ke Belanda dulu. Ayah minta maaf dan selalu mengatakan bahwa dia sangat mencintai ibu dan meminta agar dikirimkan foto kami berdua kepadanya. Hingga bertahun-tahun kemudian ketika ayah memang benar-benar tak pernah kembali, ibu selalu menyimpan keyakinan bahwa ayah tetap akan kembali menyusul kami. Dan bahkan ketika akhirnya surat-surat ayah tak pernah datang lagi dan bertahun-tahun kemudian tak terdengar kabarnya, ibu juga tetap yakin bahwa ayah pasti akan menyusul kami di Tongar.
“Kita sebaiknya memang harus melupakan ayah,” kataku kemudian. Aku tak bisa membayangkan seperti apa ayahku, karena dalam surat-surat yang dikirimkan kepada ibu, tak pernah disertai foto dirinya, sementara satu-satunya foto yang disimpan di dompet ibu, sudah sangat lusuh dan gambarnya sudah buram.
“Ayahmu adalah kekuatan bagi hidup Ibu,” kata ibu sambil tersenyum dan membelai rambutku. Aku sudah tamat SMA ketika itu, dan akan melanjutkan kuliah di Padang.
“Ibu menderita karena selalu mengenang ayah...” ucapku kemudian.
Ibu menggeleng, dan di sudut matanya keluar butiran bening. “Ayahmu lelaki yang baik, berpendirian, jujur, bertanggung jawab dan selalu menepati janjinya. Ibu jatuh cinta kepadanya karena itu, bukan karena dia anak orang Jawa terpandang di Paramaribo. Kamu menuruni sifat-sifatnya Cah Bagus. Mengenangnya sepanjang hidup adalah karunia, dan dia terus ada dalam diri Ibu,” kata ibu lagi, dan butiran bening itu menetes mengenai lenganku.
“Lalu mengapa ayah membiarkan Ibu yang sedang hamil besar pulang sendiri dan tak berusaha untuk selalu bersama Ibu?” suaraku ikut serak.
“Semua orang ingin pulang dalam gelombang pertama ketika itu. Yayasan Tanah Air, yang mengurusi kepulangan kami, akhirnya mengambil keputusan, tidak semua anggota keluarga yang bisa pulang bersamaan. Ada yang bisa pulang bersamaan karena lebih dulu mendaftar, dan ada yang harus pulang terpisah. Ketika itu kami semua yakin, mereka yang ingin pulang pasti bisa pulang karena akan ada kapal lagi untuk gelombang kedua...”
“Dan kapal itu tidak pernah ada lagi, Bu?”
Ibu memandangku. “Iya....” katanya. “Dan ayahmu ternyata tidak bisa menyusul kita di sini...” suaranya terdengar lirih dan serak, menahan tangis. “Tapi Ibu selalu yakin, ayahmu pasti akan menyusul kita di sini...”
Hampir tengah hari, aku sudah melewati Bukittinggi dan sebentar lagi akan sampai di Danau Maninjau. Kabut tebal menutup Maninjau, terlihat dari pemandangan di Kelok Ampek-ampek.2) Air danau yang biasanya tenang, tak terlihat dari atas bukit. Terlihat di setiap kelokan ada rambu-rambu bertuliskan “Hati-hati” karena di kelokan ini sering terjadi kecelakaan. Setiap akan ke Tongar, aku memilih melewati jalan memotong ini karena setelah Maninjau, akan sampai ke simpang dekat Lubuk Basung dan setelah itu jalan akan lurus sepanjang lebih kurang 70 Km menuju Tongar.3)
Ketika aku tamat SMA dan kemudian melanjutkan kuliah di Padang, berat rasanya meninggalkan ibu sendirian. Namun kakek dan nenek serta saudara-saudara ibu meyakinkanku bahwa ibu akan baik-baik saja bersama mereka. Jarak Tongar dengan Padang tidak terlalu jauh, dengan bus sekitar lima jam, dan hampir setiap bulan aku pulang. Ibu sering bercerita bahwa ketika aku kecil dan sekian tahun tak ada tanda-tanda ayah akan menyusul kami, kakek dan nenek selalu mendesak agar ibu menikah lagi karena banyak lelaki yang menginginkan ibu. Aku tahu, ibu sangat cantik. Bahkan di masa tuanya, garis-garis kecantikannya mengingatkanku pada seorang bintang film idolaku yang main di film The House of The Spirits dan Out of Africa, yaitu Marryl Streep.
Kata ibu ketika itu, “Mereka tak tahu apa itu cinta dan nikmatnya menyimpan harapan sepanjang hidup. Kalau Ibu mau, Ibu bisa mendapatkan lelaki seperti apapun yang Ibu inginkan. Tetapi lelaki yang selalu Ibu inginkan hanyalah ayahmu. Cah Bagus, jika kamu memiliki cinta untuk seseorang, kejarlah cinta itu dan jangan lepaskan. Kamu akan bahagia bersama cinta itu, meski akhirnya suatu saat kalian akan terpisah...” Aku hanya mengangguk ketika itu dan masih sempat melihat ibu menoleh ke arah lain. Matanya basah.
Ketika aku tamat kuliah dan mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan pengeboran minyak di Pekanbaru, aku ingin membawa ibu ikut bersamaku. Ketika itu, persoalan tanah di Tongar sedang rumit. Ada perusahaan perkebunan sawit yang mengincar tanah orang-orang Tongar dan sekitarnya yang akan dijadikan perkebunan dan mereka telah mendapat izin dari pemerintah, hanya saja penduduk Tongar berkeras menolaknya. Aku tidak ingin ibu ikut dalam konflik itu.
Namun ibu menolaknya dan mengatakan dia akan tetap di Tongar, dia ingin ketika ayahku datang, dia ada di sana. Hatiku tersayat mendengar itu. Begitu besarnya cinta ibu untuk ayah. Adakah seseorang yang mencintai hingga seperti itu? Namun ketika ibu mulai sakit-sakitan, aku memaksa membawanya ke Pekanbaru meski ibu menolaknya. Aku tahu, aku telah mencabut semua impian dan harapannya ketika akhirnya aku merawatnya di sebuah rumah sakit di Pekanbaru. Aku hanya ingin dekat dengannya. Ibu selalu mengatakan, jika nanti dia meninggal, dia ingin dimakamkan di Tongar, dekat dengan makam kakek dan nenek.
Dan pada sebuah malam, setelah sekitar dua bulan dirawat, ibu mengatakan tiba-tiba sangat rindu kepada ayah. “Ibu tadi malam bertemu ayahmu. Dia mengajak ibu pulang ke Tongar. Ayahmu sudah berada di Tongar, Cah Bagus...” Namun kemudian dia mengusap rambutku, “Kamu harus ingat, cinta yang membuat orang hidup bahagia atau tidak. Bukan pekerjaan yang mapan, harta yang melimpah dan semua kesenangan. Cinta, Cah Bagus. Cinta...”
Esoknya, aku mengantarkan jenazah ibu ke Tongar. Ketika dia mengusap rambutku perlahan-lahan, aku tertidur, dan paginya ketika aku bangun, tangan ibu masih di kepalaku. Kulihat matanya terpejam dan bibirnya menyunggingkan senyum. Tetapi aku sadar, ibu telah benar-benar meninggalkanku.
Aku sudah sampai Simpang Empat, dan dalam hitungan menit, akan sampai ke Tongar. Sejak dari Simpang Lubuk Basung tadi, hujan terus turun meski tidak terlalu deras. Langit menghitam sepanjang perjalanan melewati hamparan kebun sawit yang kini mulai berbuah. Setiap tahun aku pulang melewati jalan ini, memang selalu ada perubahan pada pokok-pokok sawit itu.
Namun, ketika sampai di Simpang Air Gadang menuju Tongar, aku melihat keanehan. Keanehan itu semakin nyata ketika aku benar-benar memasuki Tongar. Terlihat hamparan luas tanah bekas geledoran buldozer dengan sawit-sawit muda dan baru tumbuh, nampaknya belum lama ditanam. Cepat-cepat aku menginjak gas mobil menuju tempat pemakaman umum di mana makam ibu dan keluarga besar kami ada di sana. Dan aku benar-benar tercekat ketika melihat pemandangan itu. Pemakaman umum itu telah rata dengan tanah, dan sawit-sawit muda telah tumbuh di atasnya.
Cepat-cepat aku memutar mobil dan berusaha mencari tahu di mana makam-makam itu dipindahkan. Dan ledakan tangisku tak bisa kucegah ketika Om Maksum, adik ibu, menjelaskan bahwa ketika masyarakat masih berusaha mempertahankan tanah mereka, malam hari beberapa bouldozer telah meratakan kuburan itu dan tak ada yang sempat memindahkan kuburan keluarganya. “Maafkan kami. Kami juga tak sempat memindahkan makam ibumu, juga kakek dan nenekmu...”
Hujan semakin deras, dan seperti orang gila, aku berlari ke sana-sini di bekas makam yang kini ditanami sawit itu. Kucabuti sawit-sawit itu dan kulemparkan ke segala arah. Aku menangis sejadi-jadinya dan kemudian terduduk di tanah basah yang telah menjadi lumpur. Haruskah aku menggali seluruh tanah bekas pemakaman ini untuk mencari kerangka ibu?
Senja sudah hampir habis, namun hujan tak juga berhenti. Ketika hari benar-benar gelap, Om Maksum dan beberapa orang kampung datang dan bermaksud mengajakku pulang. Namun, dengan suara nyaris tak terdengar, kukatakan pada mereka, “Biarkanlah aku di sini malam ini. Aku ingin menemani ibu. Ibu ulang tahun hari ini...”***
Pekanbaru, 18 Juni 2007
1)Di bawah pimpinan Ketua Yayasan Tanah Air, JW Kariodimedjo, rombongan berjumlah 1.014 orang itu berangkat dari pelabuhan di Paramaribo menuju Teluk Bayur di Padang. Setelah singgah di Amsterdam dan Tanjung Pengharapan (Afrika Selatan), pada 5 Februari 1954, kapal sampai di Teluk Bayur dan jumlah mereka menjadi 1.118 orang karena ada empat bayi yang lahir di kapal. Setelah menginap di Padang beberapa hari, kapal kemudian berlayar menuju pelabuhan kecil di Sasak dan sampai pada 12 Februari 1954 sebelum akhirnya berangkat menuju Desa Tongar di Kenagarian Air Gadang di Simpang Empat. Ini adalah kepulangan pertama dan terakhir orang Jawa dari Suriname. Setelah rombongan pertama ini berangkat, tidak ada rombongan kepulangan lagi, karena banyaknya pemberontakan sparatis di Indonesia seperti DI/TII, Republik Maluku Selatan, PRRI/Permesta hingga G 30 S/PKI, membuat mereka ketakutan. Koran-koran di Suriname memberitakan bahwa terjadi perang saudara di Indonesia. Lebih lengkap baca Salikin Mardi Harjo, Bunga Rampai dari Suriname (Balai Pustaka, 1989).
2)Kelok Empat-empat. Ada 44 kelokan (belokan) menuju Danau Maninjau dari arah Bukittinggi, Sumatera Barat. Ini adalah salah satu kawasan wisata yang sangat menarik di Kabupaten Agam.
3)Dari Bukittinggi, ada tiga jalan menuju Tongar. Selain lewat Maninjau, ada jalan lewat Simpang Lubuk Alung melewati Padangpanjang dan Sicincin yang nantinya akan sampai ke simpang Simpang Lubuk Basung. Jalan lainnya adalah dari Bukittinggi menuju Lubuk Sikaping, dan baru menuju Simpang Empat. Kedua jalan ini lebih jauh.
Subscribe to:
Posts (Atom)