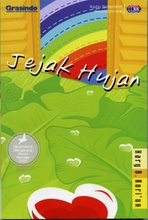Catatan Kecil Hary B Kori’un
DALAM acara diskusi tiga novel pemenang Ganti Award II 2005 (Getah Bunga Rimba [Marhalim Zaini], Jembatan [Olyrinson] dan Malam, Hujan [Hary B Kori’un, pen]) yang diadakan oleh Forum Lingkar Pena (FLP) Pekanbaru di Aula Perpustakaan Wilayah, Sabtu (11/6) lalu, salah seorang peserta yang masih sangat muda, bertanya kepada pembicara; Deded Er Moerad, Marhalim Zaini, Olyrinson dan saya sendiri (penulis). “Tadi, para pembicara mengatakan bahwa ketiga novel yang sedang didiskusikan ini berusaha membumi dan mudah dipahami oleh siapapun. Tetapi bagi saya, karya sastra, termasuk ketiga novel ini, tetap berat dan saya tidak paham apa yang dimaksudkan oleh para pengarangnya...”
Pertanyaan itu sebenarnya ditujukan kepada saya, karena sebelum gadis muda yang masih berseragam sekoah itu bertanya, saya memaparkan dan meyakinkan bahwa novel Malam, Hujan, adalah novel yang mudah dipahami, berusaha menggambarkan waktu dan tempat sedetail mungkin seolah-olah pembaca sedang menonton sebuah film, dan dengan bahasa yang tak perlu mengerutkan dahi. Namun, mendengar itu, saya menjadi mafhum dan berusaha untuk memahami kondisi masyarakat kita secara umum yang memang masih asing dengan buku. Meminjam istilah Seno Gumira Ajidarma, kita menulis di sebuah masyarakat yang tidak membaca (sesuatu yang juga dikatakan oleh Marhalim dalam peluncuran novel-novel ini di Bandar Serai beberapa waktu yang lalu).
Dalam diskusi tersebut, banyak hal yang dipaparkan baik oleh Marhalim, Deded maupun Olyrinson. Marhalim mengejaskan bahwa proses penciptaan novelnya yang kemudian menjadi novel terbaik tersebut, berawal dari kehidupan rutin ketika dia masih berada di kampung halamannya di Teluk Pambang, Bengkalis. Suasana perkampungan, kebun karet, kehidupan yang sederhana dan tenang dan ornamen-ornamen kampung lainnya, merupakan ihwal dari terciptanya ide novel itu. “Saya menulis berawal dari hal-hal biasa di sekitar saya dan ini yang selalu menjadi sumber inspirasi saya, dan untuk menambah pengayaan ide, saya membaca buku dan mempelajari lingkungan yang lain,” jelas pengajar teater di Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR) ini.
Hampir sama dengan Marhalim, Olyrinson juga menciptakan karya dengan ide dari kehidupan sehari-hari. Ide dari novel Jembatan didapatnya ketika dia pulang-pergi dari Pekanbaru-Siak dengan melewati penyeberangan di Perawang. Cerita tentang kehidupan yang biasa ini menjadi istimewa di tangan Oly karena banyak sisi humanis yang dipaparkan. “Saya tidak bisa menulis novel bagus, saya hanya bicara tentang keseharian,” jelas pegawai sebuah perusahaan kontraktor perminyakan ini.
Sementara itu Deded, seniman senior yang pernah lama tinggal di Jogjakarta, Jakarta dan Belanda, menjelaskan bahwa ketiga novel tersebut telah mampu melakukan eksplorasi estetika baik dalam bentuk maupun isi cerita. Deded mengatakan, seorang pengarang harus selalu mencari ide dan estetika dan memberikan pemikiran-pemikiran baru kepada pembacanya. “Kalau seorang pengarang tidak melakukan itu, maka ia akan ditinggalkan pembacanya,” jelas lelaki yang dekat dengan WS Rendra ini.***
BULAN Mei lalu, ketika punya kesempatan ke Surabaya, saya bertemu dengan tiga orang yang sudah eksis di dunia sastra. Mereka adalah mahaguru sastra Pak Budi Darma (saya memanggilnya “Pak” sebagai rasa hormat saya), pengarang produktif Kurnia Effendi yang sedang ada acara di Surabaya dan pengarang wanita Lan Fang yang memang tinggal di Surabaya. Kami ngobrol di rumah Pak Budi di komplek perumahan IKIP Surabaya bersama beberapa rekan yang lain.
Sangat beruntung, untuk keduakalinya saya bisa bercengkrama begitu lama dengan Pak Budi. Pertemuan pertama terjadi di Kayu Tanam, Sumatera Barat pada tahun 1997 saat Pertemuan Sastrawan Nusantara di klompleks INS Kayu Tanam. Ketika itu, saya masih hijau dan baru tumbuh sehingga saya merasa apa yang dijelaskan oleh Pak Budi dan teman-teman lainnya saat itu, terasa sulit saya cerna. Maklumlah, belum banyak buku yang saya baca karena susahnya mendapatkan buku yang bermutu baik di universitas maupun di toko buku. Untuk membeli harganya tak terjangkau oleh kantong mahasiswa, sementara tidak ada kawan yang mau meminjamkan.
Namun, kondisi ini tidak membuat saya patah semangat. Pelan tapi pasti, akhirnya saya mendapatkan beberapa buku Pak Budi seperti Olenka, Rafilus, Ny. Talis dan Orang-orang Bloomington. Belakangan cerpen-cerpennya juga mulai saya gemari seperti Mata yang Indah dan Derabat yang pernah menjadi cerpen terbaik Kompas.
Barangkali, apa yang dikatakan Pak Budi ini ada manfaatnya bagi kita. Dalam sebuah wawancara di jurnal Prosa (2003), lelaki yang selalu tampak santun, rapi, dan lembut tutur-kata ini sekali lagi mengakui, “...saya menulis tanpa saya rencanakan, dan juga tanpa draft. Andai kata menulis dapat disamakan dengan bertempur, saya hanya mengikuti mood, tanpa menggariskan strategi, tanpa pula merinci taktik. Di belakang mood, sementara itu, ada obsesi.”
Dalam perbincangan di rumahnya di malam yang hujan itu, Pak Budi lebih banyak menjadi moderator dan penyimpul diskusi, namun dengan bernas kata-katanya benar-benar mencengangkan. Misalnya, ketika kami diskusi tentang wacana muatan lokal dalam sastra Indonesia, Pak Budi mengatakan bahwa lokalitas sebuah karya itu tak bisa dipaksakan antara lokalitas daerah, lokalitas budaya atau lokalitas pemikiran. “Belum tentu seseorang yang hidup di lokalitas budaya dan daerah yang sama, memiliki lokalitas pemikiran yang sama juga,” katanya. Dia mencontohkan, pluralisme yang tumbuh di Riau. Menurutnya, lokalitas yang bisa diciptakan dengan baik di Riau adalah lokalitas daerah, tetapi tidak bisa dipaksakan lokalitas budaya dan pikiran. “Lokalitas daerah ya Riau itu. Tak bisa dipaksakan orang Minangkabau, Batak, Banjar atau Jawa yang hidup di sana, harus menulis sastra dengan latar belakang lokalitas budaya Melayu,” kata Pak Budi ketika itu.
Kembali ke pokok awal masalah tadi, bahwa apa yang dijelaskan oleh Pak Budi bagaimana proses penciptaannya, merupakan contoh bagaimana seorang pengarang menggarap ide-ide yang berbeda. Pak Budi sendiri mengakui, meski dia sudah lama tinggal dan menetap di Surabaya, namun dia sangat tidak fasih berbicara tentang kebudayaan yang berkembang di Surabaya, termasuk persoalan sosiologis masyarakat Jawa Timur yang berbeda dengan masyarakat Jawa Tengah di mana dia lahir di Rembang. Tipe masyarakat Jawa Timur cenderung terus terang dan keras, sementara Jawa Tengah lebih tertutup, mengutamakan sopan-santun dan bicara dengan lembut. “Tapi dalam proses penciptaan, saya kira seharusnya pengarang tidak harus memikirkan batasan-batasan karena itu akan memasung proses kreatifnya,” kata Guru Besar IKIP Surabaya ini.***
BEGITU keluar dari rumah Pak Budi, baik saya, Kurnia Effendi maupun Lan Fang sepanjang jalan merasakan ada hal besar dan banyak yang kami dapatkan. “Ini bedanya orang-orang muda dengan mereka yang sudah lama makan asam-garam hidup. Pak Budi banyak berkarya, dan sedikit bicara,” kata Kurnia, pengarang yang sudah menerbitkan banyak buku novel maupun kumpulan cerpen seperti Senapan Cinta, Bercinta di Bawah Bulan, Selembut Lumut Gunung, Aura Negri Cinta dan sebagainya itu.
Kurnia Effendi adalah generasi pengarang seangkatan Gus tf Sakai yang memulai menulis cerita remaja dan dimuat di Majalah Gadis, Anita Cemerlang, Aneka Ria atau Ceria Remaja. Seperti juga Gus, Kurnia juga sering memenangkan berbagai sayembara penulisan cerita (cerpen dan novel) remaja. Seiring pertumbuhan usia, keduanya juga merambah sastra serius dan karya-karyanya mulai menembus media serius seperti Horison, Kompas, Republika, Media Indonesia dan akhirnya mendapat pengakuan secara luas. “Bagi saya, menulis tak perlu memilih genre. Saya menulis apa saja yang bisa ditulis dan dikirimkan ke media yang sesuai dengan tulisan itu,” katanya suatu kali.
Akan halnya Lan Fang. Perempuan berdarah Cina ini selama ini eksis dengan dunia kepengarangan ketika cerpen maupun cerita bersambungnya memenangkan lomba yang diadakan oleh Majalah Wanita Femina atau Kartini dan beberapa novelnya yang telah menjadi buku seperti Kembang Gunung Purei, Pai Yin hingga kumpulan cerpen terbarunya, Lelaki yang Salah. Wanita kelahiran Banjarmasin ini mengakui bahwa proses kepengarangannya dilalui tanpa mencari kerumitan. “Pokoknya saya menulis cerita, banyak yang dimuat media, banyak juga yang ditolak. Tetapi saya terus menulis,” katanya.
Sebenarnya, apa yang saya tulis ini, hanya ingin memberi gambaran bahwa dunia kepenulisan itu tidak terlalu rumit, asal kita terus mau mencoba dan mencoba, termasuk membaca dan membaca. Seorang pengarang yang baik adalah ketika karyanya bisa berkomunikasi dengan pembacanya, sementara seorang pembaca yang baik adalah ketika dia bisa berkomunikasi dengan bacaannya tanpa harus mencari pemahaman dari yang lain. Semakin bingung, kan?***
Saturday, February 23, 2008
Cerita Remaja yang "Serius"
* Diskusi dan Bedah Novel “Jejak Hujan”
SABTU (12/9) lalu bertempat di Geleri Buku Ibrahami Sattah Kompleks Bandar Serai Pekanbaru, sebuah diskusi dan bedah novel berjudul Jejak Hujan karya Hary B Kori’un, diselenggarakan oleh Komunitas Paragraf. Kegiatan ini merupakan sebuah ruang bagi peminat sastra di kota ini untuk bertukar pikiran setelah kegiatan-kegiatan seperti ini akhir-akhir ini sepi. Tampil sebagai pembedah adalah Olyrinson, sastrawan muda “spesialis lomba” yang belakangan karya-karya prosanya cukup mendapat tempat di media nasional. Terakhir, cerpennya dimuat di Majalah Horison. Di awal pembicaraannya Oly mengatakan bahwa ia merasa tertantang ketika ditawari menjadi pembedah novel ini, sebab meski “hanya” berlabel novel remaja, tetapi novel ini adalah novel unggulan (10 Besar) dalam Lomba Mengarang Novel Remaja Nasional 2005 yang diselenggarakan oleh Penerbit Grasindo dan Radio Belanda.
Mulanya Oly menyangka bahwa novel ini sama dengan kebanyakan novel remaja saat ini yang bergenre teenlit atau chicklit dengan cerita cinta biasa dan hanya mengandalkan dialog tanpa penokohan dan plot yang kuat. Namun ternyata, kata Oly, “Ketika saya membaca novel ini, semua yang saya itu tak ada. Ini novel yang serius dengan penokohan dan plot yang kuat dan sangat pantas menjadi 10 Besar dari 621 naskah yang masuk dalam lomba tersebut,” jelas menulis novel Sinambela Dua Digit dan Jalan Menurun ini.
Dalam makalah panjang berjudul Jejak Hujan: Novel Remaja dengan Prespektif Dewasa, Oly membahas banyak hal yang membedakan novel ini dari novel remaja kebanyakan. Misalnya, jika biasanya novel remaja ditulis dengan ringan dengan plot linier, Jejak Hujan ditulis dengan bahasa serius, cerita yang serius dan dengan alur cerita bolak-balik sehingga kalangan remaja yang terbiasa membaca novel remaja ringan, menjadi agak berat ketika membaca novel ini. “Kita tak akan menemukan kata-kata yang sering dipakai dalam sastra remaja seperti gitu lho, dong, deh, lo, gue dan sebagainya yang selama ini menjadi pakem dalam sastra remaja,” jelas Oly yang menjadi salah satu nominator Ganti Award 2005 ini.
Dalam diskusi tersebut, Alang Rizal justru mengatakan, barangkali karena memakai bahasa serius dan cerita yang serius itu, novel ini tidak menjadi pemenang dalam lomba tersebut. “Karena mungkin yang diinginkan penyelenggara adalah karya yang ringan dan encer, sehingga novel ini gagal menjadi pemenangnya,” jelas Alang.
Peserta diskusi lainnya, sastrawan muda Griven H Putra, melihat bahwa novel Jejak Hujan memiliki kekuatan yang memang tidak dimiliki oleh novel remaja lainnya. “Keditailan penulis dalam menulis novel ini adalah salah satu kekuatannya, karena dengan begitu pengarang tidak asal menulis cerita,” jelas Griven.
Murparsaulian mempertanyakan mengapa pengarang memakai puisi Goenawan Mohammad dalam novelnya, hal yang sama juga dipertanyakan Oly dalam makalahnya. “Apakah puisi itu menguatkan atau malah melemahkan cerita? Mengapa harus puisi Goenawan, mengapa bukan puisi Marhalim Zaini atau Hang Kafrawi yang lebih dekat dengan pengarang?” tanya presenter Rtv yang juga salah seorang sastrawan perempuan Riau itu.
Dalam pembahasan sekitar penggunaan puisi berjudul “Senja pun Jadi Kecil Kota pun Jadi Putih” yang ditulis Goenawan tahun 1966 itu, Hang Kafrawi memberi pembelaan. “Bisa jadi, puisi Goenawan itu yang lebih pas mendukung cerita,” jelas Direktur Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR) ini.
Dalam diskusi berdurasi dua jam yang dipandu moderator Budy Utamy itu, Marhalim Zaini justru “menggugat” kesadaran para penulis prosa di Riau, terutama yang masih remaja, yang tidak ikut ambil bagian dalam “pesta” novel chicklit dan teenlit yang bisa menjadi proses untuk pencapaian ke sastra serius. “Saya tidak tahu apakah memang minat penulis kita yang tidak ada atau kesalahan para senior yang tak bisa membimbing para yuniornya,” jelas penulis novel Getah Bunga Rimba yang mendapatkan penghargaan utama Ganti Award 2005 ini dan juga koordinator Komunitas Paragraf yang baru saja terbentuk ini.
Dalam sesi “menjawab”, penulis novel Jejak Hujan, Hary B Kori’un menjelaskan alasannya mengutip puisi Goenawan Mohammad dalam novelnya bukan semata-mata untuk gagah-gagahan, tetapi memang karena kebutuhan cerita. “Dalam cerita itu, tokoh utama perempuan, Weny, adalah seorang anak yang cerdas dan menyukai sastra sejak kecil. Maka menurut saya, sangat wajar kalau dia sudah membaca puisi Goenawan ketika masih duduk di bangku SMP,” jelas penulis yang sudah menerbitkan empat novelnya ini.
Di bagian lain, Hary juga menjelaskan bahwa ketika dia mengikuti lomba mengarang novel tersebut, dia tidak yakin novelnya akan masuk penilaian, karena novel Jejak Hujan bukanlah novel genre remaja, tetapi novel serius. Maka, menurutnya, ketika dia tahu novelnya masuk nominasi, itu sebuah kejutan baginya. “Dan ketika saya bertemu dengan dua orang jurinya, yakni Veven SP Wardana dan Maman S Mahayana, baru saya yakin bahwa juri memang bekerja keras dalam lomba ini. Menurut mereka, novel saya memang tak bergenre remaja, tetapi sayang kalau dimasukkan dalam tong sampah dalam lomba itu karena katanya secara kualitas lumayan,” jelasnya.(riau pos)
SABTU (12/9) lalu bertempat di Geleri Buku Ibrahami Sattah Kompleks Bandar Serai Pekanbaru, sebuah diskusi dan bedah novel berjudul Jejak Hujan karya Hary B Kori’un, diselenggarakan oleh Komunitas Paragraf. Kegiatan ini merupakan sebuah ruang bagi peminat sastra di kota ini untuk bertukar pikiran setelah kegiatan-kegiatan seperti ini akhir-akhir ini sepi. Tampil sebagai pembedah adalah Olyrinson, sastrawan muda “spesialis lomba” yang belakangan karya-karya prosanya cukup mendapat tempat di media nasional. Terakhir, cerpennya dimuat di Majalah Horison. Di awal pembicaraannya Oly mengatakan bahwa ia merasa tertantang ketika ditawari menjadi pembedah novel ini, sebab meski “hanya” berlabel novel remaja, tetapi novel ini adalah novel unggulan (10 Besar) dalam Lomba Mengarang Novel Remaja Nasional 2005 yang diselenggarakan oleh Penerbit Grasindo dan Radio Belanda.
Mulanya Oly menyangka bahwa novel ini sama dengan kebanyakan novel remaja saat ini yang bergenre teenlit atau chicklit dengan cerita cinta biasa dan hanya mengandalkan dialog tanpa penokohan dan plot yang kuat. Namun ternyata, kata Oly, “Ketika saya membaca novel ini, semua yang saya itu tak ada. Ini novel yang serius dengan penokohan dan plot yang kuat dan sangat pantas menjadi 10 Besar dari 621 naskah yang masuk dalam lomba tersebut,” jelas menulis novel Sinambela Dua Digit dan Jalan Menurun ini.
Dalam makalah panjang berjudul Jejak Hujan: Novel Remaja dengan Prespektif Dewasa, Oly membahas banyak hal yang membedakan novel ini dari novel remaja kebanyakan. Misalnya, jika biasanya novel remaja ditulis dengan ringan dengan plot linier, Jejak Hujan ditulis dengan bahasa serius, cerita yang serius dan dengan alur cerita bolak-balik sehingga kalangan remaja yang terbiasa membaca novel remaja ringan, menjadi agak berat ketika membaca novel ini. “Kita tak akan menemukan kata-kata yang sering dipakai dalam sastra remaja seperti gitu lho, dong, deh, lo, gue dan sebagainya yang selama ini menjadi pakem dalam sastra remaja,” jelas Oly yang menjadi salah satu nominator Ganti Award 2005 ini.
Dalam diskusi tersebut, Alang Rizal justru mengatakan, barangkali karena memakai bahasa serius dan cerita yang serius itu, novel ini tidak menjadi pemenang dalam lomba tersebut. “Karena mungkin yang diinginkan penyelenggara adalah karya yang ringan dan encer, sehingga novel ini gagal menjadi pemenangnya,” jelas Alang.
Peserta diskusi lainnya, sastrawan muda Griven H Putra, melihat bahwa novel Jejak Hujan memiliki kekuatan yang memang tidak dimiliki oleh novel remaja lainnya. “Keditailan penulis dalam menulis novel ini adalah salah satu kekuatannya, karena dengan begitu pengarang tidak asal menulis cerita,” jelas Griven.
Murparsaulian mempertanyakan mengapa pengarang memakai puisi Goenawan Mohammad dalam novelnya, hal yang sama juga dipertanyakan Oly dalam makalahnya. “Apakah puisi itu menguatkan atau malah melemahkan cerita? Mengapa harus puisi Goenawan, mengapa bukan puisi Marhalim Zaini atau Hang Kafrawi yang lebih dekat dengan pengarang?” tanya presenter Rtv yang juga salah seorang sastrawan perempuan Riau itu.
Dalam pembahasan sekitar penggunaan puisi berjudul “Senja pun Jadi Kecil Kota pun Jadi Putih” yang ditulis Goenawan tahun 1966 itu, Hang Kafrawi memberi pembelaan. “Bisa jadi, puisi Goenawan itu yang lebih pas mendukung cerita,” jelas Direktur Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR) ini.
Dalam diskusi berdurasi dua jam yang dipandu moderator Budy Utamy itu, Marhalim Zaini justru “menggugat” kesadaran para penulis prosa di Riau, terutama yang masih remaja, yang tidak ikut ambil bagian dalam “pesta” novel chicklit dan teenlit yang bisa menjadi proses untuk pencapaian ke sastra serius. “Saya tidak tahu apakah memang minat penulis kita yang tidak ada atau kesalahan para senior yang tak bisa membimbing para yuniornya,” jelas penulis novel Getah Bunga Rimba yang mendapatkan penghargaan utama Ganti Award 2005 ini dan juga koordinator Komunitas Paragraf yang baru saja terbentuk ini.
Dalam sesi “menjawab”, penulis novel Jejak Hujan, Hary B Kori’un menjelaskan alasannya mengutip puisi Goenawan Mohammad dalam novelnya bukan semata-mata untuk gagah-gagahan, tetapi memang karena kebutuhan cerita. “Dalam cerita itu, tokoh utama perempuan, Weny, adalah seorang anak yang cerdas dan menyukai sastra sejak kecil. Maka menurut saya, sangat wajar kalau dia sudah membaca puisi Goenawan ketika masih duduk di bangku SMP,” jelas penulis yang sudah menerbitkan empat novelnya ini.
Di bagian lain, Hary juga menjelaskan bahwa ketika dia mengikuti lomba mengarang novel tersebut, dia tidak yakin novelnya akan masuk penilaian, karena novel Jejak Hujan bukanlah novel genre remaja, tetapi novel serius. Maka, menurutnya, ketika dia tahu novelnya masuk nominasi, itu sebuah kejutan baginya. “Dan ketika saya bertemu dengan dua orang jurinya, yakni Veven SP Wardana dan Maman S Mahayana, baru saya yakin bahwa juri memang bekerja keras dalam lomba ini. Menurut mereka, novel saya memang tak bergenre remaja, tetapi sayang kalau dimasukkan dalam tong sampah dalam lomba itu karena katanya secara kualitas lumayan,” jelasnya.(riau pos)
esai
Belajar Membaca dan Menulis (Sastra)
Catatan Kecil Hary B Kori’un
DALAM acara diskusi tiga novel pemenang Ganti Award II 2005 (Getah Bunga Rimba [Marhalim Zaini], [Olyrinson] dan Malam, Hujan [Hary B Kori’un, pen]) yang diadakan oleh Forum Lingkar Pena (FLP) Pekanbaru di Aula Perpustakaan Wilayah, Sabtu (11/6) lalu, salah seorang peserta yang masih sangat muda, bertanya kepada pembicara; Deded Er Moerad, Marhalim Zaini, Olyrinson dan saya sendiri (penulis). “Tadi, para pembicara mengatakan bahwa ketiga novel yang sedang didiskusikan ini berusaha membumi dan mudah dipahami oleh siapapun. Tetapi bagi saya, karya sastra, termasuk ketiga novel ini, tetap berat dan saya tidak paham apa yang dimaksudkan oleh para pengarangnya...”
Pertanyaan itu sebenarnya ditujukan kepada saya, karena sebelum gadis muda yang masih berseragam sekoah itu bertanya, saya memaparkan dan meyakinkan bahwa novel Malam, Hujan, adalah novel yang mudah dipahami, berusaha menggambarkan waktu dan tempat sedetail mungkin seolah-olah pembaca sedang menonton sebuah film, dan dengan bahasa yang tak perlu mengerutkan dahi. Namun, mendengar itu, saya menjadi mafhum dan berusaha untuk memahami kondisi masyarakat kita secara umum yang memang masih asing dengan buku. Meminjam istilah Seno Gumira Ajidarma, kita menulis di sebuah masyarakat yang tidak membaca (sesuatu yang juga dikatakan oleh Marhalim dalam peluncuran novel-novel ini di Bandar Serai beberapa waktu yang lalu).
Dalam diskusi tersebut, banyak hal yang dipaparkan baik oleh Marhalim, Deded maupun Olyrinson. Marhalim mengejaskan bahwa proses penciptaan novelnya yang kemudian menjadi novel terbaik tersebut, berawal dari kehidupan rutin ketika dia masih berada di kampung halamannya di Teluk Pambang, Bengkalis. Suasana perkampungan, kebun karet, kehidupan yang sederhana dan tenang dan ornamen-ornamen kampung lainnya, merupakan ihwal dari terciptanya ide novel itu. “Saya menulis berawal dari hal-hal biasa di sekitar saya dan ini yang selalu menjadi sumber inspirasi saya, dan untuk menambah pengayaan ide, saya membaca buku dan mempelajari lingkungan yang lain,” jelas pengajar teater di Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR) ini.
Hampir sama dengan Marhalim, Olyrinson juga menciptakan karya dengan ide dari kehidupan sehari-hari. Ide dari novel Jembatan didapatnya ketika dia pulang-pergi dari Pekanbaru-Siak dengan melewati penyeberangan di Perawang. Cerita tentang kehidupan yang biasa ini menjadi istimewa di tangan Oly karena banyak sisi humanis yang dipaparkan. “Saya tidak bisa menulis novel bagus, saya hanya bicara tentang keseharian,” jelas pegawai sebuah perusahaan kontraktor perminyakan ini.
Sementara itu Deded, seniman senior yang pernah lama tinggal di Jogjakarta, Jakarta dan Belanda, menjelaskan bahwa ketiga novel tersebut telah mampu melakukan eksplorasi estetika baik dalam bentuk maupun isi cerita. Deded mengatakan, seorang pengarang harus selalu mencari ide dan estetika dan memberikan pemikiran-pemikiran baru kepada pembacanya. “Kalau seorang pengarang tidak melakukan itu, maka ia akan ditinggalkan pembacanya,” jelas lelaki yang dekat dengan WS Rendra ini.***
BULAN Mei lalu, ketika punya kesempatan ke Surabaya, saya bertemu dengan tiga orang yang sudah eksis di dunia sastra. Mereka adalah mahaguru sastra Pak Budi Darma (saya memanggilnya “Pak” sebagai rasa hormat saya), pengarang produktif Kurnia Effendi yang sedang ada acara di Surabaya dan pengarang wanita Lan Fang yang memang tinggal di Surabaya. Kami ngobrol di rumah Pak Budi di komplek perumahan IKIP Surabaya bersama beberapa rekan yang lain.
Sangat beruntung, untuk keduakalinya saya bisa bercengkrama begitu lama dengan Pak Budi. Pertemuan pertama terjadi di Kayu Tanam, Sumatera Barat pada tahun 1997 saat Pertemuan Sastrawan Nusantara di klompleks INS Kayu Tanam. Ketika itu, saya masih hijau dan baru tumbuh sehingga saya merasa apa yang dijelaskan oleh Pak Budi dan teman-teman lainnya saat itu, terasa sulit saya cerna. Maklumlah, belum banyak buku yang saya baca karena susahnya mendapatkan buku yang bermutu baik di universitas maupun di toko buku. Untuk membeli harganya tak terjangkau oleh kantong mahasiswa, sementara tidak ada kawan yang mau meminjamkan.
Namun, kondisi ini tidak membuat saya patah semangat. Pelan tapi pasti, akhirnya saya mendapatkan beberapa buku Pak Budi seperti Olenka, Rafilus, Ny. Talis dan Orang-orang Bloomington. Belakangan cerpen-cerpennya juga mulai saya gemari seperti Mata yang Indah dan Derabat yang pernah menjadi cerpen terbaik Kompas.
Barangkali, apa yang dikatakan Pak Budi ini ada manfaatnya bagi kita. Dalam sebuah wawancara di jurnal Prosa (2003), lelaki yang selalu tampak santun, rapi, dan lembut tutur-kata ini sekali lagi mengakui, “...saya menulis tanpa saya rencanakan, dan juga tanpa draft. Andai kata menulis dapat disamakan dengan bertempur, saya hanya mengikuti mood, tanpa menggariskan strategi, tanpa pula merinci taktik. Di belakang mood, sementara itu, ada obsesi.”
Dalam perbincangan di rumahnya di malam yang hujan itu, Pak Budi lebih banyak menjadi moderator dan penyimpul diskusi, namun dengan bernas kata-katanya benar-benar mencengangkan. Misalnya, ketika kami diskusi tentang wacana muatan lokal dalam sastra Indonesia, Pak Budi mengatakan bahwa lokalitas sebuah karya itu tak bisa dipaksakan antara lokalitas daerah, lokalitas budaya atau lokalitas pemikiran. “Belum tentu seseorang yang hidup di lokalitas budaya dan daerah yang sama, memiliki lokalitas pemikiran yang sama juga,” katanya. Dia mencontohkan, pluralisme yang tumbuh di Riau. Menurutnya, lokalitas yang bisa diciptakan dengan baik di Riau adalah lokalitas daerah, tetapi tidak bisa dipaksakan lokalitas budaya dan pikiran. “Lokalitas daerah ya Riau itu. Tak bisa dipaksakan orang Minangkabau, Batak, Banjar atau Jawa yang hidup di sana, harus menulis sastra dengan latar belakang lokalitas budaya Melayu,” kata Pak Budi ketika itu.
Kembali ke pokok awal masalah tadi, bahwa apa yang dijelaskan oleh Pak Budi bagaimana proses penciptaannya, merupakan contoh bagaimana seorang pengarang menggarap ide-ide yang berbeda. Pak Budi sendiri mengakui, meski dia sudah lama tinggal dan menetap di Surabaya, namun dia sangat tidak fasih berbicara tentang kebudayaan yang berkembang di Surabaya, termasuk persoalan sosiologis masyarakat Jawa Timur yang berbeda dengan masyarakat Jawa Tengah di mana dia lahir di Rembang. Tipe masyarakat Jawa Timur cenderung terus terang dan keras, sementara Jawa Tengah lebih tertutup, mengutamakan sopan-santun dan bicara dengan lembut. “Tapi dalam proses penciptaan, saya kira seharusnya pengarang tidak harus memikirkan batasan-batasan karena itu akan memasung proses kreatifnya,” kata Guru Besar IKIP Surabaya ini.***
BEGITU keluar dari rumah Pak Budi, baik saya, Kurnia Effendi maupun Lan Fang sepanjang jalan merasakan ada hal besar dan banyak yang kami dapatkan. “Ini bedanya orang-orang muda dengan mereka yang sudah lama makan asam-garam hidup. Pak Budi banyak berkarya, dan sedikit bicara,” kata Kurnia, pengarang yang sudah menerbitkan banyak buku novel maupun kumpulan cerpen seperti Senapan Cinta, Bercinta di Bawah Bulan, Selembut Lumut Gunung, Aura Negri Cinta dan sebagainya itu.
Kurnia Effendi adalah generasi pengarang seangkatan Gus tf Sakai yang memulai menulis cerita remaja dan dimuat di Majalah Gadis, Anita Cemerlang, Aneka Ria atau Ceria Remaja. Seperti juga Gus, Kurnia juga sering memenangkan berbagai sayembara penulisan cerita (cerpen dan novel) remaja. Seiring pertumbuhan usia, keduanya juga merambah sastra serius dan karya-karyanya mulai menembus media serius seperti Horison, Kompas, Republika, Media Indonesia dan akhirnya mendapat pengakuan secara luas. “Bagi saya, menulis tak perlu memilih genre. Saya menulis apa saja yang bisa ditulis dan dikirimkan ke media yang sesuai dengan tulisan itu,” katanya suatu kali.
Akan halnya Lan Fang. Perempuan berdarah Cina ini selama ini eksis dengan dunia kepengarangan ketika cerpen maupun cerita bersambungnya memenangkan lomba yang diadakan oleh Majalah Wanita Femina atau Kartini dan beberapa novelnya yang telah menjadi buku seperti Kembang Gunung Purei, Pai Yin hingga kumpulan cerpen terbarunya, Lelaki yang Salah. Wanita kelahiran Banjarmasin ini mengakui bahwa proses kepengarangannya dilalui tanpa mencari kerumitan. “Pokoknya saya menulis cerita, banyak yang dimuat media, banyak juga yang ditolak. Tetapi saya terus menulis,” katanya.
Sebenarnya, apa yang saya tulis ini, hanya ingin memberi gambaran bahwa dunia kepenulisan itu tidak terlalu rumit, asal kita terus mau mencoba dan mencoba, termasuk membaca dan membaca. Seorang pengarang yang baik adalah ketika karyanya bisa berkomunikasi dengan pembacanya, sementara seorang pembaca yang baik adalah ketika dia bisa berkomunikasi dengan bacaannya tanpa harus mencari pemahaman dari yang lain. Semakin bingung, kan?***
Catatan Kecil Hary B Kori’un
DALAM acara diskusi tiga novel pemenang Ganti Award II 2005 (Getah Bunga Rimba [Marhalim Zaini], [Olyrinson] dan Malam, Hujan [Hary B Kori’un, pen]) yang diadakan oleh Forum Lingkar Pena (FLP) Pekanbaru di Aula Perpustakaan Wilayah, Sabtu (11/6) lalu, salah seorang peserta yang masih sangat muda, bertanya kepada pembicara; Deded Er Moerad, Marhalim Zaini, Olyrinson dan saya sendiri (penulis). “Tadi, para pembicara mengatakan bahwa ketiga novel yang sedang didiskusikan ini berusaha membumi dan mudah dipahami oleh siapapun. Tetapi bagi saya, karya sastra, termasuk ketiga novel ini, tetap berat dan saya tidak paham apa yang dimaksudkan oleh para pengarangnya...”
Pertanyaan itu sebenarnya ditujukan kepada saya, karena sebelum gadis muda yang masih berseragam sekoah itu bertanya, saya memaparkan dan meyakinkan bahwa novel Malam, Hujan, adalah novel yang mudah dipahami, berusaha menggambarkan waktu dan tempat sedetail mungkin seolah-olah pembaca sedang menonton sebuah film, dan dengan bahasa yang tak perlu mengerutkan dahi. Namun, mendengar itu, saya menjadi mafhum dan berusaha untuk memahami kondisi masyarakat kita secara umum yang memang masih asing dengan buku. Meminjam istilah Seno Gumira Ajidarma, kita menulis di sebuah masyarakat yang tidak membaca (sesuatu yang juga dikatakan oleh Marhalim dalam peluncuran novel-novel ini di Bandar Serai beberapa waktu yang lalu).
Dalam diskusi tersebut, banyak hal yang dipaparkan baik oleh Marhalim, Deded maupun Olyrinson. Marhalim mengejaskan bahwa proses penciptaan novelnya yang kemudian menjadi novel terbaik tersebut, berawal dari kehidupan rutin ketika dia masih berada di kampung halamannya di Teluk Pambang, Bengkalis. Suasana perkampungan, kebun karet, kehidupan yang sederhana dan tenang dan ornamen-ornamen kampung lainnya, merupakan ihwal dari terciptanya ide novel itu. “Saya menulis berawal dari hal-hal biasa di sekitar saya dan ini yang selalu menjadi sumber inspirasi saya, dan untuk menambah pengayaan ide, saya membaca buku dan mempelajari lingkungan yang lain,” jelas pengajar teater di Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR) ini.
Hampir sama dengan Marhalim, Olyrinson juga menciptakan karya dengan ide dari kehidupan sehari-hari. Ide dari novel Jembatan didapatnya ketika dia pulang-pergi dari Pekanbaru-Siak dengan melewati penyeberangan di Perawang. Cerita tentang kehidupan yang biasa ini menjadi istimewa di tangan Oly karena banyak sisi humanis yang dipaparkan. “Saya tidak bisa menulis novel bagus, saya hanya bicara tentang keseharian,” jelas pegawai sebuah perusahaan kontraktor perminyakan ini.
Sementara itu Deded, seniman senior yang pernah lama tinggal di Jogjakarta, Jakarta dan Belanda, menjelaskan bahwa ketiga novel tersebut telah mampu melakukan eksplorasi estetika baik dalam bentuk maupun isi cerita. Deded mengatakan, seorang pengarang harus selalu mencari ide dan estetika dan memberikan pemikiran-pemikiran baru kepada pembacanya. “Kalau seorang pengarang tidak melakukan itu, maka ia akan ditinggalkan pembacanya,” jelas lelaki yang dekat dengan WS Rendra ini.***
BULAN Mei lalu, ketika punya kesempatan ke Surabaya, saya bertemu dengan tiga orang yang sudah eksis di dunia sastra. Mereka adalah mahaguru sastra Pak Budi Darma (saya memanggilnya “Pak” sebagai rasa hormat saya), pengarang produktif Kurnia Effendi yang sedang ada acara di Surabaya dan pengarang wanita Lan Fang yang memang tinggal di Surabaya. Kami ngobrol di rumah Pak Budi di komplek perumahan IKIP Surabaya bersama beberapa rekan yang lain.
Sangat beruntung, untuk keduakalinya saya bisa bercengkrama begitu lama dengan Pak Budi. Pertemuan pertama terjadi di Kayu Tanam, Sumatera Barat pada tahun 1997 saat Pertemuan Sastrawan Nusantara di klompleks INS Kayu Tanam. Ketika itu, saya masih hijau dan baru tumbuh sehingga saya merasa apa yang dijelaskan oleh Pak Budi dan teman-teman lainnya saat itu, terasa sulit saya cerna. Maklumlah, belum banyak buku yang saya baca karena susahnya mendapatkan buku yang bermutu baik di universitas maupun di toko buku. Untuk membeli harganya tak terjangkau oleh kantong mahasiswa, sementara tidak ada kawan yang mau meminjamkan.
Namun, kondisi ini tidak membuat saya patah semangat. Pelan tapi pasti, akhirnya saya mendapatkan beberapa buku Pak Budi seperti Olenka, Rafilus, Ny. Talis dan Orang-orang Bloomington. Belakangan cerpen-cerpennya juga mulai saya gemari seperti Mata yang Indah dan Derabat yang pernah menjadi cerpen terbaik Kompas.
Barangkali, apa yang dikatakan Pak Budi ini ada manfaatnya bagi kita. Dalam sebuah wawancara di jurnal Prosa (2003), lelaki yang selalu tampak santun, rapi, dan lembut tutur-kata ini sekali lagi mengakui, “...saya menulis tanpa saya rencanakan, dan juga tanpa draft. Andai kata menulis dapat disamakan dengan bertempur, saya hanya mengikuti mood, tanpa menggariskan strategi, tanpa pula merinci taktik. Di belakang mood, sementara itu, ada obsesi.”
Dalam perbincangan di rumahnya di malam yang hujan itu, Pak Budi lebih banyak menjadi moderator dan penyimpul diskusi, namun dengan bernas kata-katanya benar-benar mencengangkan. Misalnya, ketika kami diskusi tentang wacana muatan lokal dalam sastra Indonesia, Pak Budi mengatakan bahwa lokalitas sebuah karya itu tak bisa dipaksakan antara lokalitas daerah, lokalitas budaya atau lokalitas pemikiran. “Belum tentu seseorang yang hidup di lokalitas budaya dan daerah yang sama, memiliki lokalitas pemikiran yang sama juga,” katanya. Dia mencontohkan, pluralisme yang tumbuh di Riau. Menurutnya, lokalitas yang bisa diciptakan dengan baik di Riau adalah lokalitas daerah, tetapi tidak bisa dipaksakan lokalitas budaya dan pikiran. “Lokalitas daerah ya Riau itu. Tak bisa dipaksakan orang Minangkabau, Batak, Banjar atau Jawa yang hidup di sana, harus menulis sastra dengan latar belakang lokalitas budaya Melayu,” kata Pak Budi ketika itu.
Kembali ke pokok awal masalah tadi, bahwa apa yang dijelaskan oleh Pak Budi bagaimana proses penciptaannya, merupakan contoh bagaimana seorang pengarang menggarap ide-ide yang berbeda. Pak Budi sendiri mengakui, meski dia sudah lama tinggal dan menetap di Surabaya, namun dia sangat tidak fasih berbicara tentang kebudayaan yang berkembang di Surabaya, termasuk persoalan sosiologis masyarakat Jawa Timur yang berbeda dengan masyarakat Jawa Tengah di mana dia lahir di Rembang. Tipe masyarakat Jawa Timur cenderung terus terang dan keras, sementara Jawa Tengah lebih tertutup, mengutamakan sopan-santun dan bicara dengan lembut. “Tapi dalam proses penciptaan, saya kira seharusnya pengarang tidak harus memikirkan batasan-batasan karena itu akan memasung proses kreatifnya,” kata Guru Besar IKIP Surabaya ini.***
BEGITU keluar dari rumah Pak Budi, baik saya, Kurnia Effendi maupun Lan Fang sepanjang jalan merasakan ada hal besar dan banyak yang kami dapatkan. “Ini bedanya orang-orang muda dengan mereka yang sudah lama makan asam-garam hidup. Pak Budi banyak berkarya, dan sedikit bicara,” kata Kurnia, pengarang yang sudah menerbitkan banyak buku novel maupun kumpulan cerpen seperti Senapan Cinta, Bercinta di Bawah Bulan, Selembut Lumut Gunung, Aura Negri Cinta dan sebagainya itu.
Kurnia Effendi adalah generasi pengarang seangkatan Gus tf Sakai yang memulai menulis cerita remaja dan dimuat di Majalah Gadis, Anita Cemerlang, Aneka Ria atau Ceria Remaja. Seperti juga Gus, Kurnia juga sering memenangkan berbagai sayembara penulisan cerita (cerpen dan novel) remaja. Seiring pertumbuhan usia, keduanya juga merambah sastra serius dan karya-karyanya mulai menembus media serius seperti Horison, Kompas, Republika, Media Indonesia dan akhirnya mendapat pengakuan secara luas. “Bagi saya, menulis tak perlu memilih genre. Saya menulis apa saja yang bisa ditulis dan dikirimkan ke media yang sesuai dengan tulisan itu,” katanya suatu kali.
Akan halnya Lan Fang. Perempuan berdarah Cina ini selama ini eksis dengan dunia kepengarangan ketika cerpen maupun cerita bersambungnya memenangkan lomba yang diadakan oleh Majalah Wanita Femina atau Kartini dan beberapa novelnya yang telah menjadi buku seperti Kembang Gunung Purei, Pai Yin hingga kumpulan cerpen terbarunya, Lelaki yang Salah. Wanita kelahiran Banjarmasin ini mengakui bahwa proses kepengarangannya dilalui tanpa mencari kerumitan. “Pokoknya saya menulis cerita, banyak yang dimuat media, banyak juga yang ditolak. Tetapi saya terus menulis,” katanya.
Sebenarnya, apa yang saya tulis ini, hanya ingin memberi gambaran bahwa dunia kepenulisan itu tidak terlalu rumit, asal kita terus mau mencoba dan mencoba, termasuk membaca dan membaca. Seorang pengarang yang baik adalah ketika karyanya bisa berkomunikasi dengan pembacanya, sementara seorang pembaca yang baik adalah ketika dia bisa berkomunikasi dengan bacaannya tanpa harus mencari pemahaman dari yang lain. Semakin bingung, kan?***
Novel

Malam, Hujan
Oleh Hary B Kori'un
Prolog
KATA orang, hidup adalah sebuah proses memenuhi takdir yang memang sudah dari awal digariskan kepada seseorang. Takdir dan nasib, adalah dua kata yang sama maknanya, tetapi ternyata berbeda dalam penjabarannya. Takdir datang tanpa bisa kita mencegahnya dan dia adalah sebuah bagian dari hidup sampai ke muara akhirnya. Berbeda dengan nasib, dia adalah putaran peristiwa-peristiwa yang muncul dalam fase-fase tertentu hidup manusia yang kita bisa dan boleh menawar dan melawannya. Manusia tidak boleh menyerah pada nasib, karena nasib bisa dirubah. Tetapi, melawan takdir adalah suatu hal yang sulit dilakukan. Entahlah, kadang aku sendiri bingung dengan apa yang terjadi. Lalu, mengapa aku harus mendifinisikan dua kata itu?
Aku ingin bercerita kepadamu, tentang takdir dan nasib itu. Tentang takdir dan nasib yang membuat aku kemudian menjadi paham bahwa hidup ternyata hanya bisa kita jalani, tanpa bisa kita miliki sepenuhnya. Takdir dan nasib yang membawaku pada sebuah kesimpulan, bahwa kadang-kadang kita harus kompromi dengan keadaan, dengan kenyataan dan dengan takdir itu sendiri. Aku ingin bercerita tentang seseorang yang berusaha melawan takdir dan nasibnya, tetapi menjalani hidupnya dengan mengalir bersama air. Kadang mulus dalam aliran, kadang tersangkut akar atau semak belukar. Dia menerima masa lalu buruknya tanpa harus dendam dan membenci sesiapa. Dia ingin mengubah masa depannya, namun tidak tahu jalan apa yang harus dilaluinya untuk menuju ke sana. Aku pernah memiliki keinginan untuk menuntunnya, atau bersama-sama menuju masa di depan itu, tetapi ternyata dia memiliki dunianya sendiri, dunia yang kadang-kadang tak tersentuh oleh pikiran, juga logika-logikaku, meski aku berusaha untuk menjadi paham dengan apa yang dilakukannya.
Aku ingin bercerita tentang malam dan hujan, dan seorang Iman yang berada di dalamnya, terseret dalam arus deras yang membuatnya kemudian berpikir bahwa takdir memang benar-benar tak bisa dicegah dan dilawan dengan apapun. Dia hanya bisa melawan nasib dan membelok-belokkannya, tetapi dia tak kuasa melawan takdir, sebuah kenyataan dalam dirinya bahwa manusia hanya bisa melakukan, tanpa bisa memastikan hasil akhirnya.
Seorang Iman, yang pernah datang dalam duniaku, saat malam dan hujan yang benar-benar menjadi cerita-cerita yang mengerikan baginya...
Bagian I
AKU memanggilmu kekasih. Tidak seperti lelaki yang datang sebelum dirimu, aku memberi panggilan khusus bagimu. Aku tak tahu apakah ini akan menjadi penting bagimu, tetapi aku sangat paham bahwa kehidupanmu yang tak teratur dan membingungkan bagiku, membuatku harus memberikan ingatan khusus di pikiranku bahwa kamu memang berbeda dari laki-laki lain yang pernah kukenal. Aku tak peduli apapun, bahkan ketika semua orang tak percaya bahwa aku bisa jatuh cinta kepada laki-laki seperti kamu: gondrong, kumal, kadang bau dan tak beraturan. Tetapi kamu adalah pilihanku, dan aku tak peduli apapun.
“Apa tidak ada laki-laki lain yang mau sama kamu, sampai kamu harus mati-matian mempertahankan dan membela dia?” Itu kata Rahayu, redaktur life style, orang yang memang selalu melihat seseorang dari penampilannya, gaya hidupnya dan segala yang berhubungan dengan penampakan dari luar. Aku bisa maklum. Aku hanya tersenyum mendengar itu.
“Flo yang cantik, coba deh kamu pikirkan lagi, dibanding dengan cowok-cowokmu sebelumnya, dia toh tak ada apa-apanya. Masa depan nampaknya suram: mobil atau motor gak ada, pakaian kumal, bau badan kacau... aduh, bisa buram duniamu...” yang ini kalimat Lili Darmasari, reporter yang setiap hari memang meliput tentang fashion show dan segala jenis selebritis. Kata orang, bahkan gaya hidupnya lebih selebritis dari selebritis sendiri.
Aku sebenarnya marah mereka memperlakukan kamu seperti itu. Tetapi aku tak akan melakukannya di depan mereka, toh mereka tidak mengenalmu, aku yang mengenalmu. Aku ingin katakan kepada mereka bahwa aku benar-benar menginginkanmu dengan semua yang kamu miliki. Bukan hanya sekedar kepemilikan tubuh, tetapi lebih dari itu, sesuatu yang tak kupahami bentuknya. Aku tak peduli dengan apa yang mereka katakan. Sungguh, aku benar-benar tak peduli, aku hanya peduli dengan jalan hidupmu dan segala cita-citamu yang hingga kini hanya menjadi batu, tak bergerak. Diam. Kamu tak bisa menentukan jalan mana yang harus kamu tapaki sehingga kamu terus berjalan dan dalam siklus tertentu, jalanmu akhirnya juga sampai ke rumahku. Aku sedih sebenarnya, tetapi aku tak ingin terjadi apa-apa denganmu. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu bahwa aku benar-benar mencintaimu tanpa latar belakang apapun. Kamu sangat berbeda dengan laki-laki lain yang kukenal, dan aku ingin mengenangmu lebih dalam dari sekedar percintaan di malam-malam yang sering kita lalui.
“Maafkan aku. Aku tak bisa memberi ketenangan bagimu,” katamu suatu ketika.
“Kau bisa memberi ketenangan, asal kau bisa menetap di sebuah tempat di mana aku bisa menemukanmu ketika aku ingin bertemu denganmu. Aku bisa mencari dan menemukanmu, bukan hanya kamu yang datang padaku tanpa kabar sebelumnya...”
“Aku harus hidup berpindah-pindah, Flo...”
“Aku bisa paham...”
“Mereka masih mencariku dan aku belum siap masuk penjara.”
“Aku bisa mengerti...”
Di kesempatan lain, kau pernah bercerita tentang Wang Dan, lelaki kumal yang berada di belakang demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Tiananmen yang membuat ratusan mahasiswa terbunuh oleh tentara pemerintah, termasuk Wang sendiri yang akhirnya tertangkap di kemudian hari. “Orang seperti Wang tak pernah memikirkan dirinya sendiri. Yang dipikirkannya adalah pembebasan untuk semua...”
“Kau ingin pembebasan untuk siapa?”
“Orang-orang kampungku. Mereka telah berjuang bertahun-tahun untuk mempertahankan tanahnya, tetapi mereka tak mampu karena mereka tidak memiliki kekuatan...”
“Itu kasusnya berbeda. Wang didukung oleh ribuan mahasiswa dan pejuang pro demokrasi di seluruh dunia, sedang kamu hanya di sini, ribuan kilometer dari kampungmu dan kamu tak bisa berbuat apa-apa...”
“Ya. Aku tak bisa berbuat apa-apa di sini. Tetapi aku yakin suatu saat mereka akan berhasil mendapatkankan kembali tanah-tanah mereka yang kini dikuasai perusahaan perkebunan...”
Suaramu halus, sopan dan sangat santun. Tetapi aku menemukan sebuah cita-cita besar yang sebenarnya tak pernah kuyakini sebelumnya bahwa kamu merelakan dirimu seperti itu, menjadi pelarian, dikejar intel pemerintah dan hidup berpindah-pindah di kota besar seperti Jakarta ini. Aku tak tahu apakah kamu bisa makan setiap hari tiga kali dalam pelarian ketika kamu benar-benar dalam kesulitan dan terdesak.
“Aku akan datang ke kampungmu, aku akan membuat liputan tentang itu...” kataku suatu kali.
“Sangat jauh di Sumatera. Bahkan sangat jauh dari Pekanbaru. Tidak ada penginapan di sana.”
“Tidak apa, mungkin dengan ditulis di koran, pemerintah setempat sadar bahwa ada hak masyarakat yang selama ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak berhak.”
“Aku tak bisa mengantarmu ke sana...”
“Tidak apa-apa, aku bisa datang sendiri. Aku sudah terbiasa liputan di daerah pedalaman, meski itu hanya di sekitar Jawa.”
“Di Sumatera berbeda Flo. Di Jawa sudah tidak ada hutan, di Sumatera, dari satu kota kabupaten ke kota kabupaten lain, hampir sepanjang jalan harus melewati hutan lebat. Perumahan penduduk jarang di pinggir jalan besar.”
“Tidak apa-apa...”
Kamu kemudian memelukku, menciumku. Aku terpesona, aku benar-benar berharap suatu saat masalahmu selesai dan kita bisa merencanakan untuk sesuatu, untuk sebuah masa yang akan datang. Untuk kita berdua. Meski aku tidak meyakini itu. Meski aku benar-benar tidak meyakini itu. Meski yang ada dalam pikiranku hanyalah harapan-harapan yang mungkin akan tetap menjadi harapan hingga pada akhirnya nanti. Tetapi, tetaplah kau sebagai kekasihku. Tetaplah datang dalam setiap keinginanmu tanpa mempedulikan keinginanku apa. Aku bisa menerimanya, bisa menerima semua yang akan dan sudah terjadi di antara kita, di antara pilihan-pilihan yang kemudian muncul dan meskipun itu benar-benar membingungkanku. Kau pasti tak percaya, bahwa aku selama ini tidak memiliki pikiran seperti itu, pikiran yang bagiku sangat tidak rasional. Pikiran yang selama ini tak pernah terlintas dalam kehidupanku. Menunggu laki-laki yang tak pasti? Bahkan mengatakannya sebagai kekasih?
Tetapi salahkah? Salahkah jika kemudian pikiran itu ada dan meskipun bertolak belakang dengan segala kenyataan yang selama ini ada dalam pikiran dan kehidupanku sebelum kehadiranmu? Tak bisakah semua orang yang merasa peduli padaku memahami bahwa apa yang kulakukan –dengan mencintaimu—adalah sebuah kenyataan yang masuk akal? Apa salahnya mencintai lelaki seperti kamu?
“Yang salah mungkin takdir, Flo...” itu katamu dulu.
“Aku tak percaya takdir. Manusia harus bekerja dan berusaha terlebih dahulu, baru setelah itu bicara tentang takdir.”
“Itulah yang kumaksud...”
“Takdir baru kita simpulkan setelah kita melaluinya...”
“Misalnya?”
“Misalnya? Misalnya, mengapa aku memilih mencintai laki-laki seperti kamu. Hahaha...”
Kita tertawa setelah itu dan kau mengatakan bahwa cinta yang muncul dalam hatiku bukan takdir. “Jika itu sebuah takdir, apakah selama ini semua laki-laki yang pernah singgah dalam kehidupanmu juga sebuah takdir? Begitu banyak takdir kalau begitu...”
“Juga beberapa perempuan yang ada dalam kehidupanmu sebelum aku datang?” Kali ini aku bicara serius.
Kau kemudian berjalan ke arah jendela. Di luar basah. Hujan. Tempiasnya membuat kaca jendela berkabut. “Aku tak tahu, apakah ada wanita yang benar-benar mencintaiku selain ibuku. Tetapi, ibuku pun tidak mampu berbuat apa-apa ketika itu...”
“Ketika itu?”
“Ya. Ketika itu. Ketika hujan deras dan badai, dan aku harus tetap berada di bawahnya, dalam gelap, dalam kilatan petir. Ibuku tak bisa melakukan apa-apa selain menangis bersama kedua adikku. Dan aku sendiri, bahkan tidak berani menawar...”
Aku mendekatinya, memeluknya dari belakang. Melingkarkan tanganku pada perutnya yang keras. Dia tidak kelihatan berdaging, tetapi seluruh otot di tubuhnya mengeras. Aku suka itu. Otot yang mengeras... “Kau tak pernah mau bercerita tentang itu kepadaku...”
“Suatu saat aku akan bercerita. Tetapi tidak saat ini. Aku ingin bercinta denganmu...”
Kemudian kami benar-benar bercinta sepanjang malam...
KAU memang selalu pergi tanpa harus permisi padaku. Ini yang sering kukatakan bahwa apapun tak akan bisa mengikatmu, termasuk cinta. Cinta. Cinta? Apakah aku memang benar-benar jatuh cinta? Jatuh cinta kepada laki-laki seperti kamu? Laki-laki dengan masa lalu suram dan mungkin tanpa masa depan? Tanpa masa depan? Siapa yang tahu dengan masa depan seseorang? Siapa yang bisa menentukan nasib? Takdir? Lagi-lagi takdir. Mengapa setiap bercerita tentang kamu, dengan segala apa yang kamu miliki, aku selalu menghubungkannya dengan takdir? Fullfil your destiny, is there within the child...[1]
Memenuhi takdir?
“Apakah seorang laki-laki harus memiliki masa depan, Flo?”
Suatu saat kau bertanya.
“Ya.”
“Masa depan yang seperti apa?”
“Kau tak tahu arti masa depan? Tentu bukan masa depan yang buruk. Cita-cita maksudku, karena dengan cita-cita itulah manusia akan bekerja keras untuk mendapatkannya.”
“Untuk apa?”
“Mungkin untuk dirinya sendiri. Mungkin untuk kekasihnya. Mungkin untuk anak atau istrinya...”
“Untuk anak, istri dan kekasih? Hahaha...”
“Untuk anak dan istri, jika ia sudah berkeluarga. Untuk kekasihnya, jika dia memang ingin memiliki kekasih.”
Tetapi kau memang membuatku bingung. Pada suatu malam yang hujan, kau tiba-tiba sudah berdiri di pintu setelah sekian lama tak pernah berkabar. Rambutmu basah, meneteskan air. Jaket lusuhmu juga basah, meneteskan air. Celanamu yang kumal, basah dan air mengalir. “Aku akan mengambilkan handuk,” kataku cepat-cepat masuk kamar dan sudah keluar dengan handuk putih, handuk yang memang sering kau pakai ketika berada di rumahku.
Kau tak mau menerima handuk itu. “Aku tidak memerlukan handuk ini. Aku memerlukan tubuhmu...” Kau kemudian memelukku dalam segala basah seperti itu. Gaun tidur yang kupakai akhirnya juga ikut basah. Agak lama kau memelukku dan aku terlena. Tetapi ketika kusadari tak ada gerakan apa-apa, aku mulai mengurai pelukan. Kau diam, tanpa gigil. Tuhanku, kau pingsan. Kau pingsan saat memelukku. Aku panik, tetapi cepat kuangkat tubuhmu dengan segala kekuatanku. Kubawa ke kamar, kubuka seluruh kain yang melekat di tubuhmu. Aku juga membuka seluruh kain yang ada di tubuhku. Aku memelukmu dalam selimut tebal setelah kumatikan AC. Lama aku memelukmu, tetapi kau tak siuman juga. Aku menunggu, tetap memelukkmu dengan menempelkan tubuh telanjangku pada tubuh telanjangmu, tetapi kau juga tak siuman. Aku tetap memelukmu dalam selimut tebal. Aku mulai berkeringat dan membasahi seluruh tubuhku, tetapi kau tetap beku. Lama-lama aku menyadari, bukan hanya keringat yang membasahi tubuhku –juga tubuhmu— tetapi juga air mataku sudah membuat aliran kecil di pipiku. Aku menangis. Aku benar-benar menangis. Tak maukah kau mencair? Kenapa seluruh hawa panas yang keluar dari tubuhku juga tak bisa menghangatkanmu? Tetap membuatmu beku?
Aku kemudian keluar dari selimut, memakai baju tidur lagi dan mengambil air hangat dari dispenser dan kain kompres. Aku mulai mengompres. Beberapa saat, tetapi kau tetap beku. Hingga akhirnya aku tak tahu apa lagi yang harus kulakukan untuk membuatmu siuman. Aku menangis di atas selimut yang menutup tubuhmu, sampai akhirnya aku tak sadar beberapa waktu, mungkin aku tertidur, sebelum tiba-tiba aku merasakan jemarimu mengelus rambutku. Ketika aku terbangun, kulihat kau tersenyum meski bibirmu masih kelihatan pucat dan matamu sayu. “Sudah lama aku pingsan?” tanyamu lirih.
“Lama sekali, hingga aku menunggu seperti seratus tahun...” Aku memelukmu erat, tanpa bisa menghentikan air mataku yang terus mengalir.
“Aku sering seperti ini?”
“Tidak, baru sekali ini.”
“Aku merasakan sering, tetapi mungkin baru sekali ini ketika bersamamu.”
“Benarkah?”
“Aku suka hujan, suka berhujan-hujan, apa lagi kalau malam hari. Malam dan hujan...” Kau seperti bergumam.
“Tak ada rama-rama kalau hujan...” Aku menimpali sambil meraba pipimu.
“Tak ada rama-rama. Di kota besar tak ada rama-rama.”
“Apakah di kampungmu yang katamu jauh sekali itu, setiap malam masih banyak rama-rama?”
“Banyak sekali, apalagi kalau musim gelap. Maksudku, ketika tak ada rembulan. Tetapi rama-rama tetap tak ada bila hujan. Aku suka malam dan hujan, aku juga suka rama-rama...”
“Aku ingin ke kampungmu yang katamu jauh itu...”
“Suatu saat aku akan mengajakmu ke sana.”
“Kapankah suatu saat itu?”
“Kapan-kapan...”
Di lain waktu, kau mengatakan tentang kerinduan-kerinduanmu pada tanah kelahiranmu. Katamu, kau rindu bau getah karet. Kukatakan, bukankah itu bau bacin seperti air got yang menghitam atau kotoran binatang? Ya. Tetapi kau tetap merindukannya. Kau merindukan saat remaja di sebuah kebun karet di pedalaman. “Aku melarikan diri dari sana, dari masa laluku, dari duniaku yang sesungguhnya. Aku merindukannya...”
Kau memang lelaki yang lahir dan kemudian lari dari masa lalu. Tetapi kemudian aku mengatakan bahwa semua manusia lahir dari masa lalu, sebab tidak ada masa kini dan masa depan kalau tidak ada masa lalu. Itu hukum waktu. “Tetapi aku benar-benar merindukan pohon-pohon karet yang terjajar rapi, bau bacin getahnya yang sudah berhari-hari, saat hujan yang mengerikan...”
“Hujan yang mengerikan?” sergahku.
“Hujan yang mengerikan...”
“Ceritakanlah padaku tentang hujanmu yang mengerikan itu...”
Tiba-tiba, seperti sebelum-sebelumnya, kau kedinginan dan dalam waktu yang sangat cepat berubah menjadi gigil yang membuat seluruh tubuhmu memucat: bibirmu, pipimu, dan seluruh tubuhmu dan tiba-tiba aku menangis. Bibirmu berkali-kali ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak terucap apa-apa dan aku kemudian memelukmu, mendekapmu dengan sangat erat. “Aku membutuhkan jiwamu, cintamu...” dan untuk kesekiankalinya, kau pingsan di hadapanku. Kau pingsan dan aku panik. Kuambil minyak angin, kompres dan kulakukan segala apa yang bisa kulakukan. Hingga menjelang Subuh, kau terbangun setelah tubuhmu berkeringat. Malam itu, aku menjagamu dalam diam, dan menangis juga dalam diam. Aku merasa tak mengerti apa-apa tentang dirimu.
KEMUDIAN aku memanggilmu lelaki hujan. Aku tak memaknai apa-apa dengan nama panggilan itu sebelum aku akhirnya memahami semuanya tentang satu cerita yang ingin engkau ceritakan tentang hujan yang mengerikan bagimu itu. Hujan yang mengerikan, katamu, tetapi kemudian membuatmu tumbuh menjadi pengembara yang belajar kuat meneruskan semua mimpi-mimpimu.
“Bau bacin getah itu lama-lama menjadi seharum mawar seperti yang sering kuberikan padamu,” katamu suatu kali.
“Mawar yang kau berikan padaku sering sudah layu meskipun sudah basah oleh hujan.”
“Maafkan, aku harus naik-turun kereta api untuk sampai rumahmu. Dan mawar itu kubeli dari penjual bunga di dekat stasiun, ketika kubeli, dia masih segar...”
“Tidak apa-apa. Aku suka apapun pemberianmu...”
Lalu kau cerita tentang bau bacin getah karet yang sudah direndam di dalam air berhari-hari itu. Bau bacin yang katamu berubah menjadi seharum mawar dan membuatmu selalu terkenang pada masa lalumu, pada tanah kelahiranmu, pada masa kanak-kanak dan remaja yang kemudian engkau tinggalkan.
Aku masih ingat persis ceritamu: “Senja itu hujan lebat Flo. Tetapi aku harus keluar rumah tanpa payung atau mantel hujan...” Bapakmu menginginkan kau jadi laki-laki kuat dan harus tahan segala cuaca. Kau pergi ke hutan karet saat hujan lebat dan petir menyambar-nyambar untuk mengangkut getah yang beku, bau dan masih basah itu. Malam nanti toke getah akan menimbangnya dan getah itu sudah harus ada di rumah sebelum malam.
“Tapi hujan deras sekali, Bapak...” katamu mencoba menawar kepada bapakmu.
“Kau tak akan mati oleh hujan.”
Dan kau kemudian berlari ke belakang rumah, mengikuti jalan setapak yang masuk ke belukar di hutan karet yang sudah tua dan tidak terawat itu. Tapi itulah sumber kehidupan keluargamu. Kau memang masih sangat remaja ketika itu, dan harus menapak pada jalan licin menurun dan mendaki untuk sampai ke rawa di mana getah bacin itu berada. Getah itu sudah dicetak menjadi bantalan dan ditenggelamkan di lumpur yang berair untuk menjaga kadar airnya yang akan mempengaruhi timbangan, dan kau harus mengangkatnya satu persatu sejauh hampir 400 meter dengan pundak atau punggungmu sampai di belakang rumah. Ibumu menangis menyaksikan itu dan dua adikmu hanya memandang sedih dari dapur rumah kayu itu ketika dalam hujan yang lebat kau bekerja keras.
“Biar dia belajar bertanggung jawab sebagai lelaki,” kata bapakmu kepada ibumu, sempat terdengar di telingamu.
Kau mengaku tidak dendam dengan semua itu. Sebab bapakmu sudah ringkih, terlihat tua sebelum waktunya karena beban hidup dan tembakau yang membuatnya selalu terbatuk. Kau tetap mengaku tidak dendam, karena laki-laki memang harus bertanggung jawab di kondisi apapun.
Hujan benar-benar semakin deras dan senja sudah hampir penghujung, dan bantalan getah bacin itu masih beberapa yang belum kau angkat. “Aku sudah menggigil ketika itu Flo dan tenagaku sudah semakin lemah...”
Hingga kemudian ketika bantalan bacin basah itu tinggal satu, kau benar-benar tidak memiliki tenaga dan hari sudah benar-benar gelap. Kau tetap mengangkatnya dan harus berjalan di pendakian yang licin, sementara kakimu tanpa sepatu, hanya telanjang dan menggigil. Dan tiba-tiba, ketika tenagamu benar-benar habis, kau terpeleset, bantalan bacin itu menimpa tubuhmu yang telanjang tanpa baju dan kau bergulingan hingga sebatang pohon karet menahan tubuhmu. Kau kesakitan, tetapi tidak ada yang menolong. Kau ingin berteriak tetapi suaramu tak keluar. Kau akhirnya benar-benar kedinginan, juga kesakitan, dan menggigil seperti berada di dalam bongkahan es, sebelum bapakmu menemukanmu dalam keadaan pingsan di bawah pohon karet, saat hujan mulai reda dan malam sudah benar-benar menggelapkan kampung.
Kau tetap mengaku tidak dendam dengan masa lalu itu. Hingga kemudian kau memilih pamit pada bapak, ibu dan dua adikmu untuk pergi jauh mengembara. Kau merasa dunia di luar kebun karet itu memberikan harapan-harapan dan pengalaman hidup yang lebih baik. “Biarlah dia pergi, laki-laki harus punya pengalaman hidup untuk menguatkannya,” kata bapakmu kepada ibumu yang sempat terdengar ke telingamu ketika langkahmu menyeberang pintu. Kau kemudian pergi saat hujan dan malam gelap. Meninggalkan kampungmu, rumah kayu, hutan karet, bau bacin dan segala kenangan tentang masa kecil dan remajamu.
Kau pernah kembali ke kampungmu itu beberapa tahun kemudian setelah kau merasa berhasil setelah menamatkan kuliahmu dalam pelarianmu di Pekanbaru. Kau sudah merasa menjadi kuat, tetapi kau mendapati bapakmu sangat ringkih, terbatuk-batuk dan sudah sangat susah untuk berjalan. Sudah terlihat sangat tua, sangat sepuh, jauh lebih tua dari umur sebenarnya. Bapakmu mengatakan kepadamu, bahwa sejak kau pergi ladang karet itu tak terawat, meskipun tetap diambil getahnya oleh ibumu dan dua adikmu yang sudah mulai masuk SMP. Kau merasa hatimu perih. Kau membayangkan bagaimana perjuangan ibumu dan dua adikmu untuk bisa mendapatkan uang dengan menakik getah. Kau menangis dan memeluk bapakmu. Kau tetap mengatakan bahwa kau tak dendam dengan masa lalu, terhadap kekerasan hidup yang harus kau alami, juga saat malam dan hujan itu. Kau hanya membayangkan bagaimana pedihnya ibumu dan dua adikmu sepeninggalanmu, ketika tidak ada lagi laki-laki dewasa –kau selalu mengatakan bahwa di kampung, laki-laki yang sudah masuk SMA bersikap sangat dewasa karena sering menjadi penopang hidup keluarganya ketika orang tuanya sudah mulai tua-- yang bisa membantu pekerjaan itu. Di kota-kota besar, remaja-remaja seusia itu masih kebut-kebutan di jalanan, ngobrol dengan teman-temannya di kafe, bisa les ini itu, masih merengek minta uang belanja dan sebagainya.
Kau kemudian mencari ibumu. Wajahnya memancarkan senyum meski raut mukanya sangat keletihan. “Seorang ibu hanya bisa mendoakan anaknya ketika dia merantau. Ibu takut kau tersesat dan lupa jalan pulang...” Ibumu kemudian merangkulmu dengan sangat erat. Dia sudah menunggumu lebih dari lima tahun untuk sebuah pertemuan seperti ini, karena selama kurun waktu tersebut, kau tak pernah mengirim kabar apapun.
Ketika pulang itulah, katamu ketika itu, bahwa penduduk di kampungmu kini sudah semakin terjepit. Sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk ke kampungmu, juga kampung-kampung lainnya, dengan membawa secarik kertas yang katanya sebagai izin kepemilikan atas lahan. Beberapa kampung, juga kampungmu, masuk dalam areal perkebunan. Sebab, kata mereka, dalam peta hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di areal itu tidak ada perkampungan, yang ada adalah hutan. Kampungmu tak masuk dalam peta rupanya...
Selama beberapa tahun, masyarakat melakukan perlawanan atas penguasaan lahan itu, namun mereka tetap saja terjepit. Tak ada yang bisa menolong mereka untuk bisa mempertahankan tanah yang telah mereka tempati. Mereka kalah oleh secarik kertas, yang terjadi kemudian mereka juga kalah oleh bouldozer dan puluhan aparat yang didatangkan oleh perusahaan perkebunan tersebut untuk menakut-nakuti warga.
Sekali lagi, kau mengatakan tidak dendam kepada ayahmu, karena kamu merasa hal itulah yang telah menjadikanmu laki-laki kuat, bisa survive di kota, bisa kuliah meski sambil bekerja serabutan. Kau bahkan mengatakan berterima kasih kepada bapakmu, meski kau mengucapkannya dengan perih. Karena keanehan-keanehan dalam tubuhmu mungkin ada hubungannya dengan peristiwa malam itu, ketika kau pingsan di bawah pohon karet dengan bantalan getah bacin yang menimpa tubuhmu. Juga kejadian-kejadian lainnya yang merupakan rentetan waktu. Keanehan-keanehan, termasuk gigil yang selalu datang, juga kecintaanmu pada malam dan hujan.
Kau berjanji akan tetap berada di kampungmu untuk membantu melawan perusahaan perkebunan itu, meski akhirnya kau harus lari, dan kita bertemu di stasiun kereta api menjelang Subuh, sangat jauh dari kampungmu di Sumatera... Dan inilah cerita-cerita tentang kehidupanmu itu, yang bagiku amat penting. Amat penting sehingga aku tak ingin melupakannya barang sedikitpun. Kau, laki-laki dengan masa lalu aneh, yang juga aneh bagi sekian orang di sekitarku, tetapi membuatku memiliki kekuatan untuk meyakinkan diriku bahwa hidup memang harus diperjuangkan, bukan ditangisi...
Bagian II
DINI hari, menjelang Subuh. Stasiun Solo-Balapan. Sosok itu kulihat tengah duduk di kafetaria ketika aku baru saja turun dari kereta. Aku baru sampai dari Jakarta dan aku memang memilih naik kereta malam, seperti perjalanan-perjalanan sebelumnya. Entah mengapa, aku lebih suka memilih kereta api, meski harus menghabiskan waktu semalam atau sehari untuk sampai ke Solo atau Yogyakarta, dua kota di Jawa, yang memang memiliki sejarah bagi hidupku. Solo telah melahirkanku, sedang Yogyakarta adalah tempat di mana aku harus menyelesaikan pendidikan di jurusan fotografi. Aku mencintai keduanya, Solo yang lambat, lembut dan sepi. Yogya yang mulai beriak dan sudah sering macet, tapi mengasyikkan dan menenangkan.
Aku tak tahu alasan lain yang masuk akal mengapa aku lebih memilih kereta dalam kepergianku di kota-kota di Jawa. Kereta memberikan suasana roman, artistik dan penuh historis bagiku. Barangkali begitu kalau boleh aku menyimpulkannya. Rangkaian gerbong yang ditarik lokomotif; suara yang agak bising tapi konstan dan menimbulkan irama tesendiri; orang-orang yang bergegas bahkan sering berebutan di kelas ekonomi; pohon-pohon, gedung-gedung dan rumah-rumah yang berlari di luar kaca jendela; stasiun yang lengang di malam hari...
Aku masuk ke kafe di mana lelaki itu duduk di sudut. Pagi masih kira-kira dua jam lagi, dan aku tak mau langsung ke hotel. Lebih baik menunggu pagi dan kemudian ke hotel untuk mempersiapkan segala apa yang harus kulakukan. Jika aku langsung ke hotel, pasti akan tertidur dan bagunnya akan kesiangan. Aku memesan teh hangat. Dingin di dalam gerbong tadi membuatku menggigil, padahal aku sudah memakai jaket tebal yang memang sudah kupersiapkan sebelumnya.
Entah mengapa, keinginanku untuk menoleh ke arah kanan, di sebuah sudut di mana sosok itu duduk, tak bisa kulawan. Seorang laki-laki dengan jaket agak besar, sedang menikmati kopi dan rokoknya. Rambutnya gondrong agak bergelombang, wajahnya tak terlihat. Mungkin dari tadi dia berada di sini menunggu seseorang. Tetapi ketika keretaku sampai dan orang-orang turun –termasuk aku— dia tidak bergerak. Ketika kemudian ada kereta berhenti dan menurunkan penumpang lagi, dia juga tidak beranjak dari tempat duduknya. Mungkin dia tidak menunggu seseorang, atau dia tahu kereta orang yang ditunggunya itu akan sampai setelah matahari terbit. Tapi, jika itu benar, untuk apa jam segini dia sudah berada di stasiun? Aku berandai-andai, dan jadi malu sendiri mengingat aku tak memiliki urusan dengannya.
Kunaikkan resluting jaketku, dingin terasa menusuk, meski tidak sedingin seperti di dalam gerbong kereta tadi. Aku mengambil meja yang menghadap rel kereta, sejajar dengan laki-laki di sudut itu. Aku benar-benar penasaran ingin melihat wajahnya, dan sering dengan mencuri-curi, aku melirik ke samping. Tetapi, dia nampaknya benar-benar tidak mempedulikan kehadiran seseorang di dekatnya. Aku memesan teh hangat, dan beberapa saat kemudian pelayan datang dan membawa pesanan itu. Sengaja aku mengaduk teh dengan gula itu dengan suara keras, tetapi dia juga tak menoleh barang sedikitpun. Aku hanya ingin memiliki teman bicara, barangkali, di sebuah stasiun tua yang sunyi seperti ini. Tetapi, kalau dia seorang perampok atau pembunuh, bagaimana?
Hingga terdengar suara azan dari masjid terdekat, kami tetap tak ada komunikasi apapun. Bahkan ketika kemudian hari sudah terlihat mulai terang dan matahari muncul dari timur, kami tetap dengan pikiran masing-masing. Tetapi, aku semakin jelas bisa melihat sosoknya, meski aku tetap belum bisa melihat wajahnya. Hingga kemudian, ketika hari benar-benar terang, aku bangkit dari duduk dan berjalan menuju kasir. Aku benar-benar tak ingin penasaran dan ingin melihat wajahnya sambil berjalan keluar. Tetapi, tiba-tiba, lelaki itu menoleh kepadaku.
“Nona Floren?”
Aku nyaris tergagap. “Ya?”
“Saya menjemput Anda.” Suaranya dingin, seperti dinginnya pagi yang masih berembun.
Menjemput? Beginikah cara orang menjemput? “Maksudnya...?”
“Saya menjemput Anda...”
“Saya tidak diberi tahu sebelumnya, dan selama ini tidak ada orang yang menjemput saya ketika saya ke sini...” Hatiku berdebar. Jangan-jangan...
“Saya dari hotel tempat Anda akan menginap. Saya menjemput Anda...”
“Maaf, saya tidak memesan reservasi hotel. Anda salah orang...” aku berusaha mencari selah.
“Kantor Anda telah memesankan kamar atas nama Anda, dan saya menunggu Anda...”
“Begini cara Anda menunggu seorang tamu? Membiarkan sang tamu berjam-jam seperti ini?”
“Saya hanya memastikan...”
Benar-benar aneh.
Dia kemudian bangkit. Posturnya tinggi, rambutnya gondrong, sedikit agak kumal memang –mungkin karena sejak dinihari tadi dia berada di sini dan tidak tidur. Tetapi, beginikah pelayanan sebuah hotel? Mengirimkan seseorang untuk menjemput dan membiarkannya termenung dalam malam yang dingin? Sudut mataku menangkap wajahnya: lumayan tampan, ada bekas cukur yang kebiru-biruan di atas bibir, jenggot dan cambangnya. Cukup menarik, tetapi, dia orang asing dan aku terbiasa tidak boleh cepat percaya dengan orang asing, orang yang belum kukenal, meski sejak dinihari tadi sejak aku berada di kafe, aku cukup penasaran dibuatnya. Tapi, apakah itu kemudian mengharuskan aku mempercayai apa yang dia katakan? Bagaimana kalau dia seorang penculik yang memang ditugaskan untuk menculikku? Atau, katakanlah dia menculik untuk dirinya sendiri, misalnya dia seorang penjahat kelamin yang suka memperkosa perempuan muda, dan kemudian membunuhnya? Atau, dia menculik dan kemudian menjual wanita yang diculiknya itu untuk bekerja menjadi pekerja seks komersial --pelacurlah istilah kasarnya— yang dikirim ke negara-negara asing seperti Hongkong atau Thailand?
Aku bergidik. Semua yang mengerikan itu tiba-tiba berputar-putar di kepalaku dan membuatku benar-benar bingung. Haruskah aku mengikuti keinginannya: pergi ke hotel bersamanya seperti yang dia katakan, dan membiarkan diriku berada dalam kekuasannya selama di perjalanan dan setelah itu aku tak tahu dia akan melakukan apa pada diriku... Pokoknya aku tak mengenalnya, dan itu menjadi sebuah alasan yang kuat untuk tidak percaya kepadanya terlalu cepat. Aku harus mendapatkan sebuah bukti bahwa aku benar-benar mempercayainya, kalau apa yang dia katakan itu benar: bahwa dia memang petugas hotel yang harus menjemputku. Tetapi, benarkah?
“Hubungi kantormu kalau tidak percaya...”
“Pagi-pagi seperti ini kantorku belum buka...”
“Hubungi Ibu Martini di handphone-nya. Dia yang memesankan hotel untukmu...”
Aku berpikir sejenak, menimbang-nimbang. Apa yang dia katakan benar, Martini, orang finance di kantor memang telah memesankan hotel untukku, dan sesampai di Solo sebenarnya aku bisa saja langsung masuk dengan naik taksi dari stasiun. Tetapi keputusanku untuk menunda ini, ternyata telah mempertemukanku dengan lelaki aneh yang mengaku sebagai penjemput ini. Aku menguatkan hatiku dan memutuskan apa yang terjadi terjadilah.
“Oke. Saya percaya Anda...”
“Jangan cepat percaya dengan orang yang baru Anda kenal...” jawabnya.
Apa? Justru ketika aku sudah percaya padanya, dia ngomong begitu? Tetapi kemudian dia berjalan keluar ke areal parkir, dan aku menunggu di depan pintu. Beberapa saat kemudian dia datang dengan mobil berwarna hitam, tidak ada tanda-tanda sedikitpun kalau itu mobil hotel di mana aku akan menginap. Keraguan kembali berada di otakku. Dia turun membukakan pintu --terus terang aku risih diperlakukan seperti ini: dibukakan pintu...— dan kemudian mempesilahkanku untuk masuk. Setelah aku sampai di dalam, dia menutup pintu dengan pelan dan seolah gerakannya teratur dan berirama ketika kemudian membuka pintu untuknya sendiri dan masuk ke belakang stir, menutup kembali, dan kemudian menjalankan mobil. Aku melihatnya dari belakang, dan aku masih membayangkan seandainya dia benar-benar seperti yang ada dalam bayanganku tadi: penculik, pemerkosa, pembunuh...
Jarak antara stasiun dan hotel tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu 10 menit. Dan dalam rentang waktu itu kami tidak saling bicara. Dia seperti asyik menatap jalanan yang masih lengang, menyaksikan mbok-mbok dengan sepedanya sedang menuju pasar, beberapa anak sekolah yang pagi-pagi sekali telah berada di jalan untuk pergi ke sekolahnya –bukankah dengan seperti ini sekolah telah membuat para murid menjadi mesin waktu yang harus melakukan semuanya dengan batasan waktu?-- maupun beberapa pengemudi sepeda motor yang tetap dengan tenang berada di atas motornya dengan jaket tebal dan helm besar sedang menuju sebuah arah yang aku tak perlu tahu keperluannya apa.
Tetapi laki-laki itu memang benar-benar diam. Hingga kemudian aku sampai di hotel dan diturunkan di depan lobbi, dia tetap diam: menghentikan mobil, membukakan pintu, menurunkan tasku dan memberikannya kepada seorang pelayan yang sudah siap di depan lobbi. Kemudian dia naik ke mobil lagi dan pergi seperti angin. Tak bicara apa-apa kepadaku, dan herannya aku merasa berdosa dengan segala tuduhan dalam hati tadi tentang segala kemungkinan terburuk tentangnya.
Seperti tahu apa yang ada dalam hatiku, pelayan hotel itu mengatakan bahwa dia memang seperti itu. “Maksudmu siapa?” tanyaku heran.
“Namanya Iman Jaidi, Bu. Dia pendiam dan tak banyak bicara. Pasti sepanjang jalan tadi Ibu didiami sama dia...”
“Ya. Bahkan dia membiarkan saya kedinginan di stasiun selama hampir tiga jam, padahal dia tahu saya orang yang akan dijemputnya...”
“Dia memang aneh, Bu. Maafkan atas buruknya pelayanan kami ini...”
“Oh... tidak. Tidak. Tidak ada masalah. Lupakanlah...”
Aku malah menjadi tidak enak dengan pelayan hotel itu. Dia mengantarkanku sampai resepsionis dan kemudian meninggalkanku dengan senyum manis. Aku membalasnya, dan aku yakin senyumku masam dan asam karena wajahku letih dan ngantuk.
BEBERAPA bulan kemudian aku melihat sosoknya di Jakarta. Aku sedang memotret pameran lukisan di Hotel Borobudur ketika itu saat wajahnya tertangkap kameraku sedang termangu di depan sebuah lukisan. Aku terkejut, sebelum menyadari semuanya, jariku sudah menekan tombol dan wajahnya terekam dalam beberapa petik. Mungkin merasa ada yang memperhatikannya, dia kemudian menoleh dan terkejut. Tiba-tiba dia sudah berada di dekatku ketika aku melepaskan mata dari kamera.
“Saya tidak suka dipotret.” Suaranya terdengar dingin dan berat.
“Maafkan, saya tidak sengaja. Saya hanya berusaha memotret pengunjung pameran ini dan kebetulan saja Anda menjadi salah satu obyek kamera saya...”
“Saya ingin foto saya dihapus.”
Aku terdiam. Dihapus? Ini sudah keterlaluan. “Saya tidak mungkin menghapuskan seluruh gambar di kamera saya. Tetapi saya tidak akan mencetak foto Anda.”
“Saya harus memastikan janji Anda itu.”
“Ya. Selama ini saya memposisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya.”
“Saya harus tahu alamat rumah dan kantor Anda. Saya benar-benar tidak ingin foto itu dicetak, apalagi jadi konsumsi publik.”
Aku semakin heran dengan penekanan pada kata-katanya yang dikatakan berulang. Aku jadi penasaran. Mengapa dia tidak mau fotonya dicetak? Bukankah biasanya banyak orang yang suka wajahnya nongol di media, bahkan koran atau majalah itu kemudian dibeli dan diperlihatkan kepada keluarga, sanak famili atau tetangganya. Mengapa orang ini tidak mau?
“Saya berjanji...” kataku menggantung. Aku ingin dia sadar bahwa kami pernah bertemu sebelumnya di Stasiun Solo-Balapan, saat dia menjemputku. Tetapi, ternyata kemudian dia hanya mencatat alamat rumah dan kantorku, dan setelah itu pergi.
Aku terkejut, dan kemudian dengan reflek mengejarnya. Hampir sampai di pintu keluar, aku mendahului langkahnya. “Hai, tunggu. Bukankah kita pernah bertemu sebelum ini?”
Dia menghentikan langkahnya, diam sejenak sambil memandangku, dan kemudian berjalan keluar pintu. Dia tak peduli hujan deras di luar. Diterobosnya dengan berjalan santai, dan aku dibuat bingung olehnya. Dia tidak ingat kalau kami pernah bertemu? Apakah dia memang sengaja melupakan atau memang dia tak ingat karena pekerjaannya sebagai penjemput tamu hotel membuat dia bertemu dengan banyak orang dan tak semuanya bisa diingatnya? Aku jadi heran, seorang pegawai sebuah hotel dan tugasnya adalah penjemput tamu di bandara atau stasiun, menyukai lukisan dan datang jauh-jauh dari Solo hanya untuk menyaksikan pameran ini? Atau, dia hanya kebetulan berada di Jakarta dan kemudian tahu ada pameran ini dan datang? Atau, dia memang sudah tinggal di Jakarta?
Diserang rasa penasaran, aku kemudian berlari ke tempat parkir dan langsung masuk mobil. Kuhempaskan peralatan fotoku ke jok belakang dan kemudian langsung menginjak pedal gas. Sesampai di jalan, aku tak menemukan dia. Hujan deras, banyak kendaraan di jalan dan orang-orang berjalan kaki memakai payung. Banyak juga anak-anak yang menyewakan payung berjalan di belakang orang yang menyewa payungnya. Anak-anak malang, yang harus mencari kehidupan sendiri di tengah kerasnya Jakarta. Aku bersyukur sejak kecil diberi kehidupan yang cukup oleh orang tuaku, sehingga aku tidak harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Tetapi di mana sosok itu? Siapa namanya? Aku bahkan tak pernah menanyakannya ketika kami bertemu di Solo. Iman Jaidi. Ya. Temannya yang membawakan tasku sampai ke resepsionis itu mengatakan kalau namanya itu. Tetapi, apakah benar kami pernah ketemu? Apakah tidak hanya kesamaan wajah dan tongkrongan saja? Tetapi, suaranya tadi menjelaskan bahwa aku benar-benar pernah bertemu dengannya. Mengapa aku menjadi penasaran seperti orang gila begini?
Aku membawa mobil pelan ke arah Sudirman dan berharap dia adalah satu dari banyak orang yang berjalan di trotoar dalam hujan seperti ini. Namun, di sepanjang jalan, meski mataku bergerak ke kanan dan kiri, tak kutemukan sosok itu. Jakarta telah menelannya. Jakarta yang ramai, bising dan padat ini, ke mana aku harus mencarinya? Aku terus ke kantor di Kebayoran Baru. Namun, aku dibuat tercengang ketika aku baru masuk dan kudapati dia sedang duduk di ruang tunggu. Dia kemudian berdiri ketika aku masuk dan mengatakan bahwa dia sangat serius dengan apa yang dikatakannya tentang foto tadi.
“Saya benar-benar serius dengan apa yang saya katakan tadi. Saya tak ingin foto itu dicetak, apalagi dimuat di koran Anda...”
Kupersilahkan dia duduk lagi. Aku mengamati bajunya yang basah, juga sedikit celananya. “Anda kedinginan...” entah mengapa, kata-kata itu yang keluar dari mulutku. Aku terkejut sendiri.
“Saya biasa kehujanan dan basah seperti ini. Saya benar-benar meminta Anda untuk menghapus gambar saya. Saya mohon...”
“Saya bukan orang jahat. Tetapi saya ingin tahu mengapa Anda sangat serius dengan masalah ini? Bukankah hal yang biasa wajah seseorang dimuat di koran?”
“Saya tidak mau. Ini menyangkut kehidupan saya...”
“Kehidupan?”
Dia diam. Kemudian, “Selama ini, saya tidak pernah percaya dengan siapapun. Saya hanya percaya dengan diri saya sendiri. Saya ingin hari ini mempercayai Anda, dan jika Anda benar-benar memenuhi keinginan saya, saya akan sangat berterima kasih. Anda akan menyelamatkan hidup saya...”
Aku tidak tahu arah bicaranya ke mana. Tetapi kemudian aku berjanji kepadanya bahwa aku tidak akan mencetak ataupun malah memuat fotonya (meskipun pada kenyataannya aku mencetak foto itu dan dua fremnya kusimpan di laci meja kerjaku di rumah). Dia kemudian mengatakan terima kasih dan akan pergi, namun cepat-cepat aku mengatakan bahwa aku bisa mengantarkan ke mana dia tinggal. Kembali, aku menjadi terkejut dengan apa yang kukatakan itu. Aku akan mengantarkannya? Namun kemudian aku mencoba mencairkan suasana dengan mengingatkan bahwa kami pernah bertemu. “Apakah Anda benar-benar tidak ingat kalau kita pernah bertemu di Stasiun Balapan, Solo?”
Dia tersenyum (harus kuakui, senyumnya sangat manis dan menarik) dan kemudian mengatakan bahwa dia mengingat itu. Aku merasa dunia telah mencair, maksudku, gunung es itu telah mencair. “Tetapi terima kasih dengan tawaran Anda. Saya bisa pulang sendiri dan tak perlu harus merepotkan...”
Ketika aku bertanya apakah dia sekarang sudah menetap di Jakarta, dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tinggal di Jakarta. Dia berada di Solo hanya dua bulan dan bekerja di hotel itu. Namun dia merasa Solo bukan rumahnya, bukan tempatnya. Dia kemudian ke Jakarta lagi, bekerja di sebuah LSM di Pejompongan. Aku tak peduli dengan nama LSM tempat dia bekerja, sebab aku menjadi semakin bergairah untuk berbicara dengannya hingga lupa kalau baju dan celananya basah dan aku tadi sudah menawarkan untuk mengantarkannya ke rumah di mana dia tinggal. Aku hanya ingin banyak bicara dengannya, sebuah keinginan yang ketika kusadari, membuat aku heran sendiri. Mengapa aku begini agresif terhadap seorang laki-laki? Padahal selama ini teman-teman di kantor banyak yang mengatakan bahwa aku termasuk gerombolan patah hati yang tak mau dekat dengan laki-laki lagi. Mereka tahu aku baru saja putus dengan kekasihku, dua bulan lalu, tetapi aku merasa biasa saja, tidak ada yang aneh seperti yang terlihat di mata mereka.
KAMI kemudian memang sering bertemu, dan seringnya malam hari ketika kami sama-sama sudah keluar dari kantor. Kami sudah lumayan akrab dan tak pakai “Anda” atau “saya” lagi dalam bicara. Dia bekerja di sebuah LSM yang banyak bergerak pada advokasi masyarakat miskin kota. Ketika kusebut nama Wardah Hafidz, dia mengatakan bahwa dia tak ada hubungannya dengan Urban Poor Consortium itu. “Kami hanya kumpulan orang-orang kecil yang mencoba peduli dengan mereka yang terjepit di kota ini. Kamu tahu? Kemiskinan adalah sebuah rasa sakit serupa bisul yang bernanah dan siap untuk pecah. Tidak ada orang yang ingin menjadi miskin. Tetapi siapa yang bisa menolak ketika hal itu menjadi sebuah nasib?”
Kukatakan bahwa aku hanya seorang fotografer yang hanya bisa memotret dan tak paham dengan konsep-konsep kemiskinan yang banyak dia pahami. “Aku sering memotret orang miskin. Dan menurutku, adalah hak semua orang untuk tidak miskin di negri ini...”
“Ya. Pemerintah sebenarnya bisa membangun sekolah-sekolah lebih banyak, menggratiskan biaya pendidikan, membangun rumah sakit dan meringankan beban mereka yang miskin. Tetapi itu tidak dilakukan. Kemiskinan dipandang sebagai takdir, padahal itu bisa musnahkan. Namun, biaya pendidikan banyak dimakan para pejabat, obat-obatan ditilep, masyarakat dibiarkan miskin dan bodoh. Aku muak dengan semua ini...”
Lama-lama, aku semakin tahu dengan kehidupannya. Dia suka malam dan hujan, dan sering ketika hujan datang saat kami jalan, dia tiba-tiba mengatakan ingin keluar dari mobil dan berjalan kaki dalam hujan yang deras. Kukatakan bahwa itu akan membahayakan kesehatannya, tetapi dia menjawab bahwa dia sudah terbiasa dengan hal itu. “Aku mencintai malam dan hujan. Keduanya sudah lama berada dalam darah dan jiwaku...” katanya sambil berteriak karena harus melawan suara hujan. Aku mengikutinya di dalam mobil dengan lambat. Dia jalan di trotoar, sedang aku mengemudikan mobil tidak jauh darinya dan sangat pelan sekali.
“Kenapa?” aku bertanya.
“Malam dan hujan adalah dua hal yang membuatku merasa hidup.”
“Oya? Seandainya tidak ada malam dan tidak ada hujan?”
“Mungkin aku akan mati,” katanya sambil tertawa. Aku suka cara dia tertawa. Wajahnya menatap langit yang mencurahkan air, dan dibiarkannya wajah itu dijatuhi air hujan dan kemudian dia berteriak sekeras-kerasnya. “Jika aku mati, aku ingin ketika sedang berada di sebuah malam yang hujan seperti ini,” katanya masih dengan suara keras dan kemudian tetawa lagi.
Aku bergidik. Aku tak suka bicara tentang kematian. Bagiku, hidup harus terus dijalani dan kematian adalah sebuah takdir dan nasib yang tak bisa dielakkan. Kematian adalah sebuah akhir, dan sebelum itu muncul, maka hidup harus terus berjalan dan diikuti. “Aku tak suka kamu bicara tentang kematian. Mengerikan...”
Dia kemudian meminta aku menghentikan mobil. Dengan basah kuyup, dia masuk ke mobil dan aku bisa merasakan betapa dinginnya tubuhnya. Dia tidak menggigil. Dia mengatakan bahwa hujan selalu memberikannya semangat untuk memulai hidup yang lebih baik, meski dia tak pernah menemui lagi hidup yang lebih baik seperti yang diinginkannya itu.
“Mengapa harus malam dan hujan? Bukankah ada hal-hal lain lagi yang bisa menjadikan hidupmu lebih baik lagi? Cinta, misalnya. Atau lukisan seperti yang pernah kamu datangi waktu kita ketemu dulu? Masih ada yang lain kukira yang bisa membuat kita bersemangat untuk meneruskan hidup...”
Aku membawanya ke rumahku di Kembangan. Aku mengontrak sebuah rumah kecil dan itu cukup bagiku. Aku cukup nyaman di sana selama ini. Jika ada libur dan kesempatan, aku pulang ke Bogor, pulang ke rumahku yang sesungguhnya. Jakarta telah menjadikanku kaku, tetapi inilah yang memang harus kulakukan. Aku mencintai pekerjaan ini, dan aku menganggap meski kaku, tetap ada hal-hal yang menghuni dan mengisi pekerjaanku. Aku tidak bosan, hanya sering suntuk saja dan itu bisa hilang dalam beberapa jam. Fotografi adalah seni bagiku, dan ketika aku harus bekerja karena seni itu, maka yang muncul dalam diriku adalah kecintaan. Aku akan berusaha mendapatkan foto yang bagus, artistik dan tidak hanya memenuhi nilai berita sebuah foto. Memang, mulanya aku agak kaku ketika seni fotografi yang kudalami harus dituntut dengan kuantitas dan ketepatan waktu dalam dunia pers. Aku harus melakukan penyesuaian beberapa lama dan itu ternyata memang hanya sebuah proses waktu. Sekali lagi, aku mencintai duniaku sekarang. Paling tidak, dia telah menjadi sebuah jalan yang tak pernah kusesali, dan aku terus menapakinya.
“Kadang-kadang aku juga ingin sepertimu, bekerja yang benar dan mencintai pekerjaan itu...” katanya ketika sampai di rumahku.
“Selama ini kamu tidak pernah mencintai pekerjaanmu?”
“Apakah apa yang kulakukan ini sebuah pekerjaan?” Dia memandangku dengan tajam. Kemudian, katanya lagi, “Kamu mengingatkanku pada ibuku...”
Aku terpana dan agak kikuk ditatap dan dikatakan seperti itu. “Pasti dia sangat berarti bagimu...”
“Ya. Dia sangat berarti. Dia perempuan yang kuat. Sering aku merindukannya dan merasa berdosa karena meninggalkannya. Tetapi kemudian aku bersyukur karena kedua adikku tetap berada di rumah. Mereka bekerja keras bersama penduduk lainnya untuk mempertahankan tanah kami...”
“Tanah?”
“Sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapat izin dari pemerintah memasukkan tanah warga kampung kami ke dalam arealnya. Katanya, kampung kami tidak ada dalam peta. Yang ada dalam peta mereka, kawasan itu adalah hutan semua.”
“Apa yang dilakukan oleh penduduk kampungmu?” Aku mendekatinya, memegang jemarinya.
Dia mengatakan bahwa mereka dengan berbagai upaya melawan apa yang dilakukan perusahaan itu. Mulanya mereka memprotes ke kecamatan sampai ke kabupaten, namun tetap tak ada hasilnya. Lama-lama, ketegangan menjadi kian sering terjadi dan akhirnya banyak warga yang diintimidasi orang tak dikenal. Dia kemudian menjadi marah karena tekanan dan ketegangan itu membuat bapaknya sakit dan akhirnya meninggal tak berapa lama setelah terjadi bentrokan antara warga dengan orang-orang perusahaan yang membuat kantor polisi terbakar. Dia mengatakan bahwa bentrokan itu terjadi karena penduduk ingin membebaskannya setelah dia dipermak petugas keamanan di kantor perusahaan sawit itu sebelumnya.. “Aku datang ke kantor mereka tetapi aku hanya berdua dan mereka memiliki pengamanan yang terlatih. Aku bisa keluar dari kantor itu, tetapi tubuhku menjadi amukan mereka sebelum aku dibawa ke kantor polisi.”
“Tak ada yang menolong? Kamu terluka parahkah?”
“Tuhan pun tak mau menolongku. Tetapi aku tak benci Tuhan seperti aku tak pernah membenci bapak. Aku hanya benci mengapa beban hidup seperti itu selalu muncul dalam kehidupanku. Namun kemudian aku benar-benar tak tahan. Jika aku tetap berada di sana, aku akan menjadi seorang pembunuh karena dendam dan sakit hati...”
“Lalu mengapa kamu berada di Solo ketika itu?”
“Aku pergi dan melarikan diri. Aku tak tahan lama-lama di sana...”
Aku merasakan dia mulai kedinginan meskipun dia sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian baru yang kami beli di toko ketika akan pulang. Dia menggigil dan memelukku. Aku senang diperlakukan seperti itu. Aku menikmatinya, menikmati pelukan lelaki dengan masa lalu berat seperti dirinya. Seluruh perjalanan hidup yang diceritakannya padaku membuat aku trenyuh. Aku ke dapur dan memanaskan air dan membuatkan teh hangat untuknya. Dia kemudian merasa hangat dan kami bercerita lagi. Kali ini, katanya, dia tiba-tiba ingat namaku.
“Namamu mengingatkanku pada sebuah klub sepakbola Italia, Fiorentina. Itu klub besar di sana dengan warna kebanggaan ungu. Itu makanya julukan La Viola melekat di tubuh klub itu, artinya Si Ungu. Nah, nama kotanya mirip namamu, Florence, menurut orang Inggris. Sedang orang Italia menamakannya Firenze... Namamu bagus...”
“Kamu suka sepakbola?”
“Ya. Aku suka sepakbola dan aku suka Fiorentina. Klub itu pernah melahirkan pemain-pemain besar seperti Roberto Baggio sebelum pindah ke Juventus dan menjadi pemain terbaik dunia. Setelah kepergian Baggio seusai Piala Dunia 1990, datanglah Gabriel Batistuta, orang Argentina yang dianggap dewa oleh para pendukung Fiorentina. Bahkan patung Batistuta dibuat di depan Stadion Artemio Franchi. Namun, sembilan tahun dia di sana, tak satupun gelar yang didapatnya. Batistuta kemudian pindah ke AS Roma dan mendapat gelar juara liga di sana, sementara Fiorentina harus berjuang di Seri B setelah kegagalan mereka bersaing di level atas sepakbola Italia. Belakangan Fiorentina malah sampai ke Seri C karena dinyatakan bangkrut, sebelum kemudian merangkak lagi untuk memperbaiki prestasinya, setelah masuknya pengusaha sepatu...”
Aku tertawa mendengar ceritanya. Dia sangat hafal dengan sejarah klub itu. “Lalu apa hubungannya dengan namaku? Kamu seperti komentator sepakbola di televisi...”
“Namamu bagus, Flo...”
“Florentina... Itu nama baptisku.”
“Itu yang ingin kutanyakan padamu. Kamu seorang muslim, bukan?”
“Sekarang, ya. Aku lahir dari keluarga Khatolik dan besar dengan agama itu. Namun ketika masuk SMA, aku tak menemukan kenyamanan dan kemudian seorang temanku mengajakku untuk ikut pengajian yang diadakan oleh sekolah. Aku tertarik dan kemudian menjadi muslim. Awalnya memang berat. Aku harus berjuang meyakinkan ayahku dan seluruh keluargaku bahwa aku berhak memilih, sebab itu hal yang paling penting dalam hidupku meskipun selama menjadi Khatolik atau sekarang menjadi Islam, aku juga bukan orang yang taat. Semua agama baik, tetapi aku merasa lebih baik dengan pilihanku sekarang...”
“Dan nama baptis itu tetap kamu pakai?”
“Aku suka nama itu...”
“Nama aslimu siapa?”
“Kartika Ayu Darmawatiningtyas dengan baptis Florentina...”
“Namamu benar-benar indah...”
Kami berciuman lama, dan setelah itu aku tak tahu apa yang terjadi. Pagi-pagi ketika terbangun, aku tak mendapatinya lagi. Itulah kali pertama dia menghilang setelah semalam kami bersama dalam sebuah cerita yang tak bisa kuceritakan di sini.
BEBERAPA hari setelah itu, aku mendengar akan ada demo yang melibatkan buruh di beberapa pabrik di Tangerang, Urban Poor Concortium, dan beberapa elemen LSM yang gerakannya segaris. Mereka akan memperingati Hari Buruh dengan cara demo di jalanan. Kabarnya, kawasan Sudirman, Thamrin hingga Monas akan dipenuhi massa. Teman-teman di kantor sudah mendapat kabar ini jauh-jauh hari, dan aku langsung teringat padanya. Tetapi, ke mana aku harus mencarinya untuk menanyakannya apakah dia ikut dalam gerakan ini? Dia tak meninggalkan jejak apapun kepadaku. Tidak alamat atau nomor telefon yang bisa kubuhubungi.
Seperti keinginanku, malamnya dia datang ke kantorku ketika aku akan pulang. Dia mengatakan kangen, tetapi aku balas dengan meninju dadanya. Aku menangis. “Kau membiarkan aku terombang-ambing beberapa hari ini. Mengapa kau meninggalkanku dan tak memberi kabar apapun?”
Kami kemudian menuju mobil dan aku mengajaknya ke rumah.
“Maafkan aku. Aku telah melibatkanmu dalam kehidupanku yang rumit...”
“Kamu yang menganggap rumit. Kenapa? Apakah kau kira aku tak bisa dan tak boleh hidup dalam kerumitanmu itu?”
“Flo... Aku hidup mengikuti arah angin dan matahari. Aku tak punya rencana-rencana seperti orang-orang yang berpikir tentang masa depan. Aku mengikuti waktu dan tak pernah mempedulikan tentang kebahagiaan di suatu saat nanti. Itu sangat buruk kukira. Jangan mengikuti jejakku, Flo...”
“Kenapa? Apakah kamu melakukan itu karena kamu dendam dengan apa yang dilakukan bapakmu kepadamu?”
“Bapakku telah mengajarkan kepadaku tentang sebuah pelajaran hidup yang sebenarnya. Aku tak pernah dendam kepadanya meski ketika itu aku benar-benar marah dan sangat kecewa...”
“Lalu kenapa?”
“Aku tak pernah jatuh cinta kepada seorang perempuan, Flo. Aku tak ingin kamu sengsara bersama denganku, karena perempuan yang kucintai itu kamu...”
“Benarkah?” Aku memeluknya
“Seorang laki-laki harus melindungi perempuannya, dan aku tak akan bisa melakukannya terhadapmu. Aku akan selalu pergi mengikuti angin dan matahari, mengikuti perasaan-perasaanku, kekecewaan-kekecewaanku...”
Aku memeluknya dan mengatakan bahwa aku akan menerima apapun yang terjadi. Aku ingin mengikuti angin yang diikutinya, matahari yang diikutinya, perasaan yang diikutinya, kekecewaan yang diikutinya... Aku ingin merasakannya, seperti merasakan ketika dia pingsan karena harus menanggung beban berat di tubuhnya di malam yang dingin dan hujan di ladang karet itu. Aku mengatakan kepadanya bahwa rasa cintanya kepadaku itu telah membuatku berada di dunia lain, tetapi nyata dan indah. Dunia yang membuat aku tak ingin berhubungan dengan orang lain selain mendengar cerita-ceritanya yang satir dan getir tentang bagaimana dia memandang dunianya. Getir dan satir, namun di telinga dan perasaanku terasa indah dan nyaman. Aku ingin mengubah dunianya dalam ceritanya itu menjadi penuh warna keindahan.
Aku benar-benar masuk dalam dunianya, meski segala keanehan yang selalu muncul dan membuatku cemas. Tentang kecintaannya kepada malam dan hujan. Hampir di setiap malam dan hujan, dia keluar rumah dan membiarkan dirinya berada dalam hujan yang membasahkan seluruh tubuhnya –yang di mataku dia terlihat seksi, jantan dan menggairahkan. Namun, sering juga kemudian dia menggigil tanpa ada sebabnya di malam yang tak hujan dan bahkan panas. Dia kedinginan dan aku harus pontang-panting mencarikan selimut dan bahkan aku membiarkan tubuhku menjadi selimut baginya. Aku membuka seluruh pakaian di tubuhnya, juga yang ada di tubuhku. Semuanya. Dan aku memeluknya sambil menangis, hingga seluruh air mataku mengalir ke tubuhnya dan sering kemudian dia siuman dan kemudian mengatakan bahwa dia sangat mencintaiku.
Aku tahu, malam dan hujan memang menjadi bagian dari hidupnya. Malam dan hujan yang menjadi lembaran hitam dalam sejarah hidupnya saat di kampungnya, dirubahnya menjadi sebuah kecintaan yang mengerikan bagiku, meski kemudian pelan-pelan aku bisa memahaminya.
Dan, ketika kemudian dia ikut terlibat dalam demonstrasi buruh dan masyarakat miskin kota yang kemudian berubah menjadi huru-hara dan kerusuhan itu, aku juga berusaha untuk memahaminya. Dia mengatakan bahwa selama ini kemiskinan hanya menjadi tontonan para borjuis dan banyak dijadikan proyek oleh para pejabat dan pengusaha untuk kekayaan sendiri. “Semua orang berhak untuk hidup lebih baik dan negara ini punya uang untuk membuat rakyatnya terbebas dari segala penderitaan itu. Di Riau, ada seorang bupati yang membangun rumah dinasnya dengan angka yang sangat fantastis, 25 miliar rupiah. Juga banyak pejabat yang tak mau naik mobil mewah biasa, mereka membeli yang harganya tinggi biar dikatakan keren. Bukankah Riau daerah kaya? Mungkin begitu pikiran mereka. Para wakil rakyat juga dengan senang hati ketika dibagi-bagi mobil mewah sehingga semua ajuan anggaran disepakati dan di belakang dipotong ramai-ramai. Aku yakin di Jakarta ini dan di daerah lain, hal serupa terjadi...”
Maka, katanya, harus ada sebuah gerakan sosial yang harus mengubah itu karena gerakan moral sudah tidak dipedulikan lagi. “Mereka sudah tidak memiliki moral lagi. Moral hanya menjadi sebuah legenda bagi mereka, sementara bagi masyarakat kecil, hanya itulah yang mereka miliki selain kejujuran, karena kekayaan dan kebanggaan mereka sudah tidak memiliki lagi...”
Bulu kudukku bergidik mendengar apa yang dikatakannya itu. Apa lagi kemudian dia menyebut-nyebut banyak tokoh pergerakan yang katanya menjadi pahlawan sejati bagi masyarakat dunia. “Kamu harus tahu, di balik baju lusuh dan sepeda butut yang dikendarai Wang Dan, ada tersimpan magma dan semangat yang menjadi inspirasi bagi anak-anak muda dan mahasiswa Cina yang menginginkan perubahan. Meskipun kemudian dia mati di tangan diktaktor komunis bersama ratusan mahasiswa lainnya di Tiananmen, tetapi orang pasti tahu bahwa lambat tapi pasti, perubahan itu akan terwujud...”
“Tapi gerakan Wang Dan, Che Guevarra, dan sekian penggerak demokrasi maupun aktivis sosial, didukung oleh dunia internasional. Sedang gerakanmu, siapa yang mendukung?”
“Aku tak ingin terkenal seperti Wang Dan atau tokoh-tokoh lainnya. Aku hanya ingin kemiskinan dibuang dan masyarakat diberi keadilan yang memang pantas mereka terima. Negara ini kaya, Flo...”
Setelah bentrokan yang menimbulkan korban luka-luka baik aparat maupun buruh dan masyarakat miskin itu, dia kemudian menghilang agak lama. Beberapa sumber yang kudengar menyebutkan bahwa dia masuk salah satu orang yang diburu aparat untuk dimintai keterangan. Dia menelponku bahwa dia berada di suatu tempat di Solo. “Aku aman, Flo. Nanti kalau semuanya baik-baik saja, aku akan mengabarimu lagi. Mungkin wartel tempatku menelponmu ini juga sudah diawasi oleh inteljen. Tetapi, sejatinya aku tak takut tertangkap. Apakah dengan gerakan dan bentrokan seperti itu, aku harus masuk penjara? Jika semua orang yang melakukan demonstrasi dan bentrokan itu masuk penjara, penjara akan penuh dan pemerintah akan repot mengurus kami yang kemudian mereka malah tak mau mengurus orang-orang miskin yang kami perjuangkan itu Flo...”
Aku kemudian menjadi paham, mengapa dia bersikeras tidak mau fotonya dicetak atau malah masuk koran. Namun, aku tetap mencetaknya dan menyimpannya di dalam kamarku. Menjadikannya sebagai pengobat rindu, atau hanya kenangan?
Bagian III
BAPAK memang menginginkan aku menjadi laki-laki yang kuat. Katanya, lelaki harus bisa melindungi perempuannya, bisa saja kekasih atau istrinya, juga anak-anaknya. Katanya, jika dia menelantarkan perempuan dan anak-anaknya, maka dia bukan laki-laki. Dia lebih buruk dari banci dan mirip babi! Bapak sangat benci dengan babi. Ketika kami masih kecil, kami sering diajak tidur di gubuk di pinggir hutan untuk menghalau babi yang merusak dan memakan tanaman padi, juga sayuran. Ketika itu adikku yang paling kecil belum lahir sehingga aku dan adikku, juga ibuku, harus mengungsi ke hutan setiap malam untuk ikut bapak menjaga padi gogo. Sebenarnya, aku lebih banyak tidur ketimbang menjaga. Bapak dan ibuku yang sering terbangun dan menarik-narik tali di empat arah yang masing-masing disambungkan dengan orang-orangan yang di sana ditalikan bermacam kaleng yang kalau ditarik-tarik bisa menimbulkan suara gaduh.
Pagi-pagi, kami kembali lagi ke rumah dan aku pergi ke sekolah sementara adikku yang masih kecil bermain tidak jauh dari rumah. Tidak jauh dari rumah, itu perintah bapak, karena katanya kalau jauh dari rumah, saat diperlukan dia tidak ada. “Dari kecil ini, kalian harus selalu ada ketika diperlukan oleh keluargamu. Ketika kayu bakar habis, kalian harus mencarinya untuk memasak. Jika air habis, kalian harus mengangkutnya dari sungai. Kalian juga yang harus berbelanja ke warung biar emakmu tidak perlu capek karena dia sudah capek memasakkan nasi dan lauk untuk kalian.” Begitu kata bapak, juga beberapa kata lainnya.
Aku tak menjawab apa-apa, juga adikku.
Aku pergi ke sekolah berjalan kaki sekitar tiga kilo, sementara adikku bermain tidak jauh dari rumah. Sementara bapak kembali lagi ke ladang padi untuk menjaga padi dari serangan beruk dan monyet yang sering datang bergerombol untuk merusak padi-padi kami. Sebenarnya, tidak hanya kami yang menanam padi. Para tetangga juga menanam dan ketika malam saat berjaga, kadang mereka, orang-orang tua itu, bercengkrama di bahwa gubuk dan aku memilih tidak mendengarkan.
“Kita harus bekerja untuk mendapatkan apa yang akan kita makan dan uang. Kamu harus paham itu. Jangan sisakan makanan yang ada dalam piringmu, ingatlah semua jerih-payah kita untuk mendapatkannya. Kelak, jika kamu dewasa dan ketika aku tidak bisa bekerja lagi, kamu akan tahu bagaimana susahnya untuk mendapatkan makanan dan keperluan hidup. Bapakmu makin lama akan makin tua, dan kalian berdua akan tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang kuat. Kalianlah yang harus menggantikan aku untuk menghidupi keluargamu. Laki-laki harus begitu...”
“Iya, Bapak...”
KETIKA tanah tak lagi menyisakan humus setelah ditanam tiga atau empat kali, penduduk kampung kami menaminya dengan pohon karet. Kami kemudian berpindah lagi untuk membuka ladang baru untuk ditanami padi dan palawija sambil menunggu tanaman karet kami bisa ditakik setelah berusia lima sampai enam tahun. Dan selama itu, kami tetap harus mengungsi ke ladang di pinggir hutan lindung untuk menjaga serangan babi.
Aku sudah masuk SMP ketika itu, ketika karet kami sudah bisa disadap dan getahnya bisa dijual untuk digantikan dengan uang. Uang itulah yang dipergunakan oleh keluargaku untuk biaya sekolahku dan dua adikku (adikku yang paling kecil lahir kemudian), dan untuk kebutuhan sehari-hari. Aku bisa memahami kalau bapak memang sangat hati-hati dalam membelanjakan uang. Yang penting, katanya, biaya sekolah kami tetap ada, sementara kami tak memikirkan bagaimana mendapatkan beras karena hasil panen sekali setahun tanaman padi gogo bisa menghidupi kami dalam setahun juga. Kami punya gudang untuk tempat padi dan gabah. Hampir semua orang kampung punya.
Bapak yang mengajariku bagaimana menakik pohon karet yang baik agar pisau sadapnya tidak menyentuh batang kayu. Sebab, kalau sampai batang kayunya teriris, maka kulitnya akan lama untuk pulih sehingga ketika harus mengulangi menyadap di kulit baru beberapa tahun kemudian, akan kesulitan, dan getah yang diharapkan tidak sebanyak yang awal. Hal itu juga akan membuat jamur lebih gampang menyerang pohon yang kemudian sering tiba-tiba pohon karet itu meranggas kering dan mati.
“Begini...” kata bapak sambil memegangkan pisau ke tangan kananku. “Tangan kananmu yang memegang gagangnya, dan tangan kiri menjadi penyeimbang di besinya. Pelan-pelan, naik-turunkan secara pelan agar pisau tidak memakan terlalu tebal kulit, dan sisi kanannya tidak terlalu masuk ke dalam agar tidak menyentuh batang kayunya....”
Aku tak perlu menjawab. Yang kuperlukan adalah memahami apa yang dikatakannya. Dan hanya dalam waktu seminggu, aku sudah sangat fasih menyadap karet untuk mendapatkan getah yang bau awalnya saat menetes di mangkok yang terbuat dari bathok kelapa itu, lumayan harum. Namun setelah nanti diambil getak lateks berwarna putih itu dan disatukan ke dalam sebuah bak untuk dibekukan memakai pupuk TSP yang sudah dilarutkan ke dalam air sebagai pengganti asam cuka, beberapa hari kemudian baunya sangat bacin.
Mulanya, aku agak mual ketika harus memegang dan sering harus ikut membantu bapak memanggul bantalan getah itu untuk dibawa ke rawa, agar tetap berada dalam air. Namun akhirnya lama-lama itu seperti sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku memang tidak bisa ikut menakik setiap pagi karena harus ke sekolah, tetapi sorenya, ketika masih ada pohon yang belum tersadap oleh bapak dan emak, aku sering ikut membantu. Ketika selesai Ashar, kami mengambil lateks dari mangkok di pohon satu per satu, dan kemudian membawanya untuk dikentalkan. Setelah itu, aku bisa bermain voli atau sepakbola bersama teman-teman di lapangan, tidak jauh dari rumah.
“Laki-laki itu, yang paling penting adalah tanggung jawab. Tanggung jawab apa saja, terhadap pekerjaan yang harus dikerjakannya terutama. Dan itu memerlukan kedisiplinan, mengatur waktu, kapan saatnya sekolah, membantu di ladang, olahraga dan belajar di malam hari sebelum tidur. Mungkin ini akan membosankan, tetapi suatu saat kamu akan memahami ini...”
Aku hanya mengangguk beberapa kali. Dari kecil, aku memang tak pernah belajar untuk bertanya atau menjawab apa yang dikatakan oleh bapak. Menurut emak, memang tidak ada yang perlu dijawab dan dipertanyakan apa yang dikatakan bapak. Cukup dilaksanakan, semuanya akan selesai. Dan memang, selama ini, semuanya begitu. Selesai. Meski kadang-kadang aku rindu ingin berbincang-bincang dengan bapak. Paling tidak, ada komunikasi dua arah, bukan hanya satu arah dan aku hanya mengangguk dan kemudian melaksanakan. Ini kusadari ketika aku sudah masuk SMA di kota kecamatan, yang harus berangkat dengan sepeda sejauh lebih 15 kilo meter.
“Tapi itu tidak penting. Yang paling penting bagimu adalah belajar yang tekun. Jangan seperti Emak yang tak pandai membaca. Kamu harus jadi orang pintar, terserah mau jadi apa kamu nanti...”
“Iya, Mak...”
Kehidupan berjalan dengan baik dan normal. Aku menikmati apa yang kami dapatkan, menyelesaikan semuanya dengan baik tanpa harus mempertanyakan terlalu rumit apa-apa yang telah kami lakukan. Namun, semuanya menjadi berat ketika kejadian itu membuat hampir seluruh penduduk kampung akhirnya berada dalam situasi yang rumit.
Sebenarnya, kasak-kusuk itu sudah muncul sebelumnya, bahwa juragan Marno, salah seorang yang paling berpengaruh di kampungku, sering bertindak sewenang-wenang terhadap penduduk. Dia lumayan kaya. Punya dua mobil truk dan satu mobil pribadi. Dialah yang selama ini menjadi pedagang pengumpul getah karet kami, dan dari bisnis ini, dia benar-benar memiliki segalanya. Namun, lama-lama para petani karet tahu, dia sering bertindak curang. Dia sering mengurangi timbangan, membeli dengan harga yang rendah –kata bapak, harga yang diberikannya sangat jauh dengan harga beberapa tauke lain di kampung tetangga dan selama ini tidak ada yang mempertanyakan— dan malah belakangan sering main pukul terhadap beberapa petani yang mempertanyakan soal harga itu. Dan berita yang paling baru adalah, Marno sering mengganggu wanita, baik yang sudah berkeluarga, janda atau beberapa gadis. Aku sendiri tidak tahu itu, tetapi bisik-bisik itu berkembang sampai jauh.
Mulanya, aku sering mendapati bapak sering pulang malam –ketika itu kami sedang tidak berjaga di ladang karena habis panen. Ibuku mengatakan bahwa bapak pergi ke rumah Madrohi, salah seorang penduduk yang dikabarkan sepekan sebelumnya dipukuli oleh Marno sampai lebam-lebam. Katanya, banyak penduduk kampung yang pergi ke rumahnya setiap malam, juga banyak pemuda desa yang usianya memang lebih muda dari usia bapak dan orang tua lainnya. Aku hanya mendengar sebatas itu dari emak, dan aku memang tidak banyak bertanya lagi.
Tapi bapak memang sering pulang malam, dan sering aku yang membukakan pintu. Kadang sampai jam 12 malam, atau malah sering lebih. Aku tidak bertanya apa-apa kepadanya; tidak patut, bukan urusan anak kecil, dan memang selama ini aku memang tak pernah bertanya apa-apa kepada bapak, aku hanya semakin sering mendengar bahwa penduduk kampung kami sudah semakin muak dengan apa yang dilakukan Marno. Lelaki berumur 40 tahunan itu, kata berita-berita itu, sudah semakin keterlaluan. Ada penduduk yang dipukul, dimaki-maki seperti anak kecil, getahnya tidak dibayar, dan –ini yang lebih keterlaluan— Marno juga malah semakin sering menganggu perempuan di kampung.
Sama seperti kami, Marno sebenarnya adalah pendatang. Katanya, dia dulu seorang preman di Pasar Legi, Solo. Kabarnya lagi, dia sangat ditakuti oleh semua preman di sana sebelum akhirnya ia menyeberang ke Sumatera membawa seorang perempuan tanpa anak, yang memang sangat cantik dan muda, jauh dari usianya. Beberapa kali aku melihat istrinya saat sore akan pergi main bola yang melewati rumah besar Marno yang berpagar rapi. Aku yang masih SMP ketika itu, memang mengakui bahwa istri Marno memang canntik. Teman-teman juga mengatakannya demikian.
Hampir seluruh warga kampung kami adalah pendatang. Ada yang dari Jawa, Sumatera Utara, Padang, dan beberapa daerah lainnya. Kebanyakan dari Jawa, Medan, Padang dan dari beberapa daerah di Teluk Kuantan. Hampir dua puluh tahun yang lalu, kampung ini masih berupa hutan lebat, dan satu per satu, pada pendatang membukanya. Bapak pindah ke sini dari Logas hanya beberapa bulan setelah menikah dengan ibuku, dan menjadi keluarga ke-12 di kampung ini sebelum kemudian berdatangan keluarga-keluarga lain dari berbagai suku. Kata ibuku, awalnya memang sulit beradaptasi dengan banyak suku seperti ini, tetapi kemudian semuanya menjadi baik. Orang-orang yang datang dari Jawa –-mereka tidak transmigrasi, tetapi katanya merantau— akhirnya sedikit-sedikit bisa memakai bahasa Indonesia meski masih bercampur bahasa Jawa. Mereka yang datang dari Medan juga begitu, pun mereka yang datang dari Sumbar dan orang-orang Riau yang datang dari berbagai daerah. Mereka membuka ladang dengan giliran. Dan dengan cara inilah akhirnya kampung ini benar-benar menjadi kampung. Pemerintah kemudian melebarkan jalan yang menghubungkan langsung dengan Lintas Sumatera, sekita 15 kilo. Sebelum jalan itu dibesarkan, kata ibuku, memang sudah ada jalan lama yang dibuat oleh sebuah perusahaan HPH yang mengambil kayu di hutan, masih beberapa kilo lagi dari kampung kami. Katanya perusahaan itu bernama Inhutani IV. Akses jalan ke kampung kami bukan jalan utama mereka, tetapi bagi kami sudah cukup untuk bisa digunakan sebagai jalan yang fungsinya sangat penting.
Itu makanya, berladang berpindah masih dilakukan penduduk untuk membuka hutan bekas tebangan Inhutani IV itu. Bapak pernah bercerita, bahwa di kawasan ini, kawanan harimau dan gajah masih banyak, meski hingga kini aku tak pernah secara langsung bertemu dengan binatang-binatang buas itu. Meski kadang-kadang, aku melihat ada rasa was-was di muka bapak dan penduduk kampung lainnya ketika kami menunggui ladang padi, karena kalau gajah datang menyerbu, tidak akan ada yang berani melawan selain melarikan diri. Tapi benar, sampai aku menceritakan ini, belum pernah sekalipun aku berhadapan langsung dengan gajah yang masuk perkampungan penduduk.
PERIHAL Marno, kata ibuku lagi, dia datang beberapa tahun setelah kami menetap di kampung ini. Mulanya dia datang sebagai orang biasa; menumpang di salah satu rumah penduduk asal Jawa, dan kemudian beberapa bulan setelah itu mendirikan pondok sendiri. Sama seperti penduduk lainnya, Marno juga membuka ladang untuk ditanami padi dan menjual kayunya kepada touke-touke yang datang dari Pekanbaru dengan harga yang rendah. Beberapa bulan setelah itu, Marno memiliki mesin cainshaw sendiri dan bekerja membalak kayu di hutan bersama beberapa penduduk kampung. Lama-lama, usahanya berkembang dan dia bisa membeli truk. Dia kemudian menanam ladangnya dengan tanaman karet dan memiliki beberapa anak buah untuk membalak kayu di hutan. Ketika pohon karet mulai menghasilkan, Marno kemudian terjun di bisnis jual-beli tersebut. Penduduk kampung tetap melihat dan menilai Marno sebagai salah satu bagian dari mereka dengan segala kebaikannya. Tidak banyak omong, bekerja tekun, lumayan pandai dan tidak terlihat kalau dia bekas preman di Pasar Legi seperti cerita yang berkembang.
Semua usaha yang dilakukan Marno berhasil dan tumbuh dengan baik. Dua anaknya kemudian lahir dan istrinya masih saja kelihatan cantik. Namun belakangan, tabiatnya berubah, dan mungkin itulah tabiat aslinya. Dia menjadi orang sukses, kaya dan bisa membeli apa saja. Awalnya, seluruh warga menganggapnya sebagai kekilafannya, tetapi kemudian mereka menjadi marah karena hal itu sering terulang dan terulang. Hingga akhirnya aku sering melihat bapak pulang malam yang katanya pergi ke rumah Madrohi, salah seorang penduduk yang jadi bulan-bulanan Marno beberapa hari sebelumnya.
Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Namun hembusan angin itu juga sampai ke telingaku, bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu yang buruk akan terjadi dan aku tidak tahu apa bentuknya. Hingga pada sebuah Subuh, aku terjaga ketika ibuku mengatakan bahwa benar telah terjadi sesuatu. Dua adikku tetap tidur ketika aku menyelinap keluar rumah dan berjalan kaki sejauh satu kilo menuju sebuah rumah besar di tengah-tengah kampung. Di sana, telah berkumpul banyak orang dengan masing-masing memegang senter dan senjata. Ada pisau, parang, sabit, clurit, batangan besi, kayu bloti dan senjata-senjata lainnya. Semuanya laki-laki, muda dan orang tua. Aku melihat dari agak kejauhan dan tidak bisa melihat apa yang benar-benar terjadi.
Pagi-pagi aku baru tahu kisah sebenarnya.
Tengah malam, hampir seluruh penduduk sudah berkumpul di rumah Madrohi. Dengan senjata-senjata yang mereka bawa, juga senter dan obor di tangan, mereka bergerak ke rumah Marno menjelang Subuh. Sebenarnya Marno sudah tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya, paling tidak dia paham bahwa akan ada kemarahan dari warga terhadap dirinya. Yang terjadi, dia sudah menyiapkan beberapa orang preman dari luar kampung yang selama ini memang sering berada di rumahnya. Dia yakin, bahwa warga tidak akan berani memasuki pagar rumahnya, apalagi masuk ke pintu rumahnya. Semuanya sudah dijaga oleh anak buahnya. Namun malang, jumlah warga terlalu banyak, anak buahnya tak bisa melawan dan akhirnya mereka dibuat lari terbirit-birit keluar kampung dengan motor mereka masing-masing. Ada yang sempat selamat dan tanpa luka apa-apa, tetapi ada yang sempat semaput karena pukulan kayu bloti dan besi, atau malah terluka oleh pisau dan parang yang dibawa warga.
Aku mendapatkan cerita ini dari Zamzami, pemuda yang umurnya lebih tua dariku, tetapi kami sering bermain bola bersama hampir setiap sore. Katanya, “Setelah kami berhasil melumpuhkan anak buah Marno, secara serentak, kami masuk ke tiga pintu masuk di rumahnya...”
Targetnya adalah Marno. Harus mati, malam itu juga. Dua anak dan istrinya tidak boleh disentuh. Anak-anak dan wanita harus dijauhkan dari kekerasan. Tetapi, mengapa harus ada kekerasan seperti itu? Sebab, kata Zamzami, Marno sudah keterlaluan, dan kemarahan warga sudah berada di titik puncak, tidak bisa ditawar lagi. Marno tidak saja telah melukai warga secara fisik, tetapi kelakuannya terhadap para perempuan, dianggap sudah tidak bisa dimaafkan. Selama ini warga memang terkesan diam dan ketakutan, tetapi sekarang tidak. Mereka bersama-sama, tak ada yang harus ditakutkan. Dan, menjelang Subuh malam itu, Marno memang menemui nasib yang tragis.
“Dia berusaha mengunci dirinya di dalam kamar bersama anak dan istrinya. Tapi pintu berhasil kami jebol...”
Dua anak dan istrinya dikeluarkan dan dijauhkan dari Marno. Mereka dibawa pergi ke rumah sebelah dan dijaga oleh beberapa laki-laki. Mereka menangis dan meraung-raung, seakan tahu apa yang akan terjadi pada Marno. Tetapi mereka tetap dibawa, tidak diapa-apakan, hanya dijauhkan dari Marno. “Ampunkan suamiku... Ampuni dia...” suara Ambar, istri Marno, melengking, tetapi dia dan dua anaknya tetap dijauhkan dari Marno.
Di rumah Marno, kejadiannya sangat cepat. Setelah anak dan istrinya berhasil dikeluarkan, Marno ditarik beberapa laki-laki keluar kamar. Tapi, dia berhasil melepaskan diri dan berlari ke arah belakang rumahnya. Ternyata, di sana, puluhan laki-laki sudah menunggu dengan senjata masing-masing. Marno berusaha menerobos, tetapi sial, sabetan dan pukulan senjata itu membuat dia meraung meski tetap berlari. Dan sialnya lagi, di belakang rumahnya da kolam berukuran sekitar 3x4, penuh air, dan Marno kecemplung di kolam itu. Saat itulah, sabetan dan pukulan itu datang bertubi-tubi. Beberapa laki-laki masuk ke dalam kolam menghajarnya dengan kayu, besi, parang, pisau dan segala jenis senjata yang dibawa. Marno meraung, namun lukanya tetap bertambah, bertambah, terluka dan bertambah lagi. Hampir semua laki-laki yang memegang senter dan obor itu mengarahkannya ke kolam. Kolam ikan yang airnya keruh itu berubah menjadi merah kelam. Merah kelam. Dan beberapa waktu kemudian, tubuh Marno tak bergerak. Hanya diam di dalam air yang sudah berubah menjadi merah kelam itu.
Hingga pagi datang, tidak ada laki-laki yang meninggalkan tempat itu. Mereka duduk di pinggir kolam tanpa ada yang bersuara. Mereka merokok, hampir semuanya, dan ketika matahari terbit, mereka mematikan obor dan senter, tetapi tetap duduk di pinggir kolam itu tanpa bergerak. Hampir semuanya memandang ke kolam, terlihat kepala Marno bersandar di salah satu sisi kolam dan tubuhnya terendam air. Wajahnya sudah tak berbentuk, darah memenuhimya, mungkin hampir semua giginya rompal. Tapi tak ada yang bergerak untuk mengambil tubuh itu.
Ketika kemudian polisi datang dengan truk dan satu mobil patroli --yang ini aku melihat sendiri— sekitar jam 10 siang, semuanya tidak ada yang beranjak dari pinggir kolam itu. Terlihat wajah-wajah letih yang semalaman tidak tidur. Ada juga wajah yang menyesal, masih geram, dan ada yang terlihat lega. Semuanya kemudian mengumpulkan senjata masing-masing ke satu tempat, dan kembali duduk. Polisi kemudian memasang police line berwarna kuning –sebelumnya aku tak tahu untuk apa polisi memasang itu— dan kemudian salah seorang dari mereka, mungkin komandannya, berkata dengan suara berat. “Siapa yang bertanggung jawab dengan semua ini?”
Semua laki-laki di sana kemudian berdiri serentak. Beberapa saat kemudian, semua laki-laki yang berjumlah hampir 30 orang itu dinaikkan ke dalam truk dan dibawa pergi keluar dari desa itu. Mayat Marno yang sudah diangkat dari dalam kolam, dimasukkan ke dalam mobil ambulance yang datang kemudian. Katanya untuk diperiksa. Aku bingung, mengapa mayat harus diperiksa?
Di luar pagar rumah Marno, semua perempuan menangis, ibuku juga. Bapak ikut dalam barisan yang masuk ke dalam truk tersebut, dan aku ikut sedih, seperti ibu-ibu yang suaminya dibawa, juga anak-anaknya. Tetapi aku tidak menangis, dua adikku yang menangis. Sebelum masuk ke dalam truk, bapak mendekati ibuku dan mengatakan sesuatu yang tidak kudengar. Setelah itu keduanya memandang ke arahku. Aku, untuk pertama kalinya, berani membalas tatapan bapak. Aku tak tahu apa maknanya itu, tetapi paham bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk dari perlindungannya terhadap ibu dan kami, anak-anaknya, juga sebagai solidaritas warga kampung terhadap apa yang dilakukan Marno selama ini. Aku menyimpulkan hal itu beberapa tahun kemudian, ketika umurku bertambah dan aku sudah duduk di SMA. Ibu memeluk bapak. Bapak kemudian menggendong adik bungsuku, dan menciumnya. Aku melihat sekeliling, hampir semua laki-laki yang memiliki anak dan istri, melakukan hal yang sama.
Tiba-tiba, aku mendapati bapak sudah berada di dekatku. “Suatu saat, kamu akan paham mengapa kami harus melakukan ini. Ini cara laki-laki...” Bapak kemudian mengusap kepalaku beberapa kali, dan aku merasakan ada yang kosong dalam dadaku.
“Ya, Bapak.” Hanya itu yang keluar dari mulutku, dan aku tak melakukan gerakan apa-apa hingga kemudian bapak naik ke truk bak terbuka, juga semua laki-laki itu, dan kemudian dibawa keluar dari kampung.
Aku tidak tahu itu cara laki-laki. Yang aku tak paham, mengapa tak ada satupun yang melawan saat polisi datang, justru mereka malah dengan suka-rela mengumpulkan senjata dan kemudian bersama-sama naik ke atas truk, bahkan tanpa diborgol tangannya. Apakah karena polisi tak memiliki lebih dari 30 borgol? Atau ini sudah disepakati bersama bahwa mereka akan sama-sama menyerahkan diri kepada polisi setelah mereka menghabisi Marno? Apakah ini juga seperti yang disebut bapak, sebuah cara laki-laki? Aku benar-benar tak paham. Bahkan ketika kemudian truk yang membawa puluhan orang itu sudah hilang dari pandanganku, aku tetap masih belum paham dengan apa yang terjadi. Apakah memang pantas Marno menerim hukuman mati seperti itu? Bagaimana dengan nasib istri dan kedua anaknya? Siapa yang bertanggung jawab atas mereka? Mengapa untuk menyelesaikan persoalan seperti ini harus diselesaikan dengan kematian? Pikiran dan nalar kecilku tidak mampu mencerna itu semua. Kelak, ketika aku sudah bisa berpikir, akupun tak bisa menyadari bahwa “cara laki-laki” seperti yang dikatakan bapak itu adalah sebuah kebenaran. Namun, apalah arti sebuah kebenaran ketika rasa sakit itu sudah menghujam ulu hati?
“Tidak ada pembenaran untuk membunuh seseorang,” kata ibuku ketika aku sampai di rumah.
“Tetapi mengapa bapak juga ikut dalam pembunuhan itu?”
“Itulah laki-laki. Dunianya memang kadang tidak bisa dipahami. Kelak, jika kamu besar, mungkin juga kamu akan menjadi seperti itu, susah untuk dipahami...”
“Mengapa laki-laki susah dipahami, Mak?”
“Karena dia memiliki dunia sendiri yang terpisah dari perempuan...”
“Apa itu?”
“Laki-laki memiliki segalanya, sedang perempuan hanya memiliki laki-laki itu...”
“Saya tidak tahu maksudnya apa...”
“Kamu laki-laki, suatu saat kamu akan mengerti sendiri.”
Dan aku memang tak pernah memahami dunia laki-laki seperti apa. Bagiku dunia tidak ada yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan. Keduanya boleh bekerja, boleh bercinta dengan pasangan yang dipilihnya, boleh melakukan apapun selain merampok atau melakukan apapun yang dilarang oleh undang-undang karena itu merampas dan mengambil hak orang lain. Aku tak pernah membedakan dunia apapun, aku hanya menjalani apa yang harus kujalani.
Aku semakin tidak mengerti dengan dunia laki-laki dalam pikiran bapak ketika keesokan harinya setelah bapak dan teman-temannya diangkut polisi, aku mendengar kabar bahwa pemimpin gerakan untuk menghabisi Marno ini adalah bapak. Aku bertanya kepada ibuku tentang kebenaran hal itu, tetapi yang kudapati, ibu sudah menangis di sudut kamar sambil memeluk adikku yang paling kecil, Rizal. “Benarkah bapak yang merencanakan ini semua, Mak?” Aku memang tidak mengharapkan betul jawaban ibuku. Aku tak perlu jawaban itu, aku hanya ingin tahu kepastiannya, sebab ibukulah yang paling tahu siapa bapak sebenarnya.
Besoknya lagi, kami pergi ke Rengat, menjenguk bapak, bersama rombongan ibu-ibu yang suaminya ikut diangkut dalam truk setelah pembunuhan Marno. Ketika ibuku dan kedua adikku mendekati bapak, aku sengaja menjauh, hanya melihatnya sekali-kali. Aku tak bisa memahami perasaanku seperti apa. Aku hanya berpikir, jahatkah bapakku? Apakah laki-laki yang berusaha melindungi keluarga dan warga kampung, dianggap penjahat? Tetapi mengapa untuk melakukan semua itu harus menggerakkan warga untuk membunuh? Jahatkah bapak? Jahatkah laki-laki yang kini sedang menggendong Rizal, adikku yang paling kecil, di ruang bezuk itu?
Aku terkejut ketika bapak sudah berada dekat denganku. Dia duduk di sebelahku dan kami sama-sama memandang ke luar ruangan. Dia kemudian mengatakan bahwa aku harus membantu emak dalam mengurusi segalanya hingga saatnya nanti bapak keluar dari penjara. “Mungkin suatu saat nanti ketika Bapak keluar penjara, kamu sudah besar dan sudah dewasa. Itu bisa lima tahun atau malah lebih lama lagi. Suatu saat nanti, kalau kamu memang sudah benar-benar dewasa, kamu harus menjaga emak dan adik-adikmu. Ingatlah, itu pekerjaan laki-laki...”
Pekerjaan laki-laki itulah yang kemudian memang kulakukan. Setelah panen padi gogo di ladang di pinggir ladang, kami lebih konsentrasi pada kebun karet. Pagi aku tetap sekolah dan sorenya menyadap karet setelah paginya, dengan kemampuan yang terbatas, ibuku juga melakukannya. Barangkali inilah yang dikatakan bapak tentang pekerjaan laki-laki itu. Dan sampai akhirnya aku masuk SMA di Ukui dan harus pulang-pergi sejauh 15 kilo meter dengan sepeda, aku tetap menjalaninya. Saat itu, proses persidangan bapak dan teman-teman sudah hampir mencapai akhir. Tinggal 11 orang yang dinyatakan sebagai terdakwa dan diadili, sekitar 20 warga kampung dibebaskan karena mereka tidak melakukan eksekusi akhir terhadap Marno.
Merekalah yang kadang membantu anak-anak dan istri-istri yang dari 11 orang itu. Warga saling membantu dalam menghadapi kesulitan kami, kadang membantu menyadapkan karet kami, membantu mengambil lateksnya untuk dibekukan dan juga membantu mengangkutnya sampai ke rumah untuk ditimbang saat dijual. Kami memang merasa terbantu, dan di sinilah kami merasa menjadi senasib sepenanggungan. Tidak peduli mereka Jawa, Padang, Sunda, Teluk Kuantan atau Melayu, mereka bersama-sama mengatasi persoalan, termasuk mencarikan uang semir untuk para jaksa. Kepala kampung kami, Mardiaksa, memobilisasi warga untuk iuran setiap ada aba-aba dari jaksa, juga hakim, untuk meringankan tuntutan dan mungkin nanti putusannya.
Hampir tiap tiga hari sekali, aku dan emak menjenguk bapak di sel tahanan sebelum putusan pengadilan menjatuhi bapak hukuman paling berat di antara teman-temannya. Bapak harus masuk penjara selama dua tahun, sementara teman-temannya rata-rata satu tahun. Menurut hakim, tidak ada pelegalan pembunuhan, tetapi karena pertimbangan berbagai hal dan ini sifatnya sangat kolektif, termasuk penyerahan diri warga dan tindak-tanduk saat ditahan dan sebagainya, maka hukuman yang dianggap ringan itu diputuskan.
Ibuku menangis ketika itu, juga kedua adikku, Masri dan Rizal. Tetapi aku tidak, aku hanya diam dan tidak tahu perasaanku seperti apa. Jelas, aku merasa kehilangan, tetapi aku anak tertua dan saat ini sedang menuju proses dewasa. Aku ingin menjelaskan kepada bapak bahwa aku akan menjadi laki-laki seperti yang diinginkannya. Aku akan tegar, aku akan melakukan apapun untuk ibuku dan dua adikku. Aku akan bekerja keras untuk mereka selama bapak di penjara, aku ingin bertanggung jawab, karena itu salah satu pekerjaan laki-laki.
Aku menikmati semua tanggung jawab itu, tanpa harus meninggalkan sekolah. Aku ingin sekolah, dan tak ingin meninggalkannya meski bapak di penjara, dan banyak teman yang tahu tentang itu yang kemudian mengucilkanku dalam pergaulan di sekolah. Tetapi aku tak peduli, aku tetap sekolah dan melakukan kegiatan yang memang harus kulakukan.
“Bapaknya seorang pembunuh...”
“Iya, bapaknya yang memimpin warga desa untuk membunuh orang paling kaya di sana...”
“Mungkin bapaknya iri dengan kekayaan orang itu!”
“Atau bapaknya naksir dengan istri orang itu yang katanya masih sangat cantik meski sudah punya anak dua?”
“Mungkin juga, atau mungkin kedua-duanya. Ingin menguasai harta sekaligus istrinya!”
“Wah, itu namanya kemaruk, rakus!”
“Siapa yang tidak ingin punya istri cantik dan harta melimpah?”
“Lalu mau dikemanakan anak dan istri lamanya?”
“Kasihan dia ya...”
Aku mendengar semua pembicaraan teman-teman di sekolah itu, dan aku membiarkannya. Hatiku sakit, tetapi aku tak ingin memperlihatkan kepada semua orang. Bagiku, yang harus kulakukan adalah menyelesaikan sekolah. Mereka anak-anak orang kaya yang pergi ke sekolah memakai motor bagus dengan uang jajan yang sangat cukup, tapi aku tak peduli.
Namun besoknya, ketika salah seorang dari mereka bertanya padaku dengan mengejek, aku benar-benar tak bisa menerimanya.
“Benar bapakmu menginginkan harta dan istri cantik orang yang dibunuhnya?” tanya Fahrizal, teman sekelas yang memang selama ini terkenal usil.
Aku diam, menahan geram.
“Kamu malu mengatakannya?”
Aku bangkit dan kemudian dengan cepat memegang kerah bajunya dan tinjuku menghajar mulut dan hidungnya berkali-kali, sebelum kemudian dipisah teman-teman yang lain. Mungkin tulang hidungnya patah dan ada giginya yang juga patah. Dia dibawa ke puskesmas, dan aku disidang oleh majelis guru. Ketika mereka bertanya apa yang terjadi, aku menceritakan semuanya. Aku diskors seminggu, tetap masuk ke sekolah, tetapi tugasku adalah membersihkan WC guru, dan segala tingkah-lakuku akan dinilai dan dipantau terus-menerus.
Aku tidak dendam dengan Fahrizal, juga teman-teman lainnya. Yang selalu muncul dalam hati dan pikiranku, jahatkah bapak melakukan semua itu?
BAPAK menjadi orang asing bagiku saat keluar dari penjara. Meski aku sering mengantar ibuku membezuknya di penjara, tetapi aku benar-benar merasa asing. Bukan karena melihat wajahnya semakin tua dan ringkih, tetapi aku merasakan betapa aku selama ini seperti tak pernah mengenal bapak, lelaki yang membuatku ada dan terlahir ke dunia. Aku merasa ada sekat, ada jarak, bahkan dinding yang menghalangi kami untuk dekat, atau aku yang mendekatkan diri. Aku ingin membuang jarak itu, menembus dinding itu, mengoyak sekat itu, tetapi aku tetap merasa jauh, merasa ada yang membuat aku harus selalu menjauhinya.
Ketika secara resmi bebas keluar, kami menjemputnya di LP dan kemudian sama-sama pulang naik angkutan pedesaan menuju rumah kami. Tak ada yang berubah dari rumah kami selama bapak berada di penjara. Aku tak memiliki kekuatan apa-apa untuk melakukan perubahan-perubahan, sebab waktuku habis di sekolah dan mengelola kebun bersama emak dan Masri yang sudah mulai masuk SMP. Tapi bapak mengatakan senang bisa bersama kami lagi di rumah.
“Bapak berterima kasih kepada kalian semua yang tetap bertahan meski Bapak selama dua tahun ini tidak bersama kalian. Meninggalkan rumah dalam waktu lama tanpa memberikan apapun, bukan hal yang baik bagi seorang laki-laki. Tetapi mempertahankan harga diri adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki tidak boleh lembek, dia harus kuat, tegas, keras dan kalau memang perlu harus kasar dalam menghadapi hidup!”
“Ya, Bapak.”
“Dan mulai hari ini, Bapak akan berada lagi di antara kalian. Tapi Bapak sudah semakin tua dan ringkih, tidak sekuat dulu. Di penjara tidak seperti di rumah. Di sini, kita bisa ke ladang, menebang kayu, menyangkul, menyadap karet, mengangkut getah dan semuanya yang membuat otot-otot kita terlatih dan kuat. Di penjara, tidak ada pekerjaan itu sehingga otot-otot Bapak mulai mengendur. Mungkin juga karena usia. Kalian bertiga laki-laki, harus benar-benar menjadi laki-laki...”
Aku tahu, bapak sangat mencintai kami, anak-anaknya, juga ibuku. Aku paham itu, dan merasakan itu. Mungkin, kekerasan hidupnya yang membuat dia mencurahkan segala perasaan cinta dan sayangnya itu, dengan cara yang keras juga. Tetapi, aku juga paham, bahwa tetap ada jarak di antara kami, jarak yang sangat tidak kupahami apa sebabnya.
Mungkin sama tak kupahami ketika tiba-tiba malam dan hujan selalu menjadi hal yang membuat ganjil dalam kehidupanku. Malam dan hujan, suasana yang kemudian sangat kurindukan, sekaligus menakutkanku. Mungkin berawal dari kejadian itu.
Aku pergi ke hutan karet saat hujan lebat dan petir menyambar-nyambar untuk mengangkut getah yang beku, bau dan masih basah itu. Malam nanti touke getah akan menimbangnya dan getah itu sudah harus ada di rumah sebelum malam.
“Tapi hujan deras sekali, Bapak...” kataku mencoba menawar kepada bapak. Itulah barangkali untuk pertama kalinya aku mengucapkan kata yang tidak cocok dengan keinginan bapak.
“Kau tak akan mati oleh hujan.”
Dan aku kemudian berlari ke belakang rumah, mengikuti jalan setapak yang masuk ke belukar di hutan karet yang sudah tua dan tidak terawat itu. Aku memang masih sangat remaja ketika itu, belum tamat SMA, dan meskipun ketika bapak di penjara, aku telah melakukan segalanya, tetapi kini benar-benar hujan yang menakutkan bagiku. Dan aku harus menapak pada jalan licin menurun dan mendaki untuk sampai ke rawa di mana getah bacin itu berada. Getah itu sudah dicetak menjadi bantalan dan ditenggelamkan di lumpur yang berair untuk menjaga kadar airnya yang akan mempengaruhi timbangan, dan aku harus mengangkatnya satu persatu sejauh hampir 400 meter dengan pundak atau punggungku sampai di belakang rumah. Ibuku menangis menyaksikan itu dan dua adikku hanya memandang sedih dari dapur rumah kayu ketika dalam hujan yang lebat aku bekerja keras. Masri keluar rumah dan akan membantu, tetapi kukatakan kepadanya bahwa aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak tega melihat Masri yang masih kelas satu SMP itu harus membantuku dalam hujan seperti ini. Aku ingin mengatakan kepada bapak bahwa aku bisa menjadi laki-laki seperti yang sering dia katakan, meski aku juga tak tahu apa bentuk laki-laki seperti yang diinginkannya itu.
“Biar dia belajar bertanggung jawab sebagai lelaki,” kata bapak kepada ibuku, sempat terdengar di telingaku.
Aku berjanji tidak akan dendam dengan semua itu, meski hatiku perih dan air mataku mengalir, bersatu dengan air hujan yang deras. Tapi cepat-cepat aku menghapuskannya, sebab kata bapak, laki-laki tak boleh menangis. Aku mencoba menghibur diriku dan meyakinkannya, apa yang kulakukan ini adalah karena aku anak lelaki pertama dan sebab bapak sudah mulai ringkih, terlihat tua sebelum waktunya karena beban hidup dan tembakau yang membuatnya selalu terbatuk sejak keluar dari penjara.
Hujan benar-benar semakin deras dan senja sudah hampir penghujung, dan bantalan getah bacin itu masih beberapa yang belum kuangkat. Aku sudah menggigil ketika itu dan tenagaku sudah semakin lemah...
Hingga kemudian ketika bantalan bacin basah itu tinggal satu, aku benar-benar tidak memiliki tenaga dan hari sudah benar-benar gelap. Aku tetap mengangkatnya dan harus berjalan di pendakian yang licin, sementara kakiku tanpa sepatu, hanya telanjang dan menggigil. Dan tiba-tiba, ketika aku merasakan tenagaku benar-benar habis, aku terpeleset, bantalan bacin itu menimpa tubuhku yang telanjang tanpa baju dan aku bergulingan hingga sebatang pohon karet menahan tubuhku. Rasanya sakit sekali, tetapi aku akan minta tolong kepada siapa? Aku ingin berteriak tetapi suaraku tak keluar. Aku akhirnya benar-benar kedinginan, juga kesakitan, dan menggigil seperti berada di dalam bongkahan es, sebelum bapak datang dan menemukanku, dan setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di rumah dan mendapati ibu dan kedua adikku menangis di dekatku. Mungkin aku pingsan tadi, dan badanku masih terasa sakit di sana-sini.
Tidak, aku tidak dendam dengan masa lalu itu. Hingga kemudian setelah tamat SMA aku memilih pamit pada bapak, ibu dan dua adikku untuk pergi jauh mengembara. Aku merasa dan berharap dunia di luar kebun karet itu memberikan harapan-harapan dan pengalaman hidup yang lebih baik.
“Biarlah dia pergi, laki-laki harus punya pengalaman hidup untuk menguatkannya,” kata bapak kepada ibuku yang sempat terdengar olehku ketika langkahku menyeberang pintu.
“Tapi di sini adalah rumahnya. Sejak kecil dia di sini, dan di luar sana dia akan tinggal dengan siapa?” aku masih mendengar ibuku menangis. “Saya mohon, tahanlah dia, dia belum bisa berdiri sendiri, dia masih membutuhkan kita...” ibuku memohon.
Tapi kudengar jawaban bapak: “Dia laki-laki, dan dia akan menentukan jalannya sendiri. Itu pilihannya...”
“Tapi dia memilih itu karena dia merasa tidak mampu lagi hidup dengan caramu...” Baru kali ini aku mendengar ibuku melawan apa yang dikatakan bapak.
“Suatu saat dia akan kembali, jika dia memang tidak mampu. Dia tahu jalan pulang ke rumah ini, meskipun dia keluar kampung malam gelap dan hujan seperti ini...”
Aku tidak tahu apa yang terjadi di kamar itu, tetapi aku mendengar, baru sekali inilah suara bapak bergetar, tidak seperti suara-suara tegas yang kudengar selama ini. Apakah bapak menangis? Menangisi kepergianku? Tidak, bapak tidak akan menangisi aku. Tetapi aku kemudian benar-benar pergi saat hujan dan malam gelap itu. Meninggalkan kampung, rumah kayu, hutan karet, bau bacin dan segala kenangan tentang masa kecil dan remajaku.
Aku kembali ke kampung beberapa tahun kemudian setelah aku merasa berhasil setelah menamatkan kuliahku dalam pelarianku di Pekanbaru. Ingin mengatakan kepada bapak bahwa aku telah benar-benar menjadi laki-laki, mungkin yang seperti inilah yang diinginkan bapak. Aku sudah merasa menjadi kuat, tetapi aku mendapati bapak sangat ringkih, terbatuk-batuk dan sudah sangat susah untuk berjalan. Sudah terlihat sangat tua, sangat sepuh, jauh lebih tua dari umur sebenarnya. Hilang segala kesombongan yang kubawa dari kota melihat bapak seperti itu. Bapak mengatakan kepadaku, bahwa sejak aku pergi, ladang karet itu tak terawat, meskipun tetap diambil getahnya oleh ibuku dan dua adikku yang sudah mulai remaja. Masri sudah hampir tamat SMA, sedang Rizal sudah hampir tamat SD. Terasa semuanya menjadi perih di hatiku. Aku membayangkan bagaimana perjuangan ibuku dan dua adikku untuk bisa mendapatkan uang dengan menakik getah. Aku menangis dan memeluk bapak. Aku tetap mengatakan bahwa aku tak dendam dengan masa lalu, terhadap kekerasan hidup yang harus kualami, juga saat malam dan hujan itu. Aku hanya membayangkan bagaimana pedihnya ibuku dan dua adikku sepeninggalanku, mereka harus bekerja keras ketika bapak benar-benar sudah tidak bisa bekerja lagi. Apakah penjara selama dua tahun telah menghancurkan semua energi dan kekuatannya?
Aku benar-benar menangis. Dan sejak itu, aku berjanji kepada mereka bahwa aku akan ada ketika mereka membutuhkan aku. Aku tak akan meninggalkan mereka lagi. Tetapi, perjalanan kemudian membawaku ke negri jauh. Aku meninggalkan mereka, meninggalkan masa laluku, meninggalkan semua cerita yang pernah hidup dan menjadi seluruh muara dari semua apa yang kulakukan hari-hari ini. Aku telah mengingkari janjiku untuk membantu membebaskan warga kampungku dari cengkraman perusahaan sawit itu. Aku malah menjadi pelarian untuk sesuatu yang menurutku juga sebuah perjuangan tersendiri. Tetapi, aku benar-benar telah mengingkari janjiku pada ibuku, dua adikku dan penduduk kampung yang mungkin hingga kini masih sering mendapat teror dari orang-orang suruhan perusahaan sawit itu...
Bagian IV
DIA terkejut ketika sampai di rumah saat senja menjelang. Sudah lima tahun dia tak pulang. Selama itu dia berusaha sekuat tenaga melawan semua perasaan rindu pada ibunya, Zulmasri dan Rizaldi, dua adiknya –juga pada bapaknya. Selama lima tahun dia tak mengirimkan kabar apa-apa, juga tak mendapat kabar apa-apa tentang kampung dan keluarganya. Dia tak ingin menjadi cengeng. Ketika dia keluar rumah, keluar kampung dan ingin keluar dari masa lalu, di malam yang gelap dan hujan itu, dia sudah bertekad untuk tidak pulang dan tidak memberikan kabar apapun sebelum dia mendapatkan sesuatu yang bisa dibawanya ke depan bapaknya. Awalnya, dia tidak tahu apa sesuatu tersebut, tetapi dia ingin mengatakan bahwa dia bisa hidup, bediri tegak di kaki sendiri selama dia jauh dari rumah.
Dia ingat malam itu. Dalam hujan lebat dan gelap, dia berjalan kaki keluar dari kampung. Jalanan licin, kilat petir yang saling bersahutan, membuat dia bisa melihat jalanan yang licin karena berlumpur. Itu pun dia sering terjatuh karena terpeleset. Namun, dia tak peduli. Dia harus sampai di jalan raya yang berjarak 15 kilometer dari kampungnya yang tak tersentuh listrik tersebut. Dia tak bertemu satu orangpun selama di jalan, apalagi kendaraan. Ketika dia melewati hutan lebat dan kebun sawit atau karet yang sepi, teringat di kepalanya tentang harimau dan binatang buas lainnya yang kabarnya masih sering ada di sana. Tetapi dia tak peduli.
Hampir tengah malam dia sampai di pinggir Lintas Sumatera. Seluruh pakaian dan badannya basah. Tas ransel yang berisi pakaian dan ijazahnya juga basah. Dia menunggu kendaraan yang lewat ke arah Pekanbaru. Dia tak pernah ke Pekanbaru, tetapi dia tahu arah ke sana. Setelah berjam-jam menunggu, sebuah truk yang dia tak peduli sedang mengangkut apa, bersedia membawanya setelah sekian bus atau truk yang berusaha dihentikannya tak mau memberi tumpangan kepadanya.
Dia sampai di Pekanbaru pagi hari. Sopir truk yang belakangan diketahui bernama Alo, bertanya tujuannya apa ke Pekanbaru. Dia menjawab tak tahu, yang penting baginya keluar dari kampungnya dan mau kerja apa saja asal bisa makan. Sesampai di Pekanbaru, dia bingung mau turun di mana. Ketika sampai di Harapan Raya, Alo bertanya lagi, dia mau turun di mana. Dia menjawab tidak tahu. Alo kemudian menawarkan dia untuk sementara tinggal di rumah petaknya di kawasan Sail. Dia bersyukur ketika itu dan ingin rasanya menangis menerima kebaikan Alo, lelaki tinggi besar berkulit legam itu. Alo juga yang kemudian mengajaknya ikut truk yang dikendarainya, kebetulan stokar dia sudah seminggu tidak ada kabar beritanya. Dia merasa, Tuhan kembali menolongnya. Akhirnya, selama dua bulan lebih dia tunggal di rumah Alo yang sempit dan bekerja bersama Alo mencari kelapa sampai ke Pariaman atau Indragiri Hilir untuk dijual ke Pekanbaru dan beberapa kota lainnya. Selama dua bulan itu, Alo memberi kesempatan kepadanya untuk belajar nyetir. “Rugi kamu kerja di mobil tapi tak pandai nyetir. Kamu harus bisa, modalnya nekad saja,” kata Alo suatu ketika.
Dia kemudian belajar nyetir dan dalam waktu yang tidak lama, dia sudah bisa mengganti Alo ketika perjalanan mau atau dari Pariaman atau daerah lain penghasil kelapa di Sumbar, atau dari Inhil. Dia bersyukur. Dia pernah mendengar cerita tentang orang-orang kampung yang pergi ke kota dan kemudian menjadi gelandang atau gembel di sana. Tapi nasibnya agaknya lebih baik karena dia tidak harus melalui fase itu, meski dia memang harus bekerja keras untuk bisa hidup. “Iman, orang-orang seperti kita ini tidak memiliki pilihan apa-apa. Aku sudah dari dulu ingin berhenti jadi supir, mencari pekerjaan yang layaklah, entah jadi apa begitu. Tapi, setelah keluar-masuk di pekerjaan mulai dari buruh sawit dan pekerjaan lainnya, akhirnya larinya juga ke mobil, nyopir. Sejak itu aku tak banyak berharap. Alhamdullillah, dengan pekerjaan ini keluargaku tetap makan dan aku tetap bisa tenang di jalan...”
“Terima kasih, Abang sudah banyak menolong saya. Saya tidak tahu harus bagaimana membalasnya,” katanya ketika itu.
“Iman, ketika masih remaja dulu, ketika lulus SMP dan tak bisa melanjutkan ke SMA karena tak punya duit, aku mengutuk mengapa dilahirkan menjadi orang miskin, mengapa bapak dan emakku tidak menjadi kaya seperti orang-orang lainnya. Tapi kemudian aku berpikir lagi, bahwa nasib orang itu berbeda-beda. Tetapi, bapakku pernah mengatakan kepadaku bahwa tetaplah baik kepada semua orang, tolonglah semampu kita kalau orang itu kesusahan. Sebab, kata bapakku, dengan menolong orang itu, Tuhan akan mengingat kita. Kalau kita kena kesusahan, mungkin bukan orang yang kita tolong itu yang akan menolong kita, tetapi Tuhan akan menggunakan tangan orang lain untuk menolong kita. Dan benar, Iman, selama aku kerja di mobil, aku bersyukur saat kesusahan, selalau saja ada orang yang menolongku. Itu makanya aku ingin sekali membantumu malam itu...” kata lelaki bermana asli Zulfikar ini.
Dia ingin menangis saat itu juga mendengar apa yang dikatakan Alo, lelaki kelahiran Magek (Bukittinggi) itu. Dia berjanji di dalam hati, dia akan balas semua kebaikan Alo suatu saat kalau hidupnya mujur.
Di bulan ketiganya di Pekanbaru, seorang kenalan Alo datang kepada Alo. Katanya dia sedang mencari seorang yang bisa bekerja di tokonya, sebuah toko penjual peralatan tulis, fotokopi dan penjilidan, di Panam. Alo kemudian menawarkan Iman. “Dia memang belum kenal mesin fotokopi atau menjilid. Tetapi aku yakin dia cepat bisa, selama bekerja denganku dia sangat rajin...”
Dari sinilah jalannya mulai terkuak. Dia tinggal dan sekaligus menjaga toko itu, berkenalan dengan banyak mahasiswa dan banyak orang pintar. Dia kemudian bertanya kepada Agustiar, pemilik toko buku kecil dan fotokopi itu, bagaimana caranya untuk bisa kuliah. Mulanya, Agustiar tersenyum mendengar apa yang ditanyakan Iman itu. “Tapi kalau kamu memang ingin kuliah, tahun depan coba ikut tes. Kamu masih bisa kerja di sini sepulang kuliah, juga masih boleh tinggal di sini...”
“Terima kasih, Pak...”
“Aku suka melihat lelaki pekerja keras sepertimu. Hidup ini yang penting semangat, Iman. Dengan semangat itulah kita bisa melakukan apa saja...”
“Ya, Pak...”
Iman merasa Tuhan memang telah mempertemukannya dengan orang-orang baik. Sejak itu, dia benar-benar serius ingin kuliah. Seluruh upah yang didapatkannya dari Agustiar dikumpulkannya dan dia benar-benar hidup hanya untuk bekerja di toko itu. Dia tak peduli apapun, yang penting bisa kuliah. Dan benar, dia kemudian lulus UMPTN dan diterima di jurusan Sosiologi di Unri. Selama kuliah, yang ada di pikirannya adalah membaca buku di pustaka, kuliah dan bekerja di toko Agustiar. Tak ada pikiran lain. Dia tahu, banyak gadis cantik dan borjuis yang suka padanya. Tetapi dia tahu, setelah mereka tahu latar kehidupannya seperti apa, mereka akan mundur dan bukan tidak mungkin malah akan mempermalukan dirinya sendiri. Untuk itu, dia tak pernah ingin dekat dengan salah satu dari sekian gadis, teman di jurusan maupun fakultasnya, atau mereka yang sengaja selalu memfotokopi di toko Agustiar. Kadang-kadang, muncul juga dalam pikirannya untuk mencoba bagaimana rasanya pacaran, seperti pemuda normal lainnya, tetapi kembali pikiran awalnya muncul. Mereka gadis kota dan borjuis, meskipun mereka akan mengatakan mau menjadi kekasihnya dengan apa adanya, tetapi dia tak mau membuat gadis itu malu punya pacar dirinya.
Dia ingin cepat selesai kuliah dan kemudian kembali ke kampungnya untuk mengatakan kepada bapaknya bahwa dia bisa kuliah dan menjadi sarjana. Dan akhirnya, waktu itu datang juga ketika dia benar-benar menjadi sarjana. Dia tidak ikut wisuda karena tak mampu membayar biaya wisuda. Dia hanya punya uang untuk membayar pengambilan ijazah, dan setelah itu dia pamitan dengan Agustiar bahwa dia akan pulang ke Ukui.
“Di Pekanbaru ini, Bapak adalah orang tua saya. Saya hidup, makan dan tidur di sini. Pekerjaan saya selama ini tidak sebanding dengan apa yang Bapak berikan kepada saya. Bapak telah memberikan kepercayaan, kehidupan dan kemuliaan. Saya sangat berterima kasih, semoga Tuhan akan memberi segala kebaikan kepada Bapak dan seluruh keluarga...” Dia menangis hari itu. Dia tahu, laki-laki tidak boleh menangis, tetapi dia benar-benar ingin menangis ketika itu dan memeluk Agustiar, juga istri dan dua anaknya yang usianya masih di bawah dia.
“Iman, sekarang kamu sudah menjadi orang, menjadi sarjana. Meskipun kamu tidak pernah bercerita apapun tentang keluargamu, tetapi aku tahu, kamu pasti punya keluarga. Dan aku juga tahu kamu ingin pulang dan menjelaskan kepada keluargamu tentang keberhasilanmu ini. Jika kamu pulang, katakan kepada bapak dan ibumu, juga kakak-adikmu, kami sekeluarga titip salam. Ingatlah, yang kamu miliki selama ini adalah kejujuran. Jangan buang kejujuran yang membuat orang percaya kepadamu itu dari hati dan dirimu. Percayalah, hanya kejujuran itu yang bisa membuat orang berhasil dan dihormati orang lain...”
Iman benar-benar menangis dan meninggalkan toko itu dengan air mata. Dia ingat bagaimana kebaikan orang-orang di Pekanbaru, Alo dan Agustiar. Dia mampir ke rumah kontrakan Alo di Sail dan berjanji suatu saat akan kembali ke Pekanbaru dan membalas semua kebaikan Alo. “Tetapi saat ini yang saya pikirkan adalah pulang, Bang. Sudah lima tahun saya tidak pulang, tak menengok bapak dan emak, juga adik-adik...”
Alo, lelaki tinggi besar dan bekulit legam itu, tak bisa menahan sedihnya. “Iman, Tuhan ternyata menunjukkan dan membimbingkan jalanmu....”
“Terima kasih, Bang...”
Dia kemudian pulang, naik bus ke arah selatan, arah kedatangannya lima tahun yang lalu ketika dia berpikir bahwa ada banyak harapan dan impian di luar kebun karet dan rumah papan keluarganya. Dan kini dia pulang dengan membawa salah satu impian dan harapannya itu: menjadi seorang sarjana, sebuah titel yang tidak gampang didapatkan oleh anak-anak di kampung, dan dia mungkin akan menjadi sarjana pertama dari kampungnya itu. Dia tidak lagi orang bodoh, dia akan menjadi orang terpandang. Paling tidak, penduduk kampung pasti akan banyak bertanya kepadanya, minimal tentang pengalamannya selama di kota, juga pandangan-pandangannya. Tapi dia tidak membutuhkan semua itu, dia tidak ingin dihargai orang. Dia hanya ingin bapaknya tahu, bahwa betul ada harapan dan impian di luar kebun karet mereka, di luar rumah papan mereka. Dan kini, dia sudah mendapatkan salah satu dari itu.
DIA masuk rumah, dan yang didapatinya adalah ayahnya yang di matanya sudah sangat kelihatan ringkih, sangat tua, sedang terbujur lunglai di dipan. Keduanya bertatapan, seperti kawan lama yang sudah tidak bertemu sekian tahun. Kawan lama? Ya, mereka sesungguhnya kawan lama, kawan yang bahu-membahu berjuang untuk keluarga ini, bahkan sejak dia masih kecil, sering diajak tidur di tengah ladang padi menjaga hama babi. Ya, mereka telah lama menjadi teman, meski selama ini komunikasi yang terjadi hanya satu arah, dari laki-laki yang kini terbujur lunglai di dipan itu. Bapaknya.
Dia tidak mendapati ibunya, Masri dan Rizaldi. “Mereka sedang menakik getah di belakang...” suara bapaknya terdengar seolah tahu ada pertanyaan di benaknya tentang mereka. “Masri tahun ini akan tamat SMA, dan Rizal akan masuk SMP lagi. Syukurlah, akhirnya kamu pulang, ada lagi yang membantu mereka untuk merawat kebun dan mengambil getah karet itu...”
“Ya, Pak...” hanya itu yang keluar dari mulutnya. Dia membayangkan bagaimana perjuangan ibunya dan dua adiknya sepeninggalannya. Membayangkan seandainya mengalami malam yang buruk seperti yang menimpanya saat dia tidak mampu lagi mengangkat bantalan getah untuk yang kesekian kalinya di malam hujan dan petir menyambar itu. Dia teringat bagaimana kemudian benda yang sudah berada di pundaknya seberat hampi 50 kilogram itu kemudian menimpa tubuhnya yang terpeleset dan membuatnya tergelincir sebelum batang karet menahan tubuhnya, setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi karena yang dia rasakan hanya gelap. Hanya gelap. Dan dingin. Dan beku.
“Apa yang ingin kamu katakan kepadaku setelah hampir lima tahun kamu pergi tanpa kabar? Ibumu selalu merisaukanmu, tetapi aku selalu mengatakan bahwa kamu laki-laki, dunia di luar sana bisa dikalahkan oleh laki-laki...”
“Ya, Pak...”
“Kamu bisa bercerita, Iman...”
Dia mendongak. Dia ingin bapaknya mengulang lagi kata-kata terakhirnya. Tak pernah selama ini bapaknya menyebut namanya, dan dia merasa kalimat itu terasa indah dan menyejukkannya.
“Kamu bisa menceritakan apa saja, mungkin tentang perasaan sakit hati dan dendammu kepada bapakmu ini...”
Dia mendekat ke dipan, menarik kursi kayu lusuh yang sejak tadi dijadikannya sebagai tempat duduk. Dipegangnya tangan bapaknya yang sudah benar-benar ringkih, tinggal terasa tulangnya saja. Dia teringat bagaimana kerasnya laki-laki ini dalam mendidiknya. Kadang dia lupa bahwa apa yang dikatakan lelaki ini sebenarnya ungkapan dari rasa sayangnya. Atau, memang semua laki-laki akan melakukan hal seperti itu untuk mewujudkan perasaan sayangnya kepada anak-anaknya nanti? Tetapi, bukankah yang dia lihat di film atau televisi dalam cerita-cerita itu, ungkapan kasih sayang seorang ayah selalu dilakukan dengan ciuman dan perhatian, bukan bentakan-bentakan dan kata-kata nasihat yang terasa sebagai ancaman? Namun dia kemudian sadar, bahwa apa yang dilakukan bapaknya itu ternyata telah membuat dia begitu kuat dalam menghadapi semua apa yang harus dilaluinya. Semua yang dilaluinya berat, dan dia bersyukur, sejak kecil dia sudah mengalami kehidupan yang berat sehingga dia bisa memahami semuanya. Bahwa, bapaknya sepertinya sudah mempersiapkan dia untuk bisa memikul keberatan itu dan melewatinya dengan baik.
Menjelang senja hampir benar-benar habis, ibu, Masri dan Rizal pulang. Yang pertama dilihatnya adalah ibunya. Dia melihat ada perubahan signifikan di raut wajah wanita yang sangat dia hormati itu. Dia tahu, dulu ibunya sangat cantik, dan meskipun guratan kecantikan itu masih tersisa di wajahnya, namun kerut ketuaan sudah mulai menyerangnya. Lima tahun dia tak melihatnya, dan selama itu pula dia tidak memberi kabar apa-apa dan saat ini dia benar-benar ingin menangis dan minta maaf. Dia kemudian memeluk ibunya yang masih bau getah itu. Dia tidak peduli. “Ampunkan saya, Emak. Ampunkan saya...” dia menangis, benar-benar menangis, meskipun dia tahu –seperti ajaran bapaknya— bahwa laki-laki tidak boleh menangis, seberat apapun deritanya.
Ibunya juga memeluknya dengan erat. “Syukurlah kamu benar-benar ingat jalan pulang. Lihatlah dua adikmu, mereka sudah besar-besar. Merekalah yang menjadi penggantimu ketika bapakmu tak bisa bekerja lagi...”
Dia kemudian memeluk Masri dan Rizal bersamaan dan mengatakan bahwa dia sebenarnya tak ingin meninggalkan kampung ini waktu itu. “Kalian sudah besar, nanti kalian akan tahu kenapa Abang harus pergi ketika itu...”
“Saya bisa paham, Bang. Tetapi sejak Abang pergi, bapak sering sakit-sakitan dan kemudian benar-benar sakit dan kami tak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya ingin mencari Abang ketika itu, tetapi Bapak melarangnya. Katanya, adalah tugas kami yang tinggal di sini untuk bekerja dan bertanggung jawab dan Abang pasti memiliki jalan lain yang memang sudah Abang pilih...”
“Abang sudah jadi sarjana, Masri. Abang bekerja keras untuk mendapatkan itu...”
“Betulkah?”
“Ya...”
“Tapi keadaan di sini semakin buruk, Bang.”
“Ada apa?”
“Pemilik perkebunan sawit yang akan mengembangkan perkebunannya di sini, sejak setahun lalu sudah mulai meneror warga...”
Malamnya dia pergi ke mushalla, bertemu dengan teman-teman sepermainannya dulu. Mereka bercerita banyak hal, juga tentang apa yang terjadi terhadap kampungnya sejak setahun lalu ketika perusahaan sawit itu masuk dan mengatakan bahwa kampung ini tidak ada dalam peta yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan, tempat mereka mendapat izin konsesi pengembangan perkebunan. “Katanya, dalam peta itu, kampung ini masih hutan dan tidak berpenduduk. Itu makanya mereka merasa memiliki kekuatan untuk mengusir kita dari kampung ini,” cerita Zamzami.
“Mengusir kita? Semudah itu?”
“Ya. Kata mereka, pemerintah akan berpihak kepada mereka kalau terjadi sengketa. Bapakmu menjadi orang pertama yang menentang itu, dan kemudian membuat kami di sini yakin bahwa akan ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini...”
Bapakku..., dia lelaki pemberani.
“Lalu apa yang telah kita lakukan selama setahun ini?”
“Kami sudah mengadu sampai ke kantor camat di Ukui. Pak Camat berjanji akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Kabarnya, masalah ini sudah sampai ke kabupaten dan pihak kabupaten sedang mempelajari akar masalahnya...” kata Matdadi, salah seorang teman sebayanya.
“Jangan percaya dengan pegawai pemerintah. Mereka banyak makan uang perusahaan. Itu sudah sering terjadi, perusahaan apapun yang masuk ke suatu daerah, menyetor uang sebagai pelicin dan sebagai gantinya mereka mendapatkan segala kemudahan untuk mendapatkan itu semua...”
“Lalu apa yang harus kita lakukan lagi?”
“Kita harus menjadi sebuah kesatuan yang kuat. Seluruh penduduk kampung harus bersama-sama dalam keadaan apapun, dan kita harus bekerja keras untuk menekan pihak kecamatan dan kabupaten bahwa ini adalah tanah kita, hak kita, hak sebagai masyarakat, hak sebagai rakyat. Tidak ada alasan apapun bagi pihak di luar yang mengklaim ini tanah mereka, meskipun di peta kampung kita ini tidak tercantum. Peta itu dibuat oleh orang-orang yang tidak memahami persoalan masyarakat. Ini juga semakin menjelaskan bahwa camat, bupati maupun gubernur, tidak pernah mempedulikan nasib kita, masyarakatnya. Kalau mereka peduli, mereka tidak akan membuat peta yang menghapuskan perkampungan...”
Dia menjadi heran. Selama ini di kampus dia hanya membaca buku-buku gerakan, tentang teorinya maupun studi kasus gerakan sosial di beberapa tempat di Indonesia maupun di dunia. Dia membaca Pemberontakan Petani Banten yang ditulis Sartono Kartodirdjo, buku-buku tentang gerakan petani yang ditulis James C Scott, Karl J Pelzer, Jan Breman, maupun kisah pemberontakan petani yang sangat gagah dan heroik di Meksiko, yakni Zapatista, juga teori-teori gerakan dari Karl Marx sampai teori sosialnya Levis Straus, Freud dan lain sebagainya. Dia juga membaca novel yang membius, yakni De Opstand van Guadalajara yang ditulis J Slauerhoff, novel Hadji Murat-nya Leo Tolstoy atau Kantarapura-nya Raja Rao dan sekian buku gerakan lainnya. Namun itu semua hanya teori, dan kini, persoalan benar-benar muncul di depan matanya, di masyarakatnya, di hidupnya. Dan latarnya berbeda dengan cerita-cerita pemberontakan dan pergerakan sosial di buku-buku yang dia baca itu, meski pada dasarnya semua gerakan itu berawal dari satu hal yang sama: ketidakadilan karena kepemilikan yang sah sebagai hak, akan direnggutkan dan direbut oleh kekuatan yang dilegitimasi oleh kekuasaan.
Dia berjanji dalam hati, inilah saatnya baginya untuk mengatakan kepada bapaknya bahwa dia laki-laki yang kuat yang juga punya pikiran. Dengan sedikit pengetahuan yang dimilikinya, dia ingin membantu warga untuk keluar dari masalah ini. Dia kemudian mengajak para pemuda sebayanya untuk datang ke rumah Kyai Abdullah, meminta masukan dari tokoh agama itu tentang masalah yang kini muncul di kampungnya. Menurut imam di mushalla dan guru ngaji itu, adalah hak umat untuk mempertahankan apa yang dimilikinya dari rongrongan orang lain. Dan untuk mempertahankan itu, sudah menjadi sebuah kewajiban dan agama mengharuskan kita mempertahankan hak yang kita miliki secara sah menurut agama.
“Apakah tanah yang kita tempati sekarang, meskipun kita tidak membelinya dari siapapun, tetapi orang-orang tua kami dulu yang membuka hutannya, adalah hak kita secara Islam, Kyai?” tanyanya saat selesai sholat Isya.
“Kita harus menjadikan apa yang dilakukan oleh nabi kita, Muhammad SAW, sebagai patokan kita dalam menilai sesuatu. Tanah ini adalah milik negara ini, dan pemilik negara ini adalah rakyat seperti kita-kita ini. Memang, dalam sebuah negara harus ada peraturan dan undang-undang agar penyelenggaraan negara menjadi tertib dan menyeluruh. Tetapi, negara juga tidak bisa menghilangkan hak-hak dasar masyarakat, termasuk dalam hal kepemilikan tanah. Kita yang membuka hutan dan telah menempatinya hampir 30 tahun, dan selama ini pemerintah dari tingkat kecamatan sampai kabupaten tidak pernah mempermasalahkannya, artinya memang tidak ada masalah. Lalu, ketika ada perusahaan sawit ingin masuk dan menguasainya, tentu kita harus mempertahankannya...”
Dia kemudian mengatakan kepada bapaknya, bahwa dia akan memimpin para pemuda di kampungnya untuk mempertahankan tanah mereka. Bapaknya, yang terbaring lemah di dipan, tersenyum mendengar itu. “Itulah laki-laki, dia harus melindungi keluarga dan masyarakatnya...” kata bapaknya. Kadang dia bosan mendengar kalimat itu, yang selalu diulang-ulang oleh bapaknya.
Setiap hari, dia pergi ke ladang karet, membersihkan semak-semak, memperbaiki jalan setapak, ikut menakik getah dan mengumpulkan lateks untuk dijadikan bantalan dan direndam di air. Sorenya dia tetap bermain sepakbola bersama teman-temannya dulu. Dan malamnya dia ke mushalla, ketemu dengan Kyai Abdullah dan teman-temannya untuk membicarakan apa yang terjadi dengan kampungnya. “Satu hal yang harus kita lakukan adalah bernegosiasi dengan perusahaan itu dulu, Kyai,” katanya setelah mereka selesai shalat Isya.
“Ya, saya setuju itu. Kita harus bicara baik-baik dulu dengan mereka dan berupaya mencarikan jalan keluarnya,” kata Kyai Abdullah.
“Kita telah melakukan itu sejak lama, Kyai. Bapak Iman sampai sakit seperti itu juga karena selalu harus pulang malam untuk bernegosiasi di Ukui maupun di Rengat. Dan selama ini hasilnya apa? Bapakmu sering mereka buat takut, Iman...” kata Zamzami.
“Tapi kita harus memulainya lagi. Setelah jalan itu buntu, misalnya tidak ada jalan keluar yang disepakati, kita bisa melakukan hal yang lain...”
“Apa misalnya?” tanya Zamzami.
“Kita demonstrasi...”
“Demonstrasi?” Kyai Abdullah menyela.
Iman kemudian menjelaskan bahwa demonstrasi adalah salah satu cara menjelaskan kepada masyarakat tetang sebuah sikap, juga sebuah keputusan. Demonstrasi diperbolehkan dalam demokrasi. “Dalam demonstrasi itu nanti ada negosiasi-negosiasi...” katanya.
Zamzami berdecak kagum dengan apa yang dijelaskan oleh Iman sejak beberapa hari ini sejak dia kembali dari Pekanbaru. “Kamu banyak dapat ilmu, Iman. Tapi apakah warga kita mengerti dengan ide-ide dan gagasanmu?”
“Tugas kitalah memahamkan kepada mereka...”
Namun esok malamnya, sebuah mobil Rocky berhenti tepat di depan mushalla ketika mereka akan melakukan shalat Isya. Lima orang berbadan kekar turun dan langsung menuju pintu mushalla. Kyai Abdullah yang berdiri di depan pintu kemudian bertanya apa maksud kedatangan mereka. “Jika Saudara-saudara bermaksud baik, silakan masuk ke dalam mushalla...”
Salah seorang dari mereka yang berjaket kulit hitam mengatakan bahwa mereka tersesat. “Sejak sore tadi kami mencari jalan tembus yang bisa ke Desa Pontian Gondan, tetapi tidak ketemu. Akhirnya kami malah sampai ke desa ini,” katanya dengan suara berat.
“Kalau begitu, silakan masuk. Inilah Desa Pontian Gondai itu...” kata Kyai Abdullah.
“Terima kasih, Kyai. Kami akan kembali ke Ukui malam ini, terima kasih atas sambutannya...”
Kelimanya kemudian masuk ke dalam mobil lagi, dan beberapa saat kemudian mobil itu melaju meninggalkan mushalla, juga desa. Zamzami, Zamroni, Iman juga Masri yang ada di dalam mushalla, dari tadi menyimak pembicaraan Kyai Abdullah dengan orang-orang berbadan kekar itu. Dalam kepala Iman, dia yakin, mereka bukan tersesat, tetapi sengaja datang ke kampungnya, dan itu pasti ada hubungannya dengan perusahaan sawit itu.
“Tidak mungkin mereka tersesat, Kyai. Jalan menuju kampung ini langsung lurus dari simpang Ukui. Ini pasti ada hubungannya dengan pembicaraan kita selama ini...” kata Iman.
“Sebelum Iman pulang dari Pekanbaru, sudah lama kita tidak membicarakan tentang upaya kita untuk melawan mereka. Dan sekarang, ketika kita sering berkumpul di mushalla ini, tiba-tiba ada orang tak dikenal datang ke kampung kita. Ini pasti ada apa-apanya. Dan mungkin mereka juga sudah mempunyai orang yang mereka jadikan sebagai mata-mata di kampung ini,” kata Zamzami.
“Artinya, mulai hari ini kita harus lebih waspada lagi. Juga, bahwa apa yang akan kita lakukan ini akan mengandung resiko,” kata Kyai Abdullah.
“Kita memang harus siap dengan segala resiko atas apa yang akan kita lakukan...” terdengar suara Iman agak berat.
Masri, adiknya, yang berada tidak jauh darinya, dari tadi selalu melihat abangnya dengan seksama. Dalam pikirannya, abangnya memang telah benar-benar berubah sejak lima tahun menghilang. Abangnya telah memposisikan dirinya sebagai seorang laki-laki yang telah melakukan sesuatu untuk hal yang memang harus dilakukan. Dia ingat bagaimana beratnya deraan yang harus diterima abangnya ketika ia masih kecil, ketika dia sendiri ketika itu belum tahu apa-apa tentang tanggung jawab, juga kewajiban. Tetapi kini abangnya telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang merasa memiliki martabat. Dia senang melihat apa yang terjadi dengan abangnya, tetapi bersamaan dengan itu, dia juga menjadi resah. Apakah masa kecil yang berat itu telah membentuk pribadi Iman menjadi pemarah, pendendam dan emosional meski itu tidak ditujukan kepada bapaknya?
Seminggu kemudian, Iman bersama Zamzami pergi ke Ukui, ke kantor perwakilan perusahaan sawit itu di sana. Namun, tak ada pegawai kantor itu yang mau melayaninya. Dia diopor ke sana-sini dan akhirnya sampai kepada bagian lapangan. Dia mengatakan bahwa penduduk kampungnya akan bertahan apapun yang terjadi.
Manajer lapangan itu, seorang lelaki yang dia tak ingin peduli siapa dan dari mana asalnya, mengatakan bahwa mereka memiliki bukti hukum yang bisa dipertanggunjawabkan di manapun. “Kami memiliki dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan itu sah. Mau dibawa ke pengadilan atau ke manapun, kami tak akan takut. Terserah Anda, jika penduduk kampung Anda tak mau mengosongkan kampung, kami memiliki cara sendiri...”
Sebelum orang itu menyelesaikan bicaranya, dia sudah naik ke meja dan dengan cepat menendang kepala lelaki itu. Zamzami yang duduk di dekatnya, terkejut, namun terlambat sebab beberapa saat kemudian, lelaki itu sudah menjadi bulan-bulanan Iman dengan pukulan dan tendangannya. “Kau tak tahu siapa kami. Tanah adalah hidup kami, dan dengan nyawa kami akan mempertahankannya,” katanya masih dengan menghajar lelaki itu.
Zamzami yang berusaha melerai, tidak mampu menghentikan Iman. “Apa yang kita lakukan bisa menjadi permasalahan besar, Iman. Hentikanlah,” katanya sambil menarik tubuh Iman.
“Dia menghina kita. Dia menghina apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Mereka berjuang keras membuka hutan itu menjadi perkampungan, dan kini dia mengatakan pekerjaan itu sia-sia. Sialan!” katanya sambil melayangkan pukulan ke sekian kalinya ke hidung lelaki itu. Terlihat, manajer lapangan itu babak-belur. Seluruh mukanya dilumuri darah yang keluar deras dari hidungnya. Dia terlihat megap-megap, tidak bisa bicara apa-apa selain mengaduh kesakitan.
Benar, beberapa saat kemudian beberapa petugas keamanan perusahaan masuk dan balik menghajar Iman, juga Zamzami. Mereka berdua berusaha melawan, tetapi jumlah petugas itu sangat banyak dan akhirnya dia dan Zamzami benar-benar menjadi bulan-bulanan mereka. Keduanya kemudian dibawa ke ruangan lain dan masih dihajar di sana hingga pingsan. Beberapa jam kemudian polisi datang dan keduanya dibawa ke pos polisi untuk diperiksa. Akhirnya, setelah melalui pemeriksaan hingga malam, Iman ditahan, sementara Zamzami dilepaskan.
Berita itu menyebar ke kampung dan sampai ke telinga bapaknya, juga ibu dan dua adiknya. “Dia ingin memperlihatkan bahwa dia benar-benar laki-laki, tetapi dia tidak perhitungan dan pikirannya dikuasai emosinya...” kata bapaknya dengan suara lemah sambil terbatuk-batuk yang didengar oleh Masri.
“Apa yang harus kita lakukan, Pak?” tanya Masri, agak cemas.
“Abangmu bisa menyelesaikan sendiri persoalannya. Dia akan lebih dewasa dengan apa yang terjadi padanya sekarang.”
“Tapi dia sendirian, Bapak... Saya mohon, kita harus membantu abang...”
Ahmad Jaidi, lelaki yang terkulai lemas dan bicaranya satu-satu itu, terbatuk dan kemudian mengatakan bahwa kesendirian itulah yang membuat Iman akan tahu bahwa hidup harus diperjuangkan. “Dia akan kuat dengan itu...”
“Tetapi dia sendiri, Bapak... Saya mohon, kita harus membantunya...” terdengar pilu suara Masri. Sementara di ruang tengah rumah papan itu, seorang wanita menangis tanpa suara, hanya isak. Siti Mudrika, ibu Iman, Masri dan Rizaldi, istri dri Ahmad Jaidi, hanya bisa menangis diam dan dalam hati, hanya isak yang keluar, juga air matanya yang mengalir deras. Dia mengenal suaminya sejak masih remaja, tetapi mengapa sebegitu keras hatinya, bahkan ketika anaknya berada dalam masalah sebesar ini?
Terdengar ketukan di pintu. Masri kemudian membukanya dan melihat Kyai Abdullah bersama beberapa penduduk kampung sudah berdiri di sana. “Kami akan ke kantor polisi di Ukui. Kami akan membawa seluruh laki-laki di kampung ini ke sana untuk membebaskan Iman. Percayalah, kami akan membawanya pulang lagi...”
Dengan sebuah truk milik kepala kampung, mereka pergi ke Ukui. Setibanya di sana, Kyai Abdullah dan dua orang penduduk masuk ke dalam menemui Kepala Pos Polisi. Kapolpos itu mengatakan bahwa Iman tak mungkin bisa dibebaskan karena perbuatan yang dilakukannya adalah kriminal berat, yakni penganiayaan dengan kekerasan. Negosiasi dilakukan dengan alot dan keputusannya tetap, Iman tidak bisa dibebaskan. Suasana malam itu semakin panas. Warga kampung mulai marah dan entah siapa yang memulai, tiba-tiba mobil patroli milik pos polisi itu sudah dilalap api. Tak lama kemudian, pos polisi itu dilempari botol-botol minyak yang diberi sumbu dan kemudian api berkobar. Beberapa polisi jaga tidak bisa menghentikan meski mengancam akan menembak, tetapi tak satu tembakan yang keluar. Mereka memilih melarikan diri dan Kyai Abdullah bersama beberapa orang kemudian masuk ke dalam sebelum api benar-benar membesar. Mereka menemukan Iman dalam keadaan tak berbentuk, seluruh badannya memar dan kondisinya benar-benar kritis.
Mereka kemudian membawa Iman ke dalam truk, dan rombongan itu kembali ke kampung. Hampir tengah malam mereka sampai dan Iman dibawa ke mushalla dan di sana Kyai Abdullah membantu Iman yang sudah sadar dengan memberikan air putih yang sudah diberi bacaan ayat-ayat Alquran. Iman mengalami luka parah di beberapa tempat. Pukulan benda-benda tumpul sepertinya hinggap di kaki, dada, pinggang dan hampir seluruh tubuhnya. Terlihat darah kental di hidung dan bibirnya, nampaknya dari dua tempat ini tadi mengucur darah segar. Dia mendengar semua apa yang dikatakan orang sekelilingnya, namun dia tak bisa berbuat apa, tak bisa berbicara, apalagi bergerak. Dia juga tahu ibu dan dua adiknya ada di situ menangisinya, tetapi dia benar-benar tak bisa berbuat apa-apa.
Melihat kondisi Iman yang kritis itu, menjelang Subuh, Kyai Abdullah dibantu dua laki-laki lainnya membawanya keluar dari kampung dengan sebuah mobil colt tua bekas milik Marno yang dibelinya dari istri Marno. Mereka tidak melewati simpang Ukui, tetapi lewat jalan-jalan di bawah pohon sawit menuju Air Molek. Di sana, di sebuah klinik kecil, Iman diobati seperlunya. Namun karena kondisinya sangat kritis, pihak klinik kemudian merekomendasikan agar Iman dibawa ke Padang, di rumah sakit umum M Jamil.
“Untuk sampai di Padang perlu waktu 8 jam, Dokter,” kata Kyai Abdullah.
“Iya, tetapi fisiknya sangat kuat, selama di perjalanan nanti akan ada perawat yang mendampinginya...”
Iman kemudian benar-benar dibawa ke sana dan dirawat dengan baik dengan biaya dari Kyai Abdullah yang selama ini memang dikenal sebagai pedagang getah yang lumayan maju.
BEBERAPA pekan kemudian Iman sudah dinyatakan sembuh. Kyai Abdullah mengatakan bahwa polisi akan tetap mengejar Iman dan penduduk lain yang terlibat pembakaran pos polisi di Ukui. “Kamu menyingkir dulu. Pergilah ke Jawa atau ke mana...”
“Saya tidak akan pergi ke mana-mana, Kyai...”
“Percayalah pada saya... Kamu akan lebih baik menyingkir dulu. Saya yang akan menanggung semuanya jika memang terjadi apa-apa...”
“Saya tidak mau orang yang tidak terlibat apa-apa menjadi tumbal apa yang saya lakukan... Lagi pula, polisi pasti akan tetap mengejar saya di manapun saya berada...”
“Tidak. Kasus itu akan dingin bersama waktu. Kamu masih muda, masih banyak yang bisa kamu lakukan ketimbang mendekam di tahanan...”
“Tiga atau empat bulan tidak berarti apa-apa bagi saya di tahanan, Kyai...”
“Pergilah!” terdengar suara Kyai Abdullah meninggi. “Saya tahu apa yang ada dalam hati dan pikiranmu. Kamu mau menunjukkan kepada bapakmu bahwa kamu juga bisa menderita seperti ini, termasuk di dalam penjara seperti yang dilakukan oleh bapakmu, kan? Kamu marah kepada bapakmu dan kamu ingin menunjukkannya dengan cara itu! Ketahuilah, apa yang dilakukan oleh bapakmu dengan mendidik kamu dengan cara keras sejak kecil, adalah karena dia sayang kepadamu...”
“Saya tahu, Kyai. Saya tidak dendam kepada bapak...” terdengar suaranya lirih.
“Maka, pergilah. Jika harus masuk tahanan, biar saya yang menggantikanmu, Nak...”
Iman memeluk Kyai Abdullah dan menangis sesenggukan. “Kami semua menyayangimu, Nak. Percayalah...”
Kyai Abdullah kemudian membawa Iman ke Indarung untuk naik bus menuju Jakarta. Seluruh biaya dan uang saku, Kyai Abdullah yang menanggungnya. “Jagalah dirimu...”
“Saya titip keluarga saya, Kyai...”
“Ya...” Ada yang basah di pipi Kyai Abdullah ketika melihat Iman sudah berada di atas bus.
Iman naik bus ANS menuju Jakarta. Kyai Abdullah percaya, meski tak pernah ke Jakarta, Iman akan bisa bertahan hidup di sana dengan cara apapun. Dia percaya dengan Iman, sepenuhnya. Dia merasa dekat dengan Iman sejak mereka sama-sama merencanakan tentang upaya untuk mempertahankan tanah dari incaran perusahaan sawit itu. Dan dari situlah dia tahu psikologis Iman. Tentang hubungannya dengan bapaknya, Ahmad Jaidi, dan perasaan sayangnya kepada ibu dan kedua adiknya.
SETELAH sekitar sebulan berada di Jakarta –Iman tinggal di rumah seorang teman kuliahnya, anak Jakarta yang kuliah di Unri— dia mendapat kabar itu dari Kyai Abdullah. Bahwa keadaan di Ukui sudah lumayan tenang. Dia dan beberapa penduduk ditahan selama tiga pekan dan kemudian dilepaskan karena peristiwa pembakaran itu dianggap amuk massa yang tiba-tiba tanpa komando siapapun. Hanya saja, kata Kyai Abdullah dalam suratnya, polisi masih berusaha mencari Iman, meski belakangan sudah tak terdengar lagi kabar tentang itu.
“Hanya saja Iman, saya tahu kamu laki-laki yang kuat. Hanya beberapa hari setelah kamu berangkat ke Jakarta, tanah kita telah menerima dengan baik bapakmu. Penyakit TBC yang dideritanya tak bisa ditahan dan sebelum meninggal, dia sempat meminta agar ibumu menyampaikan permintaan maafnya kepadamu. Ketika dia mendengar kamu ditahan, penyakitnya semakin memburuk. Ikhlaskan dan maafkan bapakmu, dia sangat mencintaimu, dan dia mengatakannya dengan cara yang berbeda agar kamu benar-benar menjadi laki-laki yang kuat seperti yang diinginkannya. Tentang ancaman perusahaan sawit itu, percayalah, kami akan bertahan semaksimal mungkin. Jangan pulang dulu sebelum ada kabar bahwa keadaan benar-benar aman...”
Dia tak bisa menahan air matanya. Dia menangis terisak malam itu saat membaca surat itu sampai akhir. Aku tak pernah dendam kepada bapak, dan aku tak pernah marah kepadanya... Apa yang dilakukannya kepadaku telah banyak membantuku dalam banyak hal. Aku mencintai bapak, seperti aku juga mencintai ibu dan dua adikku. Aku tak perlu memaafkannya, karena bapak tidak pernah bersalah. Jika harus dicari siapa yang bersalah, maka akulah orangnya. Aku melarikan diri dari realitas, aku tak mampu memenuhi janjiku untuk membantu memebebaskan kampungku dari ancaman perusahaan sawit itu. Aku yang salah, dan aku akan membawa kesalahan itu ke manapun aku akan berjalan...
Epilog
AKU tak tahu, mengapa segala yang berhubungan denganmu juga berhubungan dengan malam dan hujan, Iman. Ketika aku mendengar kabar itu, juga sedang hujan dan badai. Kabar yang selalu memberikan kepedihan meski aku bahagia ketika mengenang segala saat bersamamu. Aku tak percaya ketika itu, saat seseorang yang aku sendiri tak mau tahu siapa dia, datang ke rumah saat hujan dan mengabarkan tentangmu. Seorang laki-laki ditemukan mati di pinggir rel kereta api dekat stasiun dan di tangannya masih memegang bunga mawar yang sudah mulai layu meski basah oleh hujan yang deras. Tak ditemukan apa-apa di kantongnya, selain alamat rumahku.
Mulanya aku tak percaya, tetapi kemudian aku menangis diam saat melihat tubuhmu memucat di ruang mayat rumah sakit itu. Kata dokter yang mengotopsimu, paru-parumu sudah rusak. Kamu mengidap TBC, seperti juga bapakmu, dan selama ini aku tak pernah berusaha mencari tahu. Di mulut dan bajumu tersisa bercak darah. Mungkin kau batuk dan muntah darah sebelum ajal menjemputmu. Dokter juga mengatakan bahwa mawar yang ada di genggamanmu tak ada yang bisa mengambilnya. Dan ketika kubuka genggaman tanganmu, dengan mudah aku bisa mengambilnya.
“Mungkin dia ingin memberikan bunga itu kepada Nona,” kata dokter yang aku juga tak peduli dengan namanya itu.
Malam dan hujan selalu menyimpan segala cerita tentangmu. Namun segala yang pernah hidup denganmu tetap berada di sini: hujan, malam, mawar yang hampir layu dan mungkin bau bacin getah karet yang sering tiba-tiba datang dan tak tahu berasal dari mana...
Aku benar-benar merindukanmu di segala saat. Semoga segala tawa, penderitaan, sakit, senyum, kesedihan dan kemuraman akan menjadi segala kebaikan yang akan mengantarkanmu pada takdirmu. Aku merindukanmu, kini, esok dan segala waktu yang masih tersisa...***
Pekanbaru, Juli 2005
[1] Salah satu lirik lagu Immortality yang dipopulerkan oleh Celine Dion.
Catatan: Novel ini mendapat hadiah Penghargaan Ganti Award II 2005 di Pekanbaru (Riau)
Subscribe to:
Posts (Atom)