Cerpen Hary B Kori’un
MEMANG, aku sendiri semula tidak percaya dengan cerita dari mulut ke mulut yang berkembang begitu luas di seluruh kota. Bahwa wanita itu benar-benar ada, benar-benar hidup dan selalu menyanyikan lagu sedih, kadang lagu populer, jazz, kadang juga dangdut. Dia selalu mendatangi tempat-tempat di mana ada musik dimainkan; mulai dari panggung organ tunggal di tempat-tempat kawinan, sampai ke pub-pub yang berada di pusat kota. Suaranya merdu dan mengundang ngilu bagi yang mendengarkannya. Namun, bukan itu yang membuat aku dibuat penasaran.
“Dia cantik. Wajahnya segar dengan pipi bersemu merah, tatapan mata yang sendu, bibirnya merah muda dan membasah, bodinya tinggi langsing dengan buah dada yang seimbang: tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu rata, betisnya seperti kaki belalang, rambutnya panjang sepunggung. Tapi…”
“Tapi kenapa?” tanyaku antusias dan tak sabar ketika mendengar cerita itu dari temanku.
“Dia terluka.”
“Terluka? Luka betulan?”
“Ya. Luka betulan, di dadanya…”
“Di dadanya?”
“Ada pisau kecil yang menancap di dadanya, persis di antara dua payudaranya. Ada warna merah darah yang membasahi gaunnya, dan meskipun dia berganti-ganti gaun, pisau itu tetap menancap di sana…”
“Mengapa tidak dicabut?”
“Entahlah. Menurut kabar yang kuperoleh, dia sudah berusaha sendiri mencabut pisau itu, namun tidak bisa. Puluhan bahkan ratusan bidan di puskesmas dan dokter-dokter bedah hebat juga tak bisa mencabutnya, meski dilakukan operasi bedah sekalipun. Mungkin rasa sakit karena pisau itu yang membuat dia selalu menyanyikan lagu-lagu sedih setiap dia bernyanyi di manapun. Suaranya sangat merdu, tetapi menyayat hati. Sekali-kali, kamu harus melihat wanita itu sendiri, lihatlah dadanya, dengarkan suara sedihnya yang membuat hati kita ngilu…”
“Oooo…”
Aku benar-benar penasaran. Suatu malam yang gerimis, aku pergi ke sebuah kafetaria yang tidak terlalu ramai di pusat kota. Ketika aku masuk, suasana cukup meriah, meski tak ada suara yang keras terdengar. Banyak pasangan muda-mudi yang berada di sana. Ada yang duduk berhadapan sambil berpegangan tangan dan cerita tentang mawar yang indah, segar, sambil sesekali berbisik. Aku mendengarnya, “Semoga cinta ini tidak berakhir, Sayang…” Di sudut lain, sepasang kekasih yang sangat serasi –yang lelaki gagah dan ganteng dan si wanitanya mirip Luna Maya-- juga sedang menaburkan bunga melati dengan aroma cinta yang menebar ke mana-mana, “Semoga cinta kita abadi. We don’t say goodbye… With all my love for you…” Aku benar-benar iri. Hampir seluruh yang ada di pub tersebut berpasangan: lelaki dan wanita, dan hampir tak ada yang datang sendirian. Aku yang sendirian.
Teman-temanku mengatakan, dia pernah melihat wanita itu menyanyi di kafe itu. Dia menyanyikan lagu cinta yang patah. Cinta yang remuk dan hancur, yang selalu dibawanya ke manapun pergi, dengan darah yang selalu menetes di dadanya, karena sebuah luka akibat pisau kecil yang selalu menancap di sana.
Tiba-tiba, di atas panggung yang nampak remang-remang karena cahaya yang dibuat sedemikian rupa, seorang wanita duduk di sebuah kursi yang agak tinggi dengan membawa sebuah gitar akustik. Aku tidak tahu apakah wanita ini yang sering dikatakan teman-temanku; wanita yang selalu menyanyikan lagu sedih, dengan pisau kecil menancap di dadanya. Namun, dari bisik-bisik banyak orang di situ, aku berkesimpulan, mungkin benar wanita ini. Tetapi, adakah benar ada pisau kecil yang menancap di dadanya? Dari jarak pandang sekitar sepuluh meter dan cahaya lampu yang remang-remang, aku tidak bisa melihat hal itu. Namun, bisikan-bisikan mereka yang sepertinya pernah melihat wanita itu bernyanyi, benar mengarah ke situ.
“Kasihan dia, sepanjang hidupnya dilalui untuk membawa lukanya,” kata seseorang dengan suara pelan, nyaris berdesis, yang berada di samping kananku.
“Lelaki yang mengkhianatinya sungguh keterlaluan. Kurang apa baiknya dia?” kata yang lainnya.
“Mungkin dia bukan dikhianati kekasih atau suaminya. Mungkin dia kehilangan pegangan hidup karena keluarganya menjadi korban peristiwa kerusuhan yang pernah membakar kota…”
“Ah, itu sudah lama sekali. Tak mungkin…”
“…”
Aku mendengarkan semua bisik-bisik itu, hingga kemudian semuanya diam ketika suara wanita itu terdengar di mikrofon. “Saya berdiri di sini, bukan hendak mengajak Anda semua ikut bersedih. Ini mungkin garis nasib saya…” Suaranya sangat indah, merdu dan segala yang indah lainnya yang tak dapat kucari padanannya. Kemudian terdengar sebuah lagu sendu keluar dari mulutnya. What can I do about it, now it's all over…
Semua yang ada di kafe itu, juga aku, terasa tersihir dengan lagu yang sangat populer itu. Bahkan ketika kemudian wanita itu pergi dan tak ada lagi di panggung, aku –juga orang-orang itu— masih belum menyadarinya. Hingga kemudian, kami sama-sama seperti dibangunkan dari kelenaan, kami seperti dibangunkan dari tidur, dari mimpi muram, namun terasa indah. Anehnya, kami semua, juga aku, hampir bersamaan mengusap air yang meleleh di pipi kami masing-masing. Kami menangis, tetapi tak tahu untuk apa dan karena apa.
Ya, aku tak menemukan wanita itu ada di panggung, sehingga aku tidak bisa memastikan apakah benar wanita itu wanita yang diceritakan oleh temanku. Dari jarak sepuluh meter dari tempat dudukku dan cahaya lampu yang remang-remang, aku benar-benar tidak bisa memastikan apakah wanita itu benar-benar terluka dengan pisau kecil menancap di dadanya, persis di antara dua payudaranya yang seimbang: tidak terlalu besar dan tidak terlalu rata itu, meski aku juga tidak bisa melihat jelas seberapa besar ukuran ‘tidak terlalu besar dan tidak terlalu rata’ itu.
***
SIAPA yang percaya dengan cerita ini? Kamu pasti tak percaya, sebab aku sendiri masih belum percaya sepenuhnya meski aku melihat dan mendengarkan sendiri wanita dengan pisau menancap di dadanya itu. Dan ketika bertahun-tahun kemudian aku menjauh dari kota tempat wanita itu, kenangan dan ingatan tentangnya juga tak pernah hilang. Aku tidak tahu, mengapa ingatan itu begitu lekat, bahkan secara detil aku masih ingat persis –meski ketika itu aku melihatnya dari jauh dan dari remang cahaya lampu pub— bahwa benar-benar ada yang luka pada wanita itu.
Suatu pagi, seorang teman di kantor mengabarkan bahwa dia melihat wanita dengan pisau yang menancap di dadanya dan suka menyanyikan lagu sedih itu. “Benar. Ketika kamu pernah becerita tentang wanita itu, dulu aku tak percaya. Tapi tadi malam, ketika aku minum di bar, wanita itu benar-benar ada dan menyanyikan lagu sedih yang membuat semua yang hadir di situ meneteskan air mata. Suaranya seperti menyihir, merogoh jantung dan hati seluruh yang hadir dan membuat semuanya bersedih...”
“Kamu mengarang. Wanita itu berada di kotaku, Pekanbaru, beberapa tahun lalu, dan jaraknya dari sini ribuan kilometer. Tak mungkin dia berada di kota ini sekarang,” kataku.
“... dan meneteskan air mata. Di dadanya ada pisau kecil yang menancap di antara payudaranya, dan selalu meneteskan darah segar. Tetapi dia tidak menghiraukannya, dan dia masih terlihat cantik meskipun dengan pisau dan darah itu. Tetapi aku tahu, bukan hanya dadanya yang sakit, pasti seluruh hidupnya selama ini juga dirudung kesakitan...”
Ingatan tentang wanita itu semakin lekat di kepalaku dan membuat aku kemudian keluar rumah menuju stasiun. Entah mengapa, tiba-tiba aku ingin pergi menjauh dari kota ini, dari cerita tentang wanita itu. Aku merasa tak mampu mendengarkan cerita tentangnya, apalagi melihat wajahnya lagi. Aku pergi ke kota lain dan menetap di sana. Namun, selalu saja di kota baru yang kusinggahi, aku selalu mendengar cerita tentang wanita dengan pisau yang menancap di dadanya dan selalu mengeluarkan darah segar itu.
Hingga akhirnya aku memilih berhenti mengembara menjauhinya dan kembali ke kotaku di mana cerita awal tentang wanita itu muncul beberapa waktu lampau. Namun, ketika kembali ke sana, cerita tentang wanita itu tak pernah berhenti keluar dari mulut orang-orang di kotaku. Hampir semua orang yang kutemui bersedih dan meneteskan air mata: mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, mereka semua mengatakan merasa teriris hatinya ketika mendengarkan wanita itu menyanyi, lagu apa saja.
Aku merasakan, kotaku tiba-tiba berubah menjadi kota yang sedih dan penuh air mata. Tidak ada orang yang tertawa atau tersenyum, semuanya bersedih, menangis dan air matanya tumpah. Ini jelas sebuah bencana. Mengapa kesedihan menular ke mana-mana, dan mengapa semua orang harus menangis ketika mendengarkan ia menyanyi, sedang dia sendiri tidak menangis dan sepertinya kuat dengan penderitaannya itu?
***
KOTAKU kemudian menjadi sebuah kota yang aneh. Dan anehnya, wabah kesedihan ini juga menjalar di kota-kota lain, kota-kota yang pernah disinggahi oleh wanita itu. Dan yang membuat sangat aneh, semuanya dalam saat yang bersamaan. Apakah wanita dengan pisau menancap di dadanya itu lebih dari satu orang?
“Tidak, dia cuma satu orang. Dia tidak ke mana-mana, tetapi dia berada di mana-mana,” kata seorang kyai yang sempat bercerita denganku di sebuah masjid.
“Kesedihannya sudah menjadi kesedihan semua orang,” kata seorang pastor ketika aku lewat di depan sebuah gereja.
“Di setiap tempat di mana dia menyanyi dan darahnya sempat menetes di sana, dipastikan masyarakatnya pasti bersedih...” yang ini kata seorang ahli sosiologi yang aku sendiri tidak peduli siapa namanya.
“Jika dibiarkan dan tak ada penanganan secara sungguh-sungguh, seluruh dunia akan bersedih karena hampir semua televisi menyiarkannya. Orang yang melihat di televisipun akan menangis dan bersedih. Dan jika itu terjadi, dampaknya akan lebih dahsyat dari Perang Dunia atau krisis ekonomi dunia,” kata seorang ahli politik nasional ketika berpidato di televisi.
Banyak komentar lagi dari berbagai kalangan, mulai dari rohaniawan, politikus, olahragawan, musisi, ekonom, psikolog dan lain sebagainya. Intinya, mereka menyerukan agar kesedihan wanita itu dihentikan, dan dia tidak diberi izin untuk bernyanyi dan darah yang menetes dari dadanya tidak boleh menyentuh tanah. Tetapi, bukankah ini akan melanggar hak asasi wanita itu? “Tidak, ini tidak melanggar HAM karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata salah seorang pakar HAM.
***
SUATU ketika, aku menemui wanita itu dan berbicara dengannya beberapa saat setelah dia bangun pagi dan aku sengaja menungguinya di depan pintu rumahnya.
Aku heran, dia terkejut ketika melihat wajahku dan mengatakan untuk apa aku datang lagi. “Kita memiliki kehidupan masing-masing. Aku tidak menggangu kehidupanmu lagi, dan jangan ganggu kehidupanku...” katanya dengan suara sedih. Aku melihat, memang pisau kecil itu benar-benar menancap di dadanya, tetapi dia tetap segar dan tidak pucat sebagaimana orang yang darahnya bertahun-tahun menetes.
“Kita? Bukankah kita tak pernah saling jumpa?” Aku benar-benar dibuatnya terkejut karena tak menyangka dengan apa yang dikatakannya.
“Kau pernah mengatakan kepadaku bahwa cintamu akan kau berikan kepada semua orang saat aku mengatakan jatuh cinta kepadamu. Dan setelah itu aku mencoba bunuh diri dengan pisau ini. Tetapi pisau ini tak bisa membunuhku, hanya melukaiku, dan aku tak bisa mencabutnya kembali. Aku sedih, sepanjang hidupku kuisi dengan caraku...”
“Pasti bukan aku laki-laki yang membuatmu jatuh cinta itu...”
Dia mengamati wajahku. Dia memegang telinga kiriku dan kemudian melihat bagian belakangnya. “Kaulah lelaki itu. Ada tahi lalat di belakang telingamu, dan aku juga masih merasakan bau tubuhmu hingga kini...”
“Bukan aku! Sepanjang hidupku aku tak pernah bisa membuat seorang wanita jatuh cinta! Aku juga tak pernah bisa jatuh cinta kepada siapapun...”
“Kau memang selalu mengatakan itu kepadaku, dulu...”
Ketika aku membalikkan badan dan keluar dari pintu pagar rumahnya, aku mendengar isaknya. Tetapi aku tetap pergi dan merasa aku tak pernah mengenalnya kecuali hanya pernah melihatnya bernyanyi di pub malam itu...
***
BEBERAPA bulan kemudian, wanita itu tak terdengar lagi kabarnya. Dia tidak lagi menyanyi dan lambat-laun wabah sedih yang melanda beberapa kota pun terhenti. Aku tak tahu apa sebabnya, tetapi seorang dokter yang merawatku mengatakan bahwa wanita itu memang telah berhenti menyanyi dan pisau kecil di dadanya sudah bisa dicabut oleh seseorang yang tak pernah diketahui identitasnya.
“Mungkin laki-laki yang dicintainya itu yang membuat dia bersedih. Tapi tidak ada yang tahu siapa laki-laki itu. Pastilah dia laki-laki hebat, karena selama ini tidak ada dokter yang bisa mencabutnya, meski di meja bedah sekalipun. Menurut kabar lagi, wanita itu sudah hidup normal lagi dan mengajar sastra di sebuah universitas, pekerjaannya dulu sebelum dia mengembara dengan pisau di dadanya...”
Aku tak ingin bercerita apa-apa lagi tentang wanita itu. Ketika aku mendengar kehidupannya sudah normal, aku sangat senang. Kata beberapa perawat yang menjagaku, katanya beberapa kali seorang wanita cantik datang menjengukku saat aku tertidur, dengan ciri-ciri yang bisa kupahami mirip ciri-ciri wanita itu. Tapi aku tak percaya karena aku tak pernah mengenalnya. Sungguh, aku tak pernah mengenalnya dan kami memang benar-benar tak pernah saling mengenal. Bahkan ketika kemudian dokter memvonis umurku hanya tinggal beberapa bulan lagi setelah penyakit aneh yang bersarang di tubuhku ini, aku tetap yakin bahwa aku benar-benar tidak mengenalnya. Tapi, benarkah aku memang sudah melupakan semua masa laluku ketika penyakit aneh itu menyerang otakku dan membuat aku harus terdampar di rumah sakit ini sejak beberapa bulan lalu?
Entahlah. Aku ingin meyakinkan itu sebenarnya, sebelum aku benar-benar tak ingat apapun seperti saat ini.***
Pekanbaru, Juli 2005
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






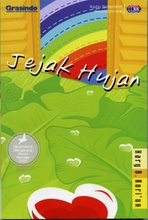

No comments:
Post a Comment