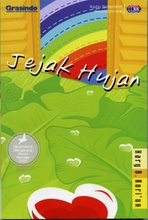Catatan Kecil Hary B Kori’un
DALAM acara diskusi tiga novel pemenang Ganti Award II 2005 (Getah Bunga Rimba [Marhalim Zaini], Jembatan [Olyrinson] dan Malam, Hujan [Hary B Kori’un, pen]) yang diadakan oleh Forum Lingkar Pena (FLP) Pekanbaru di Aula Perpustakaan Wilayah, Sabtu (11/6) lalu, salah seorang peserta yang masih sangat muda, bertanya kepada pembicara; Deded Er Moerad, Marhalim Zaini, Olyrinson dan saya sendiri (penulis). “Tadi, para pembicara mengatakan bahwa ketiga novel yang sedang didiskusikan ini berusaha membumi dan mudah dipahami oleh siapapun. Tetapi bagi saya, karya sastra, termasuk ketiga novel ini, tetap berat dan saya tidak paham apa yang dimaksudkan oleh para pengarangnya...”
Pertanyaan itu sebenarnya ditujukan kepada saya, karena sebelum gadis muda yang masih berseragam sekoah itu bertanya, saya memaparkan dan meyakinkan bahwa novel Malam, Hujan, adalah novel yang mudah dipahami, berusaha menggambarkan waktu dan tempat sedetail mungkin seolah-olah pembaca sedang menonton sebuah film, dan dengan bahasa yang tak perlu mengerutkan dahi. Namun, mendengar itu, saya menjadi mafhum dan berusaha untuk memahami kondisi masyarakat kita secara umum yang memang masih asing dengan buku. Meminjam istilah Seno Gumira Ajidarma, kita menulis di sebuah masyarakat yang tidak membaca (sesuatu yang juga dikatakan oleh Marhalim dalam peluncuran novel-novel ini di Bandar Serai beberapa waktu yang lalu).
Dalam diskusi tersebut, banyak hal yang dipaparkan baik oleh Marhalim, Deded maupun Olyrinson. Marhalim mengejaskan bahwa proses penciptaan novelnya yang kemudian menjadi novel terbaik tersebut, berawal dari kehidupan rutin ketika dia masih berada di kampung halamannya di Teluk Pambang, Bengkalis. Suasana perkampungan, kebun karet, kehidupan yang sederhana dan tenang dan ornamen-ornamen kampung lainnya, merupakan ihwal dari terciptanya ide novel itu. “Saya menulis berawal dari hal-hal biasa di sekitar saya dan ini yang selalu menjadi sumber inspirasi saya, dan untuk menambah pengayaan ide, saya membaca buku dan mempelajari lingkungan yang lain,” jelas pengajar teater di Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR) ini.
Hampir sama dengan Marhalim, Olyrinson juga menciptakan karya dengan ide dari kehidupan sehari-hari. Ide dari novel Jembatan didapatnya ketika dia pulang-pergi dari Pekanbaru-Siak dengan melewati penyeberangan di Perawang. Cerita tentang kehidupan yang biasa ini menjadi istimewa di tangan Oly karena banyak sisi humanis yang dipaparkan. “Saya tidak bisa menulis novel bagus, saya hanya bicara tentang keseharian,” jelas pegawai sebuah perusahaan kontraktor perminyakan ini.
Sementara itu Deded, seniman senior yang pernah lama tinggal di Jogjakarta, Jakarta dan Belanda, menjelaskan bahwa ketiga novel tersebut telah mampu melakukan eksplorasi estetika baik dalam bentuk maupun isi cerita. Deded mengatakan, seorang pengarang harus selalu mencari ide dan estetika dan memberikan pemikiran-pemikiran baru kepada pembacanya. “Kalau seorang pengarang tidak melakukan itu, maka ia akan ditinggalkan pembacanya,” jelas lelaki yang dekat dengan WS Rendra ini.***
BULAN Mei lalu, ketika punya kesempatan ke Surabaya, saya bertemu dengan tiga orang yang sudah eksis di dunia sastra. Mereka adalah mahaguru sastra Pak Budi Darma (saya memanggilnya “Pak” sebagai rasa hormat saya), pengarang produktif Kurnia Effendi yang sedang ada acara di Surabaya dan pengarang wanita Lan Fang yang memang tinggal di Surabaya. Kami ngobrol di rumah Pak Budi di komplek perumahan IKIP Surabaya bersama beberapa rekan yang lain.
Sangat beruntung, untuk keduakalinya saya bisa bercengkrama begitu lama dengan Pak Budi. Pertemuan pertama terjadi di Kayu Tanam, Sumatera Barat pada tahun 1997 saat Pertemuan Sastrawan Nusantara di klompleks INS Kayu Tanam. Ketika itu, saya masih hijau dan baru tumbuh sehingga saya merasa apa yang dijelaskan oleh Pak Budi dan teman-teman lainnya saat itu, terasa sulit saya cerna. Maklumlah, belum banyak buku yang saya baca karena susahnya mendapatkan buku yang bermutu baik di universitas maupun di toko buku. Untuk membeli harganya tak terjangkau oleh kantong mahasiswa, sementara tidak ada kawan yang mau meminjamkan.
Namun, kondisi ini tidak membuat saya patah semangat. Pelan tapi pasti, akhirnya saya mendapatkan beberapa buku Pak Budi seperti Olenka, Rafilus, Ny. Talis dan Orang-orang Bloomington. Belakangan cerpen-cerpennya juga mulai saya gemari seperti Mata yang Indah dan Derabat yang pernah menjadi cerpen terbaik Kompas.
Barangkali, apa yang dikatakan Pak Budi ini ada manfaatnya bagi kita. Dalam sebuah wawancara di jurnal Prosa (2003), lelaki yang selalu tampak santun, rapi, dan lembut tutur-kata ini sekali lagi mengakui, “...saya menulis tanpa saya rencanakan, dan juga tanpa draft. Andai kata menulis dapat disamakan dengan bertempur, saya hanya mengikuti mood, tanpa menggariskan strategi, tanpa pula merinci taktik. Di belakang mood, sementara itu, ada obsesi.”
Dalam perbincangan di rumahnya di malam yang hujan itu, Pak Budi lebih banyak menjadi moderator dan penyimpul diskusi, namun dengan bernas kata-katanya benar-benar mencengangkan. Misalnya, ketika kami diskusi tentang wacana muatan lokal dalam sastra Indonesia, Pak Budi mengatakan bahwa lokalitas sebuah karya itu tak bisa dipaksakan antara lokalitas daerah, lokalitas budaya atau lokalitas pemikiran. “Belum tentu seseorang yang hidup di lokalitas budaya dan daerah yang sama, memiliki lokalitas pemikiran yang sama juga,” katanya. Dia mencontohkan, pluralisme yang tumbuh di Riau. Menurutnya, lokalitas yang bisa diciptakan dengan baik di Riau adalah lokalitas daerah, tetapi tidak bisa dipaksakan lokalitas budaya dan pikiran. “Lokalitas daerah ya Riau itu. Tak bisa dipaksakan orang Minangkabau, Batak, Banjar atau Jawa yang hidup di sana, harus menulis sastra dengan latar belakang lokalitas budaya Melayu,” kata Pak Budi ketika itu.
Kembali ke pokok awal masalah tadi, bahwa apa yang dijelaskan oleh Pak Budi bagaimana proses penciptaannya, merupakan contoh bagaimana seorang pengarang menggarap ide-ide yang berbeda. Pak Budi sendiri mengakui, meski dia sudah lama tinggal dan menetap di Surabaya, namun dia sangat tidak fasih berbicara tentang kebudayaan yang berkembang di Surabaya, termasuk persoalan sosiologis masyarakat Jawa Timur yang berbeda dengan masyarakat Jawa Tengah di mana dia lahir di Rembang. Tipe masyarakat Jawa Timur cenderung terus terang dan keras, sementara Jawa Tengah lebih tertutup, mengutamakan sopan-santun dan bicara dengan lembut. “Tapi dalam proses penciptaan, saya kira seharusnya pengarang tidak harus memikirkan batasan-batasan karena itu akan memasung proses kreatifnya,” kata Guru Besar IKIP Surabaya ini.***
BEGITU keluar dari rumah Pak Budi, baik saya, Kurnia Effendi maupun Lan Fang sepanjang jalan merasakan ada hal besar dan banyak yang kami dapatkan. “Ini bedanya orang-orang muda dengan mereka yang sudah lama makan asam-garam hidup. Pak Budi banyak berkarya, dan sedikit bicara,” kata Kurnia, pengarang yang sudah menerbitkan banyak buku novel maupun kumpulan cerpen seperti Senapan Cinta, Bercinta di Bawah Bulan, Selembut Lumut Gunung, Aura Negri Cinta dan sebagainya itu.
Kurnia Effendi adalah generasi pengarang seangkatan Gus tf Sakai yang memulai menulis cerita remaja dan dimuat di Majalah Gadis, Anita Cemerlang, Aneka Ria atau Ceria Remaja. Seperti juga Gus, Kurnia juga sering memenangkan berbagai sayembara penulisan cerita (cerpen dan novel) remaja. Seiring pertumbuhan usia, keduanya juga merambah sastra serius dan karya-karyanya mulai menembus media serius seperti Horison, Kompas, Republika, Media Indonesia dan akhirnya mendapat pengakuan secara luas. “Bagi saya, menulis tak perlu memilih genre. Saya menulis apa saja yang bisa ditulis dan dikirimkan ke media yang sesuai dengan tulisan itu,” katanya suatu kali.
Akan halnya Lan Fang. Perempuan berdarah Cina ini selama ini eksis dengan dunia kepengarangan ketika cerpen maupun cerita bersambungnya memenangkan lomba yang diadakan oleh Majalah Wanita Femina atau Kartini dan beberapa novelnya yang telah menjadi buku seperti Kembang Gunung Purei, Pai Yin hingga kumpulan cerpen terbarunya, Lelaki yang Salah. Wanita kelahiran Banjarmasin ini mengakui bahwa proses kepengarangannya dilalui tanpa mencari kerumitan. “Pokoknya saya menulis cerita, banyak yang dimuat media, banyak juga yang ditolak. Tetapi saya terus menulis,” katanya.
Sebenarnya, apa yang saya tulis ini, hanya ingin memberi gambaran bahwa dunia kepenulisan itu tidak terlalu rumit, asal kita terus mau mencoba dan mencoba, termasuk membaca dan membaca. Seorang pengarang yang baik adalah ketika karyanya bisa berkomunikasi dengan pembacanya, sementara seorang pembaca yang baik adalah ketika dia bisa berkomunikasi dengan bacaannya tanpa harus mencari pemahaman dari yang lain. Semakin bingung, kan?***
Saturday, February 23, 2008
Subscribe to:
Comments (Atom)